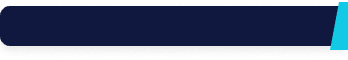Kenapa Sekolah Akan Terdisrupsi? (1)

Kenapa Sekolah Akan Terdisrupsi? (1)
A
A
A
Minggu ini anak-anak kita kembali masuk sekolah setelah liburan panjang yang sekaligus menandai dimulainya tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru 2017 ini agak berbeda karena diliputi kontroversi dan blunder kebijakan full day school (FDS) yang mengubah waktu sekolah menjadi lima hari dan delapan jam per hari.
Kebijakan blunder untuk sekian kali seperti ini (”beda menteri, beda pula blundernya”) menjadi wake-up call . Betapa kalau sekolah-sekolah kita terus dikelola dengan pendekatan BAU (business as usual ) semacam ini pada akhirnya akan menjadi obsolet alias usang, kian tak relevan, dan akhirnya masuk museum.
Dengan begitu, tak hanya tukang ojek pangkalan yang terkena disrupsi Go-Jek atau operator taksi yang terkena disrupsi Uber, saya khawatir sekolah-sekolah kita juga akan menjadi korban disrupsi berikutnya. Berikut ini adalah empat alasan substantif kenapa sekolah-sekolah kita bakal terdisrupsi jika kita terus-menerus ”gagal paham”, tidak peka, tidak agile, dan tidak cepat merespons gelombang disruptive change yang kini sedang menyapu lanskap pendidikan kita.
#1. Neo-Milennials: The Prime Disruptor
Disruptor paling utama sekolah, menurut saya, bukanlah digital apps, sharing platform, atau algoritma-AI (artificial intellegence ) yang super canggih, tapi adalah konsumen dari sekolah, yaitu murid. Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, kita mendapati sebuah generasi yang terlepas sama sekali (decoupling) dengan generasi-generasi sebelumnya (Silent, Baby Boomers, Gen X) yang disebut Generasi Neo-Milenial. Banyak istilah diberikan untuk generasi baru ini: Digital Native, Net Generation, WI-Fi Generation, Connected Generation, dan lain.
Merekalah anak-anak kita yang kini duduk di bangku SMP, SD, dan lebih muda lagi. Kalau proses transisi antara generasi-generasi sebelumnya berlangsung secara linear dan kontinu, maka terbentuknya generasi baru ini bersifat disruptif, diskontinum, dan ”tercerabut dari akarnya” alias berbeda sama sekali dengan generasi- generasi sebelumnya. Mereka highly -mobile, appsdependent, dan selalu terhubung secara online (”always connected”). Mereka begitu cepat menerima dan berbagi informasi melalui jejaring sosial.
Mereka adalah self-learner yang secara mandiri mencari sendiri pengetahuan yang mereka butuhkan melalui situs, seperti Wikipedia atau Khan Academy. Mereka emoh digurui. Mereka adalah generasi yang sangat melek visual (visually literate ). Karena itu lebih menyukai belajar berbasis visual (melalui video di YouTube, online games, bahkan menggunakan augmentedreality) ketimbang melalui teks (membaca buku atau mendengar ceramah guru di kelas).
Mereka sangat melek data (data literate ) sehingga piawai berselancar di Google mengulik, memproses, dan mengurasi informasi ketimbang pasif berkubang di perpustakaan. Itu dilakukan dengan supercepat melalui 3M: multimedia , multiplatform , dan multitasking . Mereka lebih nyaman belajar secara kolaboratif di dalam proyek riil atau pendekatan peerto- peer melalui komunitas atau jejaring sosial (menggunakan social learning platform ).
Bagi mereka, peers lebih kredibel ketimbang guru. Ingat, mereka lebih suka menggunakan interactive gaming (gamifikasi) untuk belajar ketimbang suntuk mengerjakanpekerjaanrumah( PR). Karena adanya ”generation gap ”, mereka stres dan frustrasi diajar oleh guru-guru dari generasi sebelumnya (Gen X bahkan Baby Boomers) yang gagal memahami perilaku digital mereka. Ketika anak-anak kita sudah berubah sedemikian rupa sementara sekolah bebal tak mau berubah, maka tinggal tunggu waktu, sekolah akan terkena sapu jagat disrupsi.
#2. Hyper-Demanding Parents: The Rise of Homeschooling
Meningkat drastisnya orang tua kelas menengah sejak awal tahun 2000-an menciptakan para orang tua yang sangat demanding terkait pendidikan buah hatinya. Mereka tak puas lagi dengan hasil pendidikan sekolah formal-tradisional. Mereka mengeluh, sekolah formal hanyalah berorientasi pada nilai rapor (kepentingan sekolah), bukannya mengedepankan keterampilan hidup dan bersosial (moral dan agama). Akibatnya banyak murid mengejar nilai rapor dengan menyontek.
Mereka juga merasa anak-anak mereka kurang diperhatikan keunikan bakatnya secara personal dan sekolah tak merangsang daya imajinasi dan kreasi anak. Selain itu, mereka merasa sekolah formal memiliki kelemahan mendasar karena tak memberikan pembelajaran dunia nyata yang kontekstual, tematik, nonskolastik yang tidak tersekat-sekat oleh batasan disiplin ilmu. Pembelajarannya teacher-centric bukannya student-centric dimana keterlibatan orang tua marjinal.
Ketidakpuasan ini mendorong munculnya gerakan homeschooling yang masif terjadi selama sepuluh tahun terakhir. Para orang tua memilih ”turun gunung” untuk mendidik anak-anaknya di rumah. Homeschooling menjadi tumpuan harapan orang tua untuk meningkatkan mutu pendidikan anak, mengembangkan nilai- nilai moral, dan memberikan suasana belajar yang menyenangkan.
Singkatnya, gerakan homeschooling merupakan jawaban orang tua terhadap kegagalan sekolah formal-tradisional yang kian obsolet dan tak relevan lagi. Selain murid, orang tua adalah jugadisruptorkuncibagi sekolah. (Bersambung)
YUSWOHADY
Managing Partner, Inventure www.yuswohady.com @yuswohady
Kebijakan blunder untuk sekian kali seperti ini (”beda menteri, beda pula blundernya”) menjadi wake-up call . Betapa kalau sekolah-sekolah kita terus dikelola dengan pendekatan BAU (business as usual ) semacam ini pada akhirnya akan menjadi obsolet alias usang, kian tak relevan, dan akhirnya masuk museum.
Dengan begitu, tak hanya tukang ojek pangkalan yang terkena disrupsi Go-Jek atau operator taksi yang terkena disrupsi Uber, saya khawatir sekolah-sekolah kita juga akan menjadi korban disrupsi berikutnya. Berikut ini adalah empat alasan substantif kenapa sekolah-sekolah kita bakal terdisrupsi jika kita terus-menerus ”gagal paham”, tidak peka, tidak agile, dan tidak cepat merespons gelombang disruptive change yang kini sedang menyapu lanskap pendidikan kita.
#1. Neo-Milennials: The Prime Disruptor
Disruptor paling utama sekolah, menurut saya, bukanlah digital apps, sharing platform, atau algoritma-AI (artificial intellegence ) yang super canggih, tapi adalah konsumen dari sekolah, yaitu murid. Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, kita mendapati sebuah generasi yang terlepas sama sekali (decoupling) dengan generasi-generasi sebelumnya (Silent, Baby Boomers, Gen X) yang disebut Generasi Neo-Milenial. Banyak istilah diberikan untuk generasi baru ini: Digital Native, Net Generation, WI-Fi Generation, Connected Generation, dan lain.
Merekalah anak-anak kita yang kini duduk di bangku SMP, SD, dan lebih muda lagi. Kalau proses transisi antara generasi-generasi sebelumnya berlangsung secara linear dan kontinu, maka terbentuknya generasi baru ini bersifat disruptif, diskontinum, dan ”tercerabut dari akarnya” alias berbeda sama sekali dengan generasi- generasi sebelumnya. Mereka highly -mobile, appsdependent, dan selalu terhubung secara online (”always connected”). Mereka begitu cepat menerima dan berbagi informasi melalui jejaring sosial.
Mereka adalah self-learner yang secara mandiri mencari sendiri pengetahuan yang mereka butuhkan melalui situs, seperti Wikipedia atau Khan Academy. Mereka emoh digurui. Mereka adalah generasi yang sangat melek visual (visually literate ). Karena itu lebih menyukai belajar berbasis visual (melalui video di YouTube, online games, bahkan menggunakan augmentedreality) ketimbang melalui teks (membaca buku atau mendengar ceramah guru di kelas).
Mereka sangat melek data (data literate ) sehingga piawai berselancar di Google mengulik, memproses, dan mengurasi informasi ketimbang pasif berkubang di perpustakaan. Itu dilakukan dengan supercepat melalui 3M: multimedia , multiplatform , dan multitasking . Mereka lebih nyaman belajar secara kolaboratif di dalam proyek riil atau pendekatan peerto- peer melalui komunitas atau jejaring sosial (menggunakan social learning platform ).
Bagi mereka, peers lebih kredibel ketimbang guru. Ingat, mereka lebih suka menggunakan interactive gaming (gamifikasi) untuk belajar ketimbang suntuk mengerjakanpekerjaanrumah( PR). Karena adanya ”generation gap ”, mereka stres dan frustrasi diajar oleh guru-guru dari generasi sebelumnya (Gen X bahkan Baby Boomers) yang gagal memahami perilaku digital mereka. Ketika anak-anak kita sudah berubah sedemikian rupa sementara sekolah bebal tak mau berubah, maka tinggal tunggu waktu, sekolah akan terkena sapu jagat disrupsi.
#2. Hyper-Demanding Parents: The Rise of Homeschooling
Meningkat drastisnya orang tua kelas menengah sejak awal tahun 2000-an menciptakan para orang tua yang sangat demanding terkait pendidikan buah hatinya. Mereka tak puas lagi dengan hasil pendidikan sekolah formal-tradisional. Mereka mengeluh, sekolah formal hanyalah berorientasi pada nilai rapor (kepentingan sekolah), bukannya mengedepankan keterampilan hidup dan bersosial (moral dan agama). Akibatnya banyak murid mengejar nilai rapor dengan menyontek.
Mereka juga merasa anak-anak mereka kurang diperhatikan keunikan bakatnya secara personal dan sekolah tak merangsang daya imajinasi dan kreasi anak. Selain itu, mereka merasa sekolah formal memiliki kelemahan mendasar karena tak memberikan pembelajaran dunia nyata yang kontekstual, tematik, nonskolastik yang tidak tersekat-sekat oleh batasan disiplin ilmu. Pembelajarannya teacher-centric bukannya student-centric dimana keterlibatan orang tua marjinal.
Ketidakpuasan ini mendorong munculnya gerakan homeschooling yang masif terjadi selama sepuluh tahun terakhir. Para orang tua memilih ”turun gunung” untuk mendidik anak-anaknya di rumah. Homeschooling menjadi tumpuan harapan orang tua untuk meningkatkan mutu pendidikan anak, mengembangkan nilai- nilai moral, dan memberikan suasana belajar yang menyenangkan.
Singkatnya, gerakan homeschooling merupakan jawaban orang tua terhadap kegagalan sekolah formal-tradisional yang kian obsolet dan tak relevan lagi. Selain murid, orang tua adalah jugadisruptorkuncibagi sekolah. (Bersambung)
YUSWOHADY
Managing Partner, Inventure www.yuswohady.com @yuswohady
(akr)