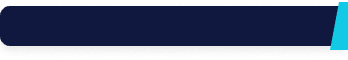Merek Berbahasa Indonesia

Merek Berbahasa Indonesia
A
A
A
Minggu ini pemerintah mengeluarkan Perpres No. 63 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Dalam Pasal 35 Perpres tersebut tertera ketentuan yang berbunyi:
“Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama merek dagang yang berupa kata atau gabungan kata yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.”
Membaca butir ketentuan itu barangkali dengan bungah kita kemudian berpikir bahwa nantinya kita akan memiliki merek-merek top dunia seperti yang dimiliki Jepang atau Korea seperti: Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Samsung, atau Hyundai.
Ya, nama-nama merek itu adalah nama-nama dari kosakata bahasa asli Jepang dan Korea yang melalui perjuangan brand-building berpuluh tahun kini telah menjadi household brand di seluruh dunia. Namun apakah memang demikian? Tak segampang itu.
Saya percaya, maksud dikeluarkannya Perpres itu baik dan mulia untuk mempromosikan bahasa kebanggaan kita Bahasa Indonesia di dalam maupun di luar negeri.
Namun jika tidak bijak dijalankan, Perpres tersebut bukannya berbuah manis tapi justru sebaliknya destruktif, kontraproduktif, dan merugikan kepentingan bangsa kita sendiri. Karena kalau kita telisik lebih dalam terdapat beberapa trade-off antara keinginan idealis dan kepentingan praktis.
Pertama, jika Perpres itu diberlakukan untuk merek-merek yang kini sudah eksis. Itu artinya merek Blue Bird misalnya, harus berganti nama menjadi: “Burung Biru”; Indofood menjadi “MakananIndonesia”; IndiHome menjadi “RumahIndonesia”; Citilink menjadi “KotaTerhubung”; mal Pacific Place menjadi “Tempat Pasifik”; dan masih banyak lagi nama-nama merek baru yang penamaannya terdengar konyol.
Dengan pemberlakukan Perpres itu akan ada ribuan merek nasional berbahasa asing yang dalam sekejab menjadi “mutan” yang tiba-tiba tidak dikenali basis konsumennya. Kalau itu terjadi tak terbayang berapa triliuan rupiah kerugian yang bakal ditanggung oleh merek-merek hebat nasional itu.
Membangun merek (brand building) adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu amat panjang (bahkan belasan/puluhan tahun) dengan biaya yang amat mahal. Tujuannya adalah menghasilkan apa yang disebut ekuitas merek (brandequity) yang mencakup beberapa elemen yaitu: pengetahuan (brandawareness), asosiasi (brandassociation), persepsi kualitas (perceivedquality), loyalitas konsumen (brandloyalty), dan rekomendasi konsumen (brandadvocacy).
Nama merek (brandname) dan logo (brandlogo) punya peran amat krusial bagi pembentukan ekuitas merek. Ia seperti halnya “wajah” sebuah merek. Ketika ekuitas merek telah mapan terbentuk selama bertahun-tahun dan kemudian tiba-tiba harus diganti namanya (dan otomatis logonya), maka seluruh ekuitas merek tersebut akan sirna dalam sekejab.
Jadi dampak perubahan nama merek dan logo tersebut akan bersifat disruptif dan dahsyat. Memang ekuitas merek bisa dibangun kembali namun prosesnya akan dari awal lagi dan membutuhkan waktu dan biaya yang amat mahal.
Karena begitu dahsyat dampak negatifnya, saya berani katakan skenario ini tak mungkin diambil oleh Pemerintah karena dampak kerugiannya akan luar biasa.
Kedua, lalu bagaimana jika Perpres ini diberlakukan untuk merek baru? Ini pun mengandung konsekuensi negatif yang tidak kecil.
Ini terutama bakal dialami saat kita membangun merek-merek nasional kita di luar negeri. Karena kosa kata Bahasa Indonesia tidak begitu dikenal di dunia, maka upaya brand-building yang kita lakukan menjadi jauh lebih sulit.
Begitu juga waktu dan biaya yang dibutuhkan menjadi berlipat-lipat lebih besar. Singkatnya, membangun merek nasional di pasar global bakal lebih sulit, lebih lama, dan lebih mahal.
Banyak dari para pemilik merek nasional kita menggunakan nama merek berbahasa Inggris bukan karena mereka kurang nasionalis atau tidak peduli dengan pengembangan Bahasa Indonesia.
Namun, karena menggunakan nama merek berbahasa Inggris membuat mereka lebih mudah, murah, dan lebih efektif dalam membangun brand awareness, association, perceived quality, dan loyalty di kalangan konsumen luar negeri.
Ambil contoh kenapa Kementerian Pariwisata lebih menggunakan merek Wonderful Indonesia ketimbang Pesona Indonesia untuk mempromosikan pariwisata Indonesia ke audiens global? Alasannya substantif, Karena menggunakan kata “wonderful” jauh lebih mudah, murah,dan efektif dibanding kata “pesona”.
Ketika kita menggunakan kata “wonderful” dari sisi brandassociation misalnya, konsumen global akan bisa langsung membayangkan bahwa Indonesia itu wonderful alias indah-menakjubkan.
Tak hanya itu asosiasi positif ini juga mempermudah mereka membangun kedekatan dan koneksi emosional dengan merek Wonderful Indonesia. Dan inilah yang menjadi basis bagi pembentukan ekuitas merek.
Hal ini berbeda jika kita mengunakan kata “pesona”. Ketika audiens global tidak mengenal kata tersebut karena sebelumnya tidak hadir dalam memori otak mereka, maka sulit bagi mereka untuk bisa mengenal (brandawareness), mengasosiasikan (brandassociation), mengetahui atribut kualitas (perceivedquality) atau mengenal lebih dekat dan loyal (brandloyalty) kepada merek tersebut.
Artinya kita mempersulit diri sendiri dalam menembus dan membangun merek nasional di pasar global. Ini tentu kontraproduktif dengan kepentingan pemerintah untuk mendorong ekspor dan mengurangi transaksi defisit berjalan (current account deficit/CAD) yang telah menjadi penyakit akut bagi ekonomi kita.
Untuk menghindari berbagai dampak negatif di atas, Perpres ini harus dikaji kembali atau penerapannya perlu diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai merugikan kepentingan nasional bangsa ini.
Yuswohady
Managing Partner Inventure
“Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama merek dagang yang berupa kata atau gabungan kata yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.”
Membaca butir ketentuan itu barangkali dengan bungah kita kemudian berpikir bahwa nantinya kita akan memiliki merek-merek top dunia seperti yang dimiliki Jepang atau Korea seperti: Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Samsung, atau Hyundai.
Ya, nama-nama merek itu adalah nama-nama dari kosakata bahasa asli Jepang dan Korea yang melalui perjuangan brand-building berpuluh tahun kini telah menjadi household brand di seluruh dunia. Namun apakah memang demikian? Tak segampang itu.
Saya percaya, maksud dikeluarkannya Perpres itu baik dan mulia untuk mempromosikan bahasa kebanggaan kita Bahasa Indonesia di dalam maupun di luar negeri.
Namun jika tidak bijak dijalankan, Perpres tersebut bukannya berbuah manis tapi justru sebaliknya destruktif, kontraproduktif, dan merugikan kepentingan bangsa kita sendiri. Karena kalau kita telisik lebih dalam terdapat beberapa trade-off antara keinginan idealis dan kepentingan praktis.
Pertama, jika Perpres itu diberlakukan untuk merek-merek yang kini sudah eksis. Itu artinya merek Blue Bird misalnya, harus berganti nama menjadi: “Burung Biru”; Indofood menjadi “MakananIndonesia”; IndiHome menjadi “RumahIndonesia”; Citilink menjadi “KotaTerhubung”; mal Pacific Place menjadi “Tempat Pasifik”; dan masih banyak lagi nama-nama merek baru yang penamaannya terdengar konyol.
Dengan pemberlakukan Perpres itu akan ada ribuan merek nasional berbahasa asing yang dalam sekejab menjadi “mutan” yang tiba-tiba tidak dikenali basis konsumennya. Kalau itu terjadi tak terbayang berapa triliuan rupiah kerugian yang bakal ditanggung oleh merek-merek hebat nasional itu.
Membangun merek (brand building) adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu amat panjang (bahkan belasan/puluhan tahun) dengan biaya yang amat mahal. Tujuannya adalah menghasilkan apa yang disebut ekuitas merek (brandequity) yang mencakup beberapa elemen yaitu: pengetahuan (brandawareness), asosiasi (brandassociation), persepsi kualitas (perceivedquality), loyalitas konsumen (brandloyalty), dan rekomendasi konsumen (brandadvocacy).
Nama merek (brandname) dan logo (brandlogo) punya peran amat krusial bagi pembentukan ekuitas merek. Ia seperti halnya “wajah” sebuah merek. Ketika ekuitas merek telah mapan terbentuk selama bertahun-tahun dan kemudian tiba-tiba harus diganti namanya (dan otomatis logonya), maka seluruh ekuitas merek tersebut akan sirna dalam sekejab.
Jadi dampak perubahan nama merek dan logo tersebut akan bersifat disruptif dan dahsyat. Memang ekuitas merek bisa dibangun kembali namun prosesnya akan dari awal lagi dan membutuhkan waktu dan biaya yang amat mahal.
Karena begitu dahsyat dampak negatifnya, saya berani katakan skenario ini tak mungkin diambil oleh Pemerintah karena dampak kerugiannya akan luar biasa.
Kedua, lalu bagaimana jika Perpres ini diberlakukan untuk merek baru? Ini pun mengandung konsekuensi negatif yang tidak kecil.
Ini terutama bakal dialami saat kita membangun merek-merek nasional kita di luar negeri. Karena kosa kata Bahasa Indonesia tidak begitu dikenal di dunia, maka upaya brand-building yang kita lakukan menjadi jauh lebih sulit.
Begitu juga waktu dan biaya yang dibutuhkan menjadi berlipat-lipat lebih besar. Singkatnya, membangun merek nasional di pasar global bakal lebih sulit, lebih lama, dan lebih mahal.
Banyak dari para pemilik merek nasional kita menggunakan nama merek berbahasa Inggris bukan karena mereka kurang nasionalis atau tidak peduli dengan pengembangan Bahasa Indonesia.
Namun, karena menggunakan nama merek berbahasa Inggris membuat mereka lebih mudah, murah, dan lebih efektif dalam membangun brand awareness, association, perceived quality, dan loyalty di kalangan konsumen luar negeri.
Ambil contoh kenapa Kementerian Pariwisata lebih menggunakan merek Wonderful Indonesia ketimbang Pesona Indonesia untuk mempromosikan pariwisata Indonesia ke audiens global? Alasannya substantif, Karena menggunakan kata “wonderful” jauh lebih mudah, murah,dan efektif dibanding kata “pesona”.
Ketika kita menggunakan kata “wonderful” dari sisi brandassociation misalnya, konsumen global akan bisa langsung membayangkan bahwa Indonesia itu wonderful alias indah-menakjubkan.
Tak hanya itu asosiasi positif ini juga mempermudah mereka membangun kedekatan dan koneksi emosional dengan merek Wonderful Indonesia. Dan inilah yang menjadi basis bagi pembentukan ekuitas merek.
Hal ini berbeda jika kita mengunakan kata “pesona”. Ketika audiens global tidak mengenal kata tersebut karena sebelumnya tidak hadir dalam memori otak mereka, maka sulit bagi mereka untuk bisa mengenal (brandawareness), mengasosiasikan (brandassociation), mengetahui atribut kualitas (perceivedquality) atau mengenal lebih dekat dan loyal (brandloyalty) kepada merek tersebut.
Artinya kita mempersulit diri sendiri dalam menembus dan membangun merek nasional di pasar global. Ini tentu kontraproduktif dengan kepentingan pemerintah untuk mendorong ekspor dan mengurangi transaksi defisit berjalan (current account deficit/CAD) yang telah menjadi penyakit akut bagi ekonomi kita.
Untuk menghindari berbagai dampak negatif di atas, Perpres ini harus dikaji kembali atau penerapannya perlu diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai merugikan kepentingan nasional bangsa ini.
Yuswohady
Managing Partner Inventure
(nfl)