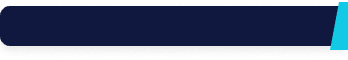Lima Bias Behavioral

Lima Bias Behavioral
A
A
A
Ratusan ribu profesional keuangan di seluruh dunia setiap tahun mengikuti ujian sertifikasi paling bergengsi yaitu Chartered Financial Analyst (CFA).
Seiring dengan semakin diakuinya kontribusi behavioral finance dalam menjelaskan banyak keputusan keuangan, sejak beberapa tahun lalu para peserta ujian tingkat terakhir (tingkat 3) CFA harus melewati soal-soal tentang topik baru yang menarik ini. Behavioral finance sendiri mulai berkembang ketika Daniel Kahneman menulis artikel tentang teori prospek pada tahun 1979 yang menjadikannya psikolog pertama dan satu-satunya peraih nobel ekonomi (2002).
Dua tahun setelah itu, pakar keuangan terkemuka dari Yale University, Robert Shiller, juga menulis artikel yang tidak kalah hebatnya karena berani menentang aliran utama ilmu keuangan yaitu hipotesis pasar efisien. Shiller membuktikan bahwa volatilitas harga saham jauh lebih besar daripada volatilitas laba atau dividennya alias terlalu banyak noise di pasar.
Menurutnya, tidak ada bukti investor rasional dan karenanya, pasar menjadi tidak efisien. Untuk artikel ini dan artikel lainnya tahun 2003 yaitu From Efficient Market Hypothesis to Behavioral Finance serta bukunya yang menggemparkan di tahun 2000 yaitu Irrational Exuberance , Shiller juga dianugerahi nobel ekonomi tahun 2013.
Behavioral finance adalah ilmu tentang aplikasi psikologi dalam dunia keuangan terutama dalam menyelaraskan perbedaan antara valuasi rasional versi teori pasar efisien (TPE) dan harga pasar yang irasional. Inilah lima bias utama behavioral yang terjadi di kalangan investor. Jangan malu untuk mengakui Anda pun mengalaminya sebagai investor saham ritel.
Merasa Diri Hebat
Investor sering menilai kemampuan dirinya berlebihan. Akibat bias ini, investor tidak ragu untuk bertransaksi saham dengan fasilitas marjin. Ilusi kontrol ini juga membuat banyak investor bertransaksi aktif karena merasa mampu untuk mengendalikan pasar dan dalam memprediksi arah harga di masa depan. Yang terjadi justru sebaliknya.
Mereka yang sering beli-jual saham malah memperoleh return rata-rata di bawah pasar. Untung belum pasti sementara argo biaya transaksi jalan terus. Implikasi lain dari bias terlalu percaya diri ini adalah praktik tidak diversifikasi yang dilakukan sebagian besar investor ritel di bursa kita dan di bursabursa dunia lainnya. Padahal strategi fokus bukanlah strategi yang pas untuk investor ritel dengan kemampuan investasi rata-rata.
Harga Referensi
Bias ini berhubungan dengan penggunaan acuan tertentu untuk pengambilan keputusan. Jika Anda sempat menjual sebuah saham di harga Rp1.700 beberapa waktu lalu, sangat mungkin Anda tidak bersedia membelinya kembali ketika harganya terus naik menjadi Rp2.000. Angka Rp1.700 akan terus Anda ingat untuk keputusan membeli saham itu.
Ada juga investor yang menggunakan harga minimum sebuah saham setahun terakhir sebagai referensi untuk membeli saham dan harga tertingginya untuk acuan harga jualnya. Jika ini terjadi, hampir pasti dia tidak akan pernah jadi membeli atau menjual saham dimaksud. Yang paling sering terjadi adalah investor menggunakan harga belinya sebagai acuan (anchoring ) harga minimum untuk menjualnya.
Stereotyping
Banyak investor termasuk yang berpengalaman sekalipun tidak dapat membedakan antara saham bagus dan perusahaan bagus. Mereka menilai saham bagus atau jelek berdasarkan bagus atau jeleknya perusahaan.
Saham bagus sejatinya tidak sama dengan perusahaan bagus. Saham yang bagus (good stocks ) adalah saham berharga bagus atau saham yang menjanjikan return yang besar di masa depan sedangkan perusahaan bagus (good company ) ukuran sederhananya adalah perusahaan yang mempunyai peringkat yang bagus, minimal tripel B sebagai batas rating layak investasi. Bias ini berhubungan dengan fenomena manusia yang sering mengambil keputusan berdasarkan stereotip .
Banyak sekali kita menemui contoh bias ini dalam kehidupan sehari-hari. Anakanak dari orang tua yang pendek dipercaya akan juga pendek, calon pelamar kerja yang indeks prestasinya tinggi (rendah), dianggap akan berprestasi tinggi (rendah) juga dalam pekerjaannya.
Takut Rugi
Buku-buku investasi tradisional mengatakan investor takut risiko atau risk-averse. Risiko sendiri didefinisikan sebagai volatilitas atau fluktuasi harga. Behavioral finance berpandangan lain bahwa investor itu sebenarnya bukan takut risiko atau volatilitas tetapi takut rugi atau loss averse .
Anda tahu harapan seorang investor yang harga sahamnya jatuh sesaat setelah dia membeli? Harapannya ternyata bukan memperoleh untung tetapi agar dia tidak jadi rugi. Karena itu doanya adalah semoga harga segera kembali lagi agar dia dapat menjualnya dan dia mendapatkan modalnya kembali. Bias ini disebut juga bias get evenitis .
Efek Disposisi
Implikasi dari loss aversion di atas adalah investor ritel kerap membiarkan kerugian portofolionya terus mengalir. Menjual saham rugi sering menjadi sangat sulit untuk dilakukan karena ada perasaan bersalah, malu, dan kekurangmampuan. Menjual saham rugi seperti sebuah pengakuan kekalahan dan tindakan ini juga menutup kemungkinan keputusan pembelian saham ternyata benar.
Di sisi lain, investor cepat dalam memutuskan menjual saham untung. Ada perasaan menang dan puas yang menyertai tindakan ini. Akibatnya, dalam portofolio akan ada banyak saham rugi besar tetapi tidak ada yang untung besar.
Bukannya membatasi kerugian dan membiarkan keuntungan mengalir (let the profits run ), banyak investor ritel justru melakukan sebaliknya yaitu membatasi keuntungan dan membiarkan kerugian menumpuk. Shefrin dan Statman (1985) mencatat ini sebagai efek disposisi yaitu sell the winners too soon and hold the losers too long.
Budi Frensidy
Staf Pengajar FEUI dan Perencana Keuangan, www.fund-and-fun.com @BudiFrensidy
Seiring dengan semakin diakuinya kontribusi behavioral finance dalam menjelaskan banyak keputusan keuangan, sejak beberapa tahun lalu para peserta ujian tingkat terakhir (tingkat 3) CFA harus melewati soal-soal tentang topik baru yang menarik ini. Behavioral finance sendiri mulai berkembang ketika Daniel Kahneman menulis artikel tentang teori prospek pada tahun 1979 yang menjadikannya psikolog pertama dan satu-satunya peraih nobel ekonomi (2002).
Dua tahun setelah itu, pakar keuangan terkemuka dari Yale University, Robert Shiller, juga menulis artikel yang tidak kalah hebatnya karena berani menentang aliran utama ilmu keuangan yaitu hipotesis pasar efisien. Shiller membuktikan bahwa volatilitas harga saham jauh lebih besar daripada volatilitas laba atau dividennya alias terlalu banyak noise di pasar.
Menurutnya, tidak ada bukti investor rasional dan karenanya, pasar menjadi tidak efisien. Untuk artikel ini dan artikel lainnya tahun 2003 yaitu From Efficient Market Hypothesis to Behavioral Finance serta bukunya yang menggemparkan di tahun 2000 yaitu Irrational Exuberance , Shiller juga dianugerahi nobel ekonomi tahun 2013.
Behavioral finance adalah ilmu tentang aplikasi psikologi dalam dunia keuangan terutama dalam menyelaraskan perbedaan antara valuasi rasional versi teori pasar efisien (TPE) dan harga pasar yang irasional. Inilah lima bias utama behavioral yang terjadi di kalangan investor. Jangan malu untuk mengakui Anda pun mengalaminya sebagai investor saham ritel.
Merasa Diri Hebat
Investor sering menilai kemampuan dirinya berlebihan. Akibat bias ini, investor tidak ragu untuk bertransaksi saham dengan fasilitas marjin. Ilusi kontrol ini juga membuat banyak investor bertransaksi aktif karena merasa mampu untuk mengendalikan pasar dan dalam memprediksi arah harga di masa depan. Yang terjadi justru sebaliknya.
Mereka yang sering beli-jual saham malah memperoleh return rata-rata di bawah pasar. Untung belum pasti sementara argo biaya transaksi jalan terus. Implikasi lain dari bias terlalu percaya diri ini adalah praktik tidak diversifikasi yang dilakukan sebagian besar investor ritel di bursa kita dan di bursabursa dunia lainnya. Padahal strategi fokus bukanlah strategi yang pas untuk investor ritel dengan kemampuan investasi rata-rata.
Harga Referensi
Bias ini berhubungan dengan penggunaan acuan tertentu untuk pengambilan keputusan. Jika Anda sempat menjual sebuah saham di harga Rp1.700 beberapa waktu lalu, sangat mungkin Anda tidak bersedia membelinya kembali ketika harganya terus naik menjadi Rp2.000. Angka Rp1.700 akan terus Anda ingat untuk keputusan membeli saham itu.
Ada juga investor yang menggunakan harga minimum sebuah saham setahun terakhir sebagai referensi untuk membeli saham dan harga tertingginya untuk acuan harga jualnya. Jika ini terjadi, hampir pasti dia tidak akan pernah jadi membeli atau menjual saham dimaksud. Yang paling sering terjadi adalah investor menggunakan harga belinya sebagai acuan (anchoring ) harga minimum untuk menjualnya.
Stereotyping
Banyak investor termasuk yang berpengalaman sekalipun tidak dapat membedakan antara saham bagus dan perusahaan bagus. Mereka menilai saham bagus atau jelek berdasarkan bagus atau jeleknya perusahaan.
Saham bagus sejatinya tidak sama dengan perusahaan bagus. Saham yang bagus (good stocks ) adalah saham berharga bagus atau saham yang menjanjikan return yang besar di masa depan sedangkan perusahaan bagus (good company ) ukuran sederhananya adalah perusahaan yang mempunyai peringkat yang bagus, minimal tripel B sebagai batas rating layak investasi. Bias ini berhubungan dengan fenomena manusia yang sering mengambil keputusan berdasarkan stereotip .
Banyak sekali kita menemui contoh bias ini dalam kehidupan sehari-hari. Anakanak dari orang tua yang pendek dipercaya akan juga pendek, calon pelamar kerja yang indeks prestasinya tinggi (rendah), dianggap akan berprestasi tinggi (rendah) juga dalam pekerjaannya.
Takut Rugi
Buku-buku investasi tradisional mengatakan investor takut risiko atau risk-averse. Risiko sendiri didefinisikan sebagai volatilitas atau fluktuasi harga. Behavioral finance berpandangan lain bahwa investor itu sebenarnya bukan takut risiko atau volatilitas tetapi takut rugi atau loss averse .
Anda tahu harapan seorang investor yang harga sahamnya jatuh sesaat setelah dia membeli? Harapannya ternyata bukan memperoleh untung tetapi agar dia tidak jadi rugi. Karena itu doanya adalah semoga harga segera kembali lagi agar dia dapat menjualnya dan dia mendapatkan modalnya kembali. Bias ini disebut juga bias get evenitis .
Efek Disposisi
Implikasi dari loss aversion di atas adalah investor ritel kerap membiarkan kerugian portofolionya terus mengalir. Menjual saham rugi sering menjadi sangat sulit untuk dilakukan karena ada perasaan bersalah, malu, dan kekurangmampuan. Menjual saham rugi seperti sebuah pengakuan kekalahan dan tindakan ini juga menutup kemungkinan keputusan pembelian saham ternyata benar.
Di sisi lain, investor cepat dalam memutuskan menjual saham untung. Ada perasaan menang dan puas yang menyertai tindakan ini. Akibatnya, dalam portofolio akan ada banyak saham rugi besar tetapi tidak ada yang untung besar.
Bukannya membatasi kerugian dan membiarkan keuntungan mengalir (let the profits run ), banyak investor ritel justru melakukan sebaliknya yaitu membatasi keuntungan dan membiarkan kerugian menumpuk. Shefrin dan Statman (1985) mencatat ini sebagai efek disposisi yaitu sell the winners too soon and hold the losers too long.
Budi Frensidy
Staf Pengajar FEUI dan Perencana Keuangan, www.fund-and-fun.com @BudiFrensidy
(ars)