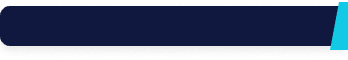Pengembang Harus Mendapat Insentif untuk Atasi Backlog

Pengembang Harus Mendapat Insentif untuk Atasi Backlog
A
A
A
DANANG KEMAYAN JATI
Praktisi Industri Properti
PEMERINTAHAN Joko Widodo telah menempatkan reforma agraria sebagai prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.
Tanah seluas 9 juta hektare menjadi rencana redistribusi tanah dan legalisasi aset di bawah payung reforma agraria. Sumber tanahnya berasal dari kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan (perkebunan). Sedangkan dalam rangka memperluas wilayah kelola masyarakat di kawasan hutan, target 12,7 juta hektare hendak dialokasikan untuk dapat diberikan izin kelolanya kepada masyarakat.
Namun kebijakan itu masih bersifat sektoral perkebunan, kehutanan dan pedesaan. Sebaknya tujuan reforma agraria seharusnya multi sektoral. Sehingga dapat menyelesaikan ketimpangan struktural di wilayah pertambangan, pesisir, kelautan, pulau-pulau kecil dan khususnya Reforma Agraria di sektor perkotaan (urban). Tulisan ini tidak bermaksud membahas sektor-sektor lainnya hanya ingin mengelupas tentang Reforma Agraria dalam bidang perkotaan (urban)
Presiden Joko Widodo juga sudah mengeluarkan kebijakan paket ekonomi dengan menyederhanakan perizinan dan lain-lain untuk mempercepat perizinan pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam perencanaan pembangunan perumahan, sejatinya perlu dibuat riset terlebih dahulu. Karena ternyata semua kebijakan paket ekonomi ternyata pengaruhnya lebih arah kota bukan untuk mengatasi kesenjanganuntuk MBR, seperti Backlog yang terus bertambah sekitar 800 ribu rumah setiap tahun. Sedangkan pemenuhan rumah tak bisa menutupi kesenjangan.
Salah satu indikasinya tentu saja karena faktor keterbatasan lahan dan harga tanah yang semakin mahal. Pemerintah tak mungkin menyelesaikan sendiri, perlu memberdayakan pihak swasta.
Memberdayakan artinya tidak merugikan pihak swasta secara bisnis atau ekonomi, melainkan memberikan insentif karena membantu program pemerintah untuk mengatasi Backlog yang sekarang telah mencapai 11 juta rumah. Insentif dari pemerintah tidak harus diberikan subsidi atau uang tapi cukup dengan kebijakan yang konsisten.
Backlog rumah tinggal diperkotaan sebenarnya dapat dibagi dalam dua kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pertama adalah kebutuhan untuk masyarakat yang bekerja secara mandiri dan kedua untuk masyarakat yang bekerja pada orang lain (pegawai pemerintah dan pegawai swasta). Sudah ada contoh negara yang berhasil mengatasi kesenjangan kepemilikan rumah ini, yaitu Singapura yang berhasil menjalankan subsidi silang dan bergotong-royong.
Ada tiga cara negara itu membuat kebijakan. Pertama, kepada seluruh pekerja baik mandiri atau bekerja pada orang lain diwajibkan menabung sesuai dengan penghasilannya. Kedua, pihak pemberi kerja, baik itu pemerintah atau swasta diminta berkontribusi dengan menambah tabungan pekerjanya. Ketiga, dana tersebut akan dikelola oleh pemerintah yang fokus membangun rumah MBR. Masyarakat tadi bisa langsung mengajukan pembelian dengan menggunakan tabungannya sebagai DP tentu saat tabungan mencapai jumlah tertentu.
Reforma Agraria diperlukan untuk mengendalikan harga tanah yang terus menerus naik, dan tampaknya pemerintah tak mungkin memaksa menurunkan harga tanah. Tetapi memberikan insentif bila setiap jengkal tanah atau setiap meter persegi dimaksimalkan intensitasnya bangunan ke atas dan memberikan denda untuk setiap pemborosan tanah di perkotaan.
Misalnya KLB harus dibatasi dan tidak lagi mengizinkan pembangunan kawasan hunian dengan mayoritas landed house. Atau jika memang diperlukan harus dengan syarat yang ketat. Ini agar tidak terjadi perambahan lahan. Prinsip utamanya lahan harus dihemat.
Selama ini, pemerintah tidak konsisten dalam penyediaan hunian vertikal. Padahal perannya sangat besar memenuhi backlog perumahan. Pembangunan apartemen misalnya, malah dihambat, dipersulit dengan beragam aturan. Banyak ongkos yang harus dikeluarkan pengembang termasuk ongkos politik. Tentu ini tidak baik bagi iklim investasi di Indonesia, khususnya dalam rangka penyediaan perumahan.
Pengembang jangan dibebani ongkos politik. Justru seharusnya bagi mereka yang membangun apartemen harus diapersiasi karena sudah memberikan solusi akibat mahalnya harga tanah.
Contoh, membangun rumah di Menteng dengan harga tanah sekitar Rp100 juta per meter persegi, ada satu orang membeli atau menguasai 1.000 meter persegi tetapi hanya dibangun 500 meter persegi, itu berarti KLB (koefisiensi luas bangunan) hanya 0,5 dibanding dengan developer yang akan membangun tanah yang sama untuk dibangun rumah susun seluas 10.000 meter persegi yang mempunyai KLB sebesar 10.
Jadi mana yang lebih dibutuhkan dalam menunjang program pemerintah? Tentunya developer yang membangun dengan KLB 10. Bagaimana pemerintah bersikap dalam memberikan insentif untuk pihak yang membangun dengan KLB 10 dibanding dengan developer yang membangun rumah tapak dengan KLB 0,5.
Karena KLB 10 dengan 50 meter persegi per unit akan dapat menyediakan 200 tempat tinggal. Itu hanya contoh untuk seribu meter, lalu bagaiman dengan rumah tapak yang terus dibangun dengan memboroskan tanah ribuah ratusan hingga ribuan hektare?
Kelak di dunia tidak ada lagi landed house baru, karena lahan terus terbatas dan ditebas. Misalnya di kawasan Cibubur dibangun perumahan yang mampu menampung 1.000 orang, padahal lahan yang digunakan bisa menampung 10.000 orang jika dibangun apartemen. Bayangkan, berapa besar penghematannya dan berapa ribu orang yang akan memperoleh manfaatnya. Pemerintah tidak sadar kondisi ini, dan sekarang saatnya pemerintah melakukan pembenahan.
Nah, terkait masalah ketersediaan lahan, tingginya kebutuhan hunian membuat banyak lahan produktif, misalnya lahan pertanian, perkebunan, dan hutan diubah menjadi perumahan. Penyediaan tempat tinggal dengan model rumah tapak atau landed house, jumlahnya harus mulai dikurangi. Sebab, semakin lama jumlah lahan mulai terbatas. Jika rumah tapak tetap dipaksakan akan berimbas terhadap konversi lahan.
Bayangkan, untuk 2 hektare lahan bisa dibangun 2.000 unit hunian dengan 2 tower. Jika 2.000 unit itu berupa rumah tapak, maka yang dibutuhkan bisa mencapai 20 hektare lahan. Keterbatasan lahan mengakibatkan harga lahan di perkotaan menjulang tinggi. Ketimbang rumah tapak, maka hunian vertikal seharusnya menjadi pilihan, terutama di kota besar.
Namun, fakta menunjukkan jumlah apartemen tahun lalu tidak mencapai target. Salah satunya dikarenakan proses pembangunan yang berjalan lambat atau molor. Banyak kendala yang terjadi di lapangan. Salah satunya proses perizinan yang berbelit-belit.
Kalau kebijakan ini diterapkan secara konsisten diseluruh perkotaan di seluruh Indonesia, secara otomatis akan memberikan dampak positif bagi penghematan tanah sekaligus akan lebih banyak menyediaakan ruang terbuka hijau (RTH). Karena dengan contoh rumah di Menteng dengan setiap satu hektare tanah, rumah di Menteng dengan KLB 0,5 akan lebih boros dibanding dengan KLB 10.
Praktisi Industri Properti
PEMERINTAHAN Joko Widodo telah menempatkan reforma agraria sebagai prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.
Tanah seluas 9 juta hektare menjadi rencana redistribusi tanah dan legalisasi aset di bawah payung reforma agraria. Sumber tanahnya berasal dari kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan (perkebunan). Sedangkan dalam rangka memperluas wilayah kelola masyarakat di kawasan hutan, target 12,7 juta hektare hendak dialokasikan untuk dapat diberikan izin kelolanya kepada masyarakat.
Namun kebijakan itu masih bersifat sektoral perkebunan, kehutanan dan pedesaan. Sebaknya tujuan reforma agraria seharusnya multi sektoral. Sehingga dapat menyelesaikan ketimpangan struktural di wilayah pertambangan, pesisir, kelautan, pulau-pulau kecil dan khususnya Reforma Agraria di sektor perkotaan (urban). Tulisan ini tidak bermaksud membahas sektor-sektor lainnya hanya ingin mengelupas tentang Reforma Agraria dalam bidang perkotaan (urban)
Presiden Joko Widodo juga sudah mengeluarkan kebijakan paket ekonomi dengan menyederhanakan perizinan dan lain-lain untuk mempercepat perizinan pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam perencanaan pembangunan perumahan, sejatinya perlu dibuat riset terlebih dahulu. Karena ternyata semua kebijakan paket ekonomi ternyata pengaruhnya lebih arah kota bukan untuk mengatasi kesenjanganuntuk MBR, seperti Backlog yang terus bertambah sekitar 800 ribu rumah setiap tahun. Sedangkan pemenuhan rumah tak bisa menutupi kesenjangan.
Salah satu indikasinya tentu saja karena faktor keterbatasan lahan dan harga tanah yang semakin mahal. Pemerintah tak mungkin menyelesaikan sendiri, perlu memberdayakan pihak swasta.
Memberdayakan artinya tidak merugikan pihak swasta secara bisnis atau ekonomi, melainkan memberikan insentif karena membantu program pemerintah untuk mengatasi Backlog yang sekarang telah mencapai 11 juta rumah. Insentif dari pemerintah tidak harus diberikan subsidi atau uang tapi cukup dengan kebijakan yang konsisten.
Backlog rumah tinggal diperkotaan sebenarnya dapat dibagi dalam dua kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pertama adalah kebutuhan untuk masyarakat yang bekerja secara mandiri dan kedua untuk masyarakat yang bekerja pada orang lain (pegawai pemerintah dan pegawai swasta). Sudah ada contoh negara yang berhasil mengatasi kesenjangan kepemilikan rumah ini, yaitu Singapura yang berhasil menjalankan subsidi silang dan bergotong-royong.
Ada tiga cara negara itu membuat kebijakan. Pertama, kepada seluruh pekerja baik mandiri atau bekerja pada orang lain diwajibkan menabung sesuai dengan penghasilannya. Kedua, pihak pemberi kerja, baik itu pemerintah atau swasta diminta berkontribusi dengan menambah tabungan pekerjanya. Ketiga, dana tersebut akan dikelola oleh pemerintah yang fokus membangun rumah MBR. Masyarakat tadi bisa langsung mengajukan pembelian dengan menggunakan tabungannya sebagai DP tentu saat tabungan mencapai jumlah tertentu.
Reforma Agraria diperlukan untuk mengendalikan harga tanah yang terus menerus naik, dan tampaknya pemerintah tak mungkin memaksa menurunkan harga tanah. Tetapi memberikan insentif bila setiap jengkal tanah atau setiap meter persegi dimaksimalkan intensitasnya bangunan ke atas dan memberikan denda untuk setiap pemborosan tanah di perkotaan.
Misalnya KLB harus dibatasi dan tidak lagi mengizinkan pembangunan kawasan hunian dengan mayoritas landed house. Atau jika memang diperlukan harus dengan syarat yang ketat. Ini agar tidak terjadi perambahan lahan. Prinsip utamanya lahan harus dihemat.
Selama ini, pemerintah tidak konsisten dalam penyediaan hunian vertikal. Padahal perannya sangat besar memenuhi backlog perumahan. Pembangunan apartemen misalnya, malah dihambat, dipersulit dengan beragam aturan. Banyak ongkos yang harus dikeluarkan pengembang termasuk ongkos politik. Tentu ini tidak baik bagi iklim investasi di Indonesia, khususnya dalam rangka penyediaan perumahan.
Pengembang jangan dibebani ongkos politik. Justru seharusnya bagi mereka yang membangun apartemen harus diapersiasi karena sudah memberikan solusi akibat mahalnya harga tanah.
Contoh, membangun rumah di Menteng dengan harga tanah sekitar Rp100 juta per meter persegi, ada satu orang membeli atau menguasai 1.000 meter persegi tetapi hanya dibangun 500 meter persegi, itu berarti KLB (koefisiensi luas bangunan) hanya 0,5 dibanding dengan developer yang akan membangun tanah yang sama untuk dibangun rumah susun seluas 10.000 meter persegi yang mempunyai KLB sebesar 10.
Jadi mana yang lebih dibutuhkan dalam menunjang program pemerintah? Tentunya developer yang membangun dengan KLB 10. Bagaimana pemerintah bersikap dalam memberikan insentif untuk pihak yang membangun dengan KLB 10 dibanding dengan developer yang membangun rumah tapak dengan KLB 0,5.
Karena KLB 10 dengan 50 meter persegi per unit akan dapat menyediakan 200 tempat tinggal. Itu hanya contoh untuk seribu meter, lalu bagaiman dengan rumah tapak yang terus dibangun dengan memboroskan tanah ribuah ratusan hingga ribuan hektare?
Kelak di dunia tidak ada lagi landed house baru, karena lahan terus terbatas dan ditebas. Misalnya di kawasan Cibubur dibangun perumahan yang mampu menampung 1.000 orang, padahal lahan yang digunakan bisa menampung 10.000 orang jika dibangun apartemen. Bayangkan, berapa besar penghematannya dan berapa ribu orang yang akan memperoleh manfaatnya. Pemerintah tidak sadar kondisi ini, dan sekarang saatnya pemerintah melakukan pembenahan.
Nah, terkait masalah ketersediaan lahan, tingginya kebutuhan hunian membuat banyak lahan produktif, misalnya lahan pertanian, perkebunan, dan hutan diubah menjadi perumahan. Penyediaan tempat tinggal dengan model rumah tapak atau landed house, jumlahnya harus mulai dikurangi. Sebab, semakin lama jumlah lahan mulai terbatas. Jika rumah tapak tetap dipaksakan akan berimbas terhadap konversi lahan.
Bayangkan, untuk 2 hektare lahan bisa dibangun 2.000 unit hunian dengan 2 tower. Jika 2.000 unit itu berupa rumah tapak, maka yang dibutuhkan bisa mencapai 20 hektare lahan. Keterbatasan lahan mengakibatkan harga lahan di perkotaan menjulang tinggi. Ketimbang rumah tapak, maka hunian vertikal seharusnya menjadi pilihan, terutama di kota besar.
Namun, fakta menunjukkan jumlah apartemen tahun lalu tidak mencapai target. Salah satunya dikarenakan proses pembangunan yang berjalan lambat atau molor. Banyak kendala yang terjadi di lapangan. Salah satunya proses perizinan yang berbelit-belit.
Kalau kebijakan ini diterapkan secara konsisten diseluruh perkotaan di seluruh Indonesia, secara otomatis akan memberikan dampak positif bagi penghematan tanah sekaligus akan lebih banyak menyediaakan ruang terbuka hijau (RTH). Karena dengan contoh rumah di Menteng dengan setiap satu hektare tanah, rumah di Menteng dengan KLB 0,5 akan lebih boros dibanding dengan KLB 10.
(ven)