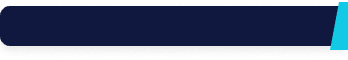Harga EBT Makin Murah, Skema Feed in Tariff di RUU EBT Tak Relevan
loading...

Para pakar dalam diskusi Regulasi EBT untuk Siapa? di acara Polemik MNC Trijaya menilai skema feed in tariff di RUU EBT perlu dihapuskan. Foto/M Faizal
A
A
A
JAKARTA - Akademisi dan pemerhati sektor energi mempertanyakan skema feed in tarif dalam Rancangan Undang-undang Energi Baru Terbarukan ( RUU EBT ) yang tengah digodok pemerintah. Sebab, skema tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dan berpotensi membebani anggaran ke depan.
Secara sederhana, skema feed in tariff artinya menetapkan harga energi baru terbarukan (EBT) di awal kontrak untuk jangka waktu tertentu, dan tidak dapat dinegosiasikan. Dengan aturan itu, diharapkan ada kepastian harga yang membuat investor antusias membangun pembangkit berbasis EBT di Indonesia.
Namun, dalam diskusi bertajuk "Regulasi EBT untuk Siapa?" di acara Polemik MNC Trijaya, Profesor Mukhtasor dari ITS mengatakan skema itu sudah tidak relevan dan bahkan berpotensi menimbulkan beban dalam jangka panjang bagi negara.
"Tren (harga EBT) di dunia internasional itu semakin turun. IEA menunjukkan, jika di 2015 tender PLTS itu (harga jual listriknya) USD20 sen/kWh sekarang sudah turun drastis jadi USD4-5 sen/kWh dan ini ke depan akan turun lagi. Jadi feed in tariff ini nggak berlaku lagi untuk sekarang," ujarnya, Sabtu (4/9/2021).
Mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) itu menambahkan, skema ini dulunya digunakan karena pengembangan EBT masih mahal sehingga butuh insentif. Namun, kebijakan insentif melalui feed in tariff ini juga diikuti upaya menumbuhkan industri terkait EBT di dalam negeri sehingga feed in tariff itu juga menciptakan nilai tambah seperti serapan tenaga kerja oleh industri, pajak, dan lainnya. "Nah di Indonesia kan tidak. Jadi insentifnya itu amblas begitu saja, hanya dinikmati pembangkit swasta," tuturnya.
Mukhtasor menambahkan, RUU EBT harus disinkronisasi dengan undang-undang ataupun regulasi lainnya, seperti regulasi pengembangan industri dalam negeri. Dia menegaskan, insentif sebaiknya disalurkan untuk menciptakan kemandirian industri nasional di bidang EBT, semisal pada industri dalam negeri yang mengembangkan dan memproduksi panel surya, turbin, dan sebagainya.
"Intinya bangun dulu ekonomi produktif, jangan modal nasional nanti habis untuk feed in tariff saja tanpa ada nilai tambahnya. Hapus feed in tariff dari RUU EBT," tegasnya.
Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif IRRES Marwan Batubara. Terkait kemajuan teknologi, kata dia, jika harga jual listrik EBT dari pembangkit swasta diikat dari awal dengan kontrak jangka panjang, maka PLN dan negara akan dirugikan.
Marwan mencontohkan PLTS Kupang yang diteken pada 2015 mematok dengan harga listrik USD25 sen/kWh untuk jangka waktu sekitar 20 tahun. Sementara, pada 2017 dibangun PLTS Likupang di Minahasa Utara dengan harga listrik hanya USD10,8 sen/kWh. Bahkan, pada 2020 lalu dibangun PLTS Cirata 145 MW yang harga listriknya lebih rendah lagi, hanya USD5,8 sen/kWh.
"Artinya dengan perkembangan teknologi harga listrik EBT semakin kompetitif. Jadi kalau diikat dengan feed in tariff yang masa berlakunya sangat lama, ini akan jadi beban bagi PLN dan ujungnya harus dibayar oleh pelanggan atau disubsidi negara," cetusnya.
Karena itu, Marwan menilai jika pemerintah bersikeras mengadopsi skema feed in tariff yang sudah ditinggalkan di banyak negara dalam regulasi EBT, maka patut diduga motif bisnislah yang menjadi dasarnya karena hanya menguntungkan pengusaha. "Kalau pro-rakyat, jangan dengar dari sisi pengusaha saja," tandasnya.
Marwan menilai skema feed in tariff berpotensi menjadi beban berat seperti kewajiban take or pay (TOP) listrik swasta di tengah kondisi kelebihan pasokan listrik di sistem Jawa-Bali dan Sumatera saat ini. "PLN punya utang begitu banyak, salah satunya gara-gara skema TOP ini. Janganlah ditambah lagi dengan skema feed in tariff ini," ujarnya.
Secara sederhana, skema feed in tariff artinya menetapkan harga energi baru terbarukan (EBT) di awal kontrak untuk jangka waktu tertentu, dan tidak dapat dinegosiasikan. Dengan aturan itu, diharapkan ada kepastian harga yang membuat investor antusias membangun pembangkit berbasis EBT di Indonesia.
Namun, dalam diskusi bertajuk "Regulasi EBT untuk Siapa?" di acara Polemik MNC Trijaya, Profesor Mukhtasor dari ITS mengatakan skema itu sudah tidak relevan dan bahkan berpotensi menimbulkan beban dalam jangka panjang bagi negara.
"Tren (harga EBT) di dunia internasional itu semakin turun. IEA menunjukkan, jika di 2015 tender PLTS itu (harga jual listriknya) USD20 sen/kWh sekarang sudah turun drastis jadi USD4-5 sen/kWh dan ini ke depan akan turun lagi. Jadi feed in tariff ini nggak berlaku lagi untuk sekarang," ujarnya, Sabtu (4/9/2021).
Mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) itu menambahkan, skema ini dulunya digunakan karena pengembangan EBT masih mahal sehingga butuh insentif. Namun, kebijakan insentif melalui feed in tariff ini juga diikuti upaya menumbuhkan industri terkait EBT di dalam negeri sehingga feed in tariff itu juga menciptakan nilai tambah seperti serapan tenaga kerja oleh industri, pajak, dan lainnya. "Nah di Indonesia kan tidak. Jadi insentifnya itu amblas begitu saja, hanya dinikmati pembangkit swasta," tuturnya.
Mukhtasor menambahkan, RUU EBT harus disinkronisasi dengan undang-undang ataupun regulasi lainnya, seperti regulasi pengembangan industri dalam negeri. Dia menegaskan, insentif sebaiknya disalurkan untuk menciptakan kemandirian industri nasional di bidang EBT, semisal pada industri dalam negeri yang mengembangkan dan memproduksi panel surya, turbin, dan sebagainya.
"Intinya bangun dulu ekonomi produktif, jangan modal nasional nanti habis untuk feed in tariff saja tanpa ada nilai tambahnya. Hapus feed in tariff dari RUU EBT," tegasnya.
Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif IRRES Marwan Batubara. Terkait kemajuan teknologi, kata dia, jika harga jual listrik EBT dari pembangkit swasta diikat dari awal dengan kontrak jangka panjang, maka PLN dan negara akan dirugikan.
Marwan mencontohkan PLTS Kupang yang diteken pada 2015 mematok dengan harga listrik USD25 sen/kWh untuk jangka waktu sekitar 20 tahun. Sementara, pada 2017 dibangun PLTS Likupang di Minahasa Utara dengan harga listrik hanya USD10,8 sen/kWh. Bahkan, pada 2020 lalu dibangun PLTS Cirata 145 MW yang harga listriknya lebih rendah lagi, hanya USD5,8 sen/kWh.
"Artinya dengan perkembangan teknologi harga listrik EBT semakin kompetitif. Jadi kalau diikat dengan feed in tariff yang masa berlakunya sangat lama, ini akan jadi beban bagi PLN dan ujungnya harus dibayar oleh pelanggan atau disubsidi negara," cetusnya.
Karena itu, Marwan menilai jika pemerintah bersikeras mengadopsi skema feed in tariff yang sudah ditinggalkan di banyak negara dalam regulasi EBT, maka patut diduga motif bisnislah yang menjadi dasarnya karena hanya menguntungkan pengusaha. "Kalau pro-rakyat, jangan dengar dari sisi pengusaha saja," tandasnya.
Marwan menilai skema feed in tariff berpotensi menjadi beban berat seperti kewajiban take or pay (TOP) listrik swasta di tengah kondisi kelebihan pasokan listrik di sistem Jawa-Bali dan Sumatera saat ini. "PLN punya utang begitu banyak, salah satunya gara-gara skema TOP ini. Janganlah ditambah lagi dengan skema feed in tariff ini," ujarnya.
(fai)