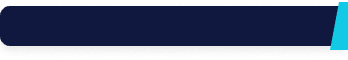Tiket Pesawat Mahal, Kemenhub Diminta Introspeksi Jangan Salahkan Maskapai

Tiket Pesawat Mahal, Kemenhub Diminta Introspeksi Jangan Salahkan Maskapai
A
A
A
JAKARTA - Menekan maskapai penerbangan untuk menurunkan tarif tiket pesawat tanpa didasarkan pada analisa yang benar menurut pengamat, berpotensi membahayakan keselamatan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta justru harus introspeksi diri mengapa tarif pesawat mahal, bukan terus menyalahkan maskapai.
“Apabila pemerintah memaksakan tarif pesawat turun sehingga maskapai menjadi rugi, berarti masyarakat dibiarkan menggunakan maskapai yang tidak sehat sehingga membahayakan keselamatan,” kata Praktisi dan pemerhati masalah transportasi logistik, Bambang Haryo Soekartono di Jakarta.
Hal ini menanggapi pernyataan Menhub Budi Karya Sumadi sebelumnya, dimana menyebutkan tarif pesawat akan turun 30% pada Senin-Kamis setiap minggu hingga Februari 2020. Menhub juga mengaku sudah mendapat komitmen itu dari Garuda Indonesia, yang diyakini bakal diikuti maskapai lainnya.
Sebagai penyedia sarana transportasi, tutur Bambang Haryo, maskapai penerbangan bertanggung jawab terhadap keselamatan nyawa dan barang publik yang diangkutnya, sehingga harus mendapatkan tarif yang cukup dan transparan.
Dia mengingatkan, pemerintah khususnya Kemenhub bisa introspeksi diri kenapa tarif pesawat mahal dan maskapai mengalami kerugian. Bahkan, maskapai sekelas Garuda Indonesia pun pernah mencatat kerugian hingga Rp3 trilun pada 2017 dan Rp1,6 trilun pada 2018, padahal saat itu tarif pesawat relatif tinggi. “Kita tidak ingin kerugian ini terulang dan tambah besar,” tegasnya.
Menurut Bambang Haryo, tarif pesawat yang tinggi saat ini bukan sepenuhnya kesalahan maskapai, melainkan justru akibat kebijakan dalam mengelola transportasi udara. Berdasarkan analisanya, setidaknya ada lima faktor yang menyebabkan tarif pesawat menjadi mahal. Pertama, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah melonjak lebih dari 60% dari sekitar Rp9.000 pada 2012 menjadi Rp14.000 pada 2019.
Depresiasi rupiah berdampak terhadap peningkatan tarif pesawat akibat lonjakan harga komponen pesawat, avtur, MRO, utang, dan biaya lain yang masih banyak mengacu ke dolar AS. “Solusinya, ekonomi harus diperbaiki supaya rupiah kembali menguat, kalau ekonomi masih lesu ya susah," sambungnya.
Kedua, walaupun harga avtur diturunkan tetapi konsumsi bahan bakar itu tetap tinggi sebab pesawat yang akan mendarat di semua bandara komersial masih harus antre atau holding. Avtur yang dihabiskan untuk holding ini bahkan lebih besar daripada insentif avtur untuk maskapai.
Dicontohkan oleh Bambang Haryo, penerbangan Jakarta-Yogyakarta yang dulunya hanya butuh waktu 45 menit, sekarang rute ini bisa menghabiskan 1 jam 5 menit, sehingga konsumsi avtur naik hampir 50%.
Lebih lanjut terang dia mengatakan, kemampuan Airnav harus segera ditingkatkan karena produktivitas runway bandara komersial sangat rendah. Bandara Soekarno-Hatta Jakarta hanya bisa melayani tidak lebih dari 30 take off dan landing pesawat per runway per jam. Sebagai perbandingan, Bandara Heattrow Inggris bisa mencapai 100 take off landing per jam per runway.
Selain itu, waktu tunggu pesawat masih terlalu lama sehingga maskapai harus membayar banyak biaya tambahan. “Penumpang sering kali menunggu lama di dalam pesawat sebelum terbang. Penyelenggara trafik angkutan udara sangat lamban, avtur menjadi boros dan produktivitas maskapai rendah.”
Ketiga, tiket pesawat mahal karena pemerintah tidak menyiapkan bandara khusus untuk maskapai low cost (LCC) sehingga terjadi pemborosan sangat besar. LCC wajib menggunakan terminal, apron dan runway untuk maskapai full service.
“Masyarakat dirugikan karena harus bayar pajak bandara dan semua fasilitas pembelian selama di terminal dengan harga komersial untuk maskapai full service,” kata Bambang Haryo.
Kondisi ini juga merugikan maskapai full service karena kesulitan pelayanan akibat banyaknya pesawat LCC yang mendarat di terminal yang sama. Campur aduk antara LCC dan full service ini membuat bandara padat sehingga tarif menjadi tidak menentu.
Keempat, tarif tinggi karena masyarakat sulit mendapatkan tempat duduk karena kapasitas pesawat yang tersedia terbatas di rute-rute gemuk, terutama pada saat musim padat penumpang (peak season).
Kondisi ini disebabkan semua maskapai menggunakan pesawat kecil (narrow body) di rute gemuk tersebut. “Seharusnya rute gemuk seperti Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, saat peak season menggunakan pesawat wide body sehingga ada keseimbangan antara supply dan demand,” ungkapnya.
Yang mengherankan, regulasi ini diterapkan di kapal ferry tetapi dengan tarif sangat murah. Bahkan, saat musim sepi penumpang pun penyeberangan diwajibkan operasikan kapal di atas 5.000 GT.
Faktor kelima, lanjut Bambang Haryo, birokrasi dan perizinan cenderung highly regulated sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi. “Jadi tidak heran, walaupun Airasia menjual tiket murah di Indonesia tapi bisa untung di atas Rp1,5 trilun tiap tahun, karena lebih banyak beroperasi di luar negeri yang tidak terjadi ekonomi biaya tinggi,” ujarnya.
“Apabila pemerintah memaksakan tarif pesawat turun sehingga maskapai menjadi rugi, berarti masyarakat dibiarkan menggunakan maskapai yang tidak sehat sehingga membahayakan keselamatan,” kata Praktisi dan pemerhati masalah transportasi logistik, Bambang Haryo Soekartono di Jakarta.
Hal ini menanggapi pernyataan Menhub Budi Karya Sumadi sebelumnya, dimana menyebutkan tarif pesawat akan turun 30% pada Senin-Kamis setiap minggu hingga Februari 2020. Menhub juga mengaku sudah mendapat komitmen itu dari Garuda Indonesia, yang diyakini bakal diikuti maskapai lainnya.
Sebagai penyedia sarana transportasi, tutur Bambang Haryo, maskapai penerbangan bertanggung jawab terhadap keselamatan nyawa dan barang publik yang diangkutnya, sehingga harus mendapatkan tarif yang cukup dan transparan.
Dia mengingatkan, pemerintah khususnya Kemenhub bisa introspeksi diri kenapa tarif pesawat mahal dan maskapai mengalami kerugian. Bahkan, maskapai sekelas Garuda Indonesia pun pernah mencatat kerugian hingga Rp3 trilun pada 2017 dan Rp1,6 trilun pada 2018, padahal saat itu tarif pesawat relatif tinggi. “Kita tidak ingin kerugian ini terulang dan tambah besar,” tegasnya.
Menurut Bambang Haryo, tarif pesawat yang tinggi saat ini bukan sepenuhnya kesalahan maskapai, melainkan justru akibat kebijakan dalam mengelola transportasi udara. Berdasarkan analisanya, setidaknya ada lima faktor yang menyebabkan tarif pesawat menjadi mahal. Pertama, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah melonjak lebih dari 60% dari sekitar Rp9.000 pada 2012 menjadi Rp14.000 pada 2019.
Depresiasi rupiah berdampak terhadap peningkatan tarif pesawat akibat lonjakan harga komponen pesawat, avtur, MRO, utang, dan biaya lain yang masih banyak mengacu ke dolar AS. “Solusinya, ekonomi harus diperbaiki supaya rupiah kembali menguat, kalau ekonomi masih lesu ya susah," sambungnya.
Kedua, walaupun harga avtur diturunkan tetapi konsumsi bahan bakar itu tetap tinggi sebab pesawat yang akan mendarat di semua bandara komersial masih harus antre atau holding. Avtur yang dihabiskan untuk holding ini bahkan lebih besar daripada insentif avtur untuk maskapai.
Dicontohkan oleh Bambang Haryo, penerbangan Jakarta-Yogyakarta yang dulunya hanya butuh waktu 45 menit, sekarang rute ini bisa menghabiskan 1 jam 5 menit, sehingga konsumsi avtur naik hampir 50%.
Lebih lanjut terang dia mengatakan, kemampuan Airnav harus segera ditingkatkan karena produktivitas runway bandara komersial sangat rendah. Bandara Soekarno-Hatta Jakarta hanya bisa melayani tidak lebih dari 30 take off dan landing pesawat per runway per jam. Sebagai perbandingan, Bandara Heattrow Inggris bisa mencapai 100 take off landing per jam per runway.
Selain itu, waktu tunggu pesawat masih terlalu lama sehingga maskapai harus membayar banyak biaya tambahan. “Penumpang sering kali menunggu lama di dalam pesawat sebelum terbang. Penyelenggara trafik angkutan udara sangat lamban, avtur menjadi boros dan produktivitas maskapai rendah.”
Ketiga, tiket pesawat mahal karena pemerintah tidak menyiapkan bandara khusus untuk maskapai low cost (LCC) sehingga terjadi pemborosan sangat besar. LCC wajib menggunakan terminal, apron dan runway untuk maskapai full service.
“Masyarakat dirugikan karena harus bayar pajak bandara dan semua fasilitas pembelian selama di terminal dengan harga komersial untuk maskapai full service,” kata Bambang Haryo.
Kondisi ini juga merugikan maskapai full service karena kesulitan pelayanan akibat banyaknya pesawat LCC yang mendarat di terminal yang sama. Campur aduk antara LCC dan full service ini membuat bandara padat sehingga tarif menjadi tidak menentu.
Keempat, tarif tinggi karena masyarakat sulit mendapatkan tempat duduk karena kapasitas pesawat yang tersedia terbatas di rute-rute gemuk, terutama pada saat musim padat penumpang (peak season).
Kondisi ini disebabkan semua maskapai menggunakan pesawat kecil (narrow body) di rute gemuk tersebut. “Seharusnya rute gemuk seperti Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, saat peak season menggunakan pesawat wide body sehingga ada keseimbangan antara supply dan demand,” ungkapnya.
Yang mengherankan, regulasi ini diterapkan di kapal ferry tetapi dengan tarif sangat murah. Bahkan, saat musim sepi penumpang pun penyeberangan diwajibkan operasikan kapal di atas 5.000 GT.
Faktor kelima, lanjut Bambang Haryo, birokrasi dan perizinan cenderung highly regulated sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi. “Jadi tidak heran, walaupun Airasia menjual tiket murah di Indonesia tapi bisa untung di atas Rp1,5 trilun tiap tahun, karena lebih banyak beroperasi di luar negeri yang tidak terjadi ekonomi biaya tinggi,” ujarnya.
(akr)