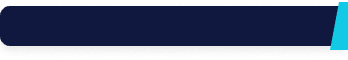Kisruh Batubara Momentum Perbaikan Tata Kelola Energi di Masa Transisi
loading...

Pemanfaatan sumber daya alam untuk energi harus mempertimbangkan aspek keandalan.
A
A
A
JAKARTA - Krisis pasokan batubara untuk pembangkit listrik dan industri di dalam negeri menjadi pelajaran mahal akan pentingnya ketahanan energi nasional. Kondisi ini juga seharusnya juga menjadi momentum bagi pemangku kepentingan dalam memperbaiki tata kelola komoditas sumber daya alam (SDA) terutama bagi sektor energi yang menjadi motor penggerak ekonomi.
Tahun ini, sektor energi dipastikan akan menghadapi tantangan cukup besar. Selain kecenderungan harga komoditas yang terus bergerak naik, isu transisi energi juga mendapat perhatian serius. Tak hanya di dalam negeri, tetapi juga di tataran global.
Sejak dua tahun terakhir, transisi energi terus digaungkan. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung energi bersih sesuai pesan dari konferensi tingkat tinggi (KTT) Iklim yang diinisiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030.
Penggunaan energi bersih memang suatu keniscayaan. Cepat atau lambat, implementasi energi hijau yang bersumber dari sumber-sumber ramah lingkungan akan terjadi. Tak ayal, perhatian pun kini tertuju pada sumber energi primer berupa fosil yang masih menjadi andalan pasokan energi di bumi Pertiwi.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, saat ini bauran energi nasional masih didominasi sumber energi fosil berupa batu bara sebanyak 38%, minyak bumi 31,6%, gas alam 19,2% dan energi baru terbarukan (EBT) 11,2%. Dengan komposisi tersebut, sangat jelas apabila porsi energi yang berasal dari fosil yakni minyak dan batu bara masih sangat dominan yakni 69,6%. Adapun untuk porsi EBT, seiring dengan program transisi energi, pemerintah telah menargetkan bauran EBT ditargetkan mencapai 23% pada 2025.
Melihat data di atas, pantas kiranya apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar para pihak terkait seperti pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki domain di sektor energi untuk mempercepat transisi energi menjadi ke energi ramah lingkungan. Pernyataan Presiden bisa jadi karena merujuk pada besarnya potensi SDA ramah lingkungan yang dimiliki.
Sebut saja misalnya, potensi panas bumi yang mencapai 23,9 gigawat (atau 23.900 Megawat/MW) namun baru termanfaatkan sekitar 2.130 MW saja. Demikian juga tenaga surya yang potensinya mencapai 207.800 MW, namun baru termanfaatkan 182,3 megawatt peak (MWp). Di samping itu ada pula tenaga bayu (angin) yang potensinya mencapai 60.600 MW dan baru dimanfaatkan 154,3 MW. Kemudian, bioenergy yang potensinya 65.200 MW dan baru dimanfaatkan 1.916,4 MW. Adapun tenaga hidro dan gelombang samudera potensinya masing-masing mencapai 75.000 MW dan 17.900 MW. Untuk tenaga hidro baru termanfaatkan sebesar 6.286 MW, sementara sumber energi dari gelombang samudera sama sekali belum digarap.
Melihat potensi besar tersebut, ada optimisme yang besar bahwa Indonesia akan mampu mengejar ketertinggalan dalam memanfaatkan sumber-sumber energi bersih. Akan tetapi, harus diingat bahwa potensi besar energi ramah lingkungan itu akan sangat tergantung pada kondisi kondisi cuaca dan musim. Sehingga apabila ingin menjadikan sistem energi yang memasok secara kontinu selama 24 jam sehari, harus dibarengi teknologi penyimpanan yang memadai.
Misalnya saja pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang akhir-akhir ini digembar-gemborkan bisa menjadi alternatif sebagai pengganti listrik dari batu bara. Untuk menghasilkan listrik, rata-rata PLTS ini maksimal hanya efektif menyerap sinar matahari maksimal delapan jam per hari. Sementara untuk malam hari dipastikan tidak bisa memproduksi listrik, kecuali ada penyimpanan energi berupa baterai berkapasitas besar untuk memasok listrik sepanjang malam. Ini tentu saja berbeda dengan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara yang bisa membangkitkan listriknya kapan saja.
Kembali ke persoalan pasokan listrik seperti disampaikan di awal tadi, kondisi ini bisa menggambarkan bahwa transisi energi kian dekat. Coba bayangkan, apabila sebelumnya di negeri ini sudah terbangun sistem pasokan energi bersih yang tidak mengandalkan batu bara atau minyak bumi, mungkin kita tidak terlalu khawatir akan kelangkaan batubara karena sudah ada sumber energi lain yang siap menyuplai.
Tapi, alih-alih mempercepat transisi energi, ketersediaan sumber daya alam termasuk batu bara semestinya tetap menjadi pertimbangan tersendiri. Dengan status sebagai eksportir terbesar batu bara ke pasar global, di mana setiap tahunnya mengekspor hampir 500 juta metrik ton, Indonesia tidak semestinya mengalami krisis energi.
Artinya, pertimbangan ketahanan energi semestinya menjadikan kita raksasa komoditas strategis tanpa mengesampaingkan kepentingan nasional. Lagi-lagi hal ini sangat berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki. Apalagi dalam UUD 1945 pasal 33 disebutkan bahwa kekayaan negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Maka, isu krisis pasokan batu bara ke pembangkit listrik dan pengguna lain di sejumlah industri seharusnya menjadi cermin bagaimana pengelolaan energi agar tetap berkelanjutan.
Sedikit berbeda dengan minyak bumi, kendati masa transisi energi memungkinkan bahan bakar fosil ini ditinggalkan secara perlahan, namun kenyataannya minyak bumi masih tetap dibutuhkan, bahkan untuk beberapa dekade ke depan. Hal ini terlihat berbagai kebijakan pemerintah yang masih memberikan karpet merah bagi pengembangan sektor minyak dan gas (migas).
Bahkan, di tengah isu transisi energi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari (bph) pada 2030. Hal ini mengindikasikan bahwa paling tidak selama satu dekad ke depan, industri migas akan terus bergeliat seiring dengan bertambahnya konsumsi minyak untuk transportasi, industri maupun sektor lainnya. Target tersebut, kendati terlihat berat namun bukan mustahil dicapai.
Menteri ESDM Arifin Tasrif pada akhir tahun lalu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan industri hulu minyak dan gas bumi (migas) di tengah upaya transisi energi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang masif dilakukan.
Menurut dia, industri hulu migas yang berperan dalam mencari cadangan, menproduksi dan mengamankan pasokan migas tetap menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia. Kendati demikian, kata dia, di masa transisi energi ini Indonesia juga mendukung pendukung program karbon rendah dan berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon pada 2060 atau lebih cepat
“Kami juga terus berupaya meningkatkan pengembangan dan penggunaan energi terbarukan,” kata Arifin pada sebuah konferensi di Bali, Desember lalu.
Sementara itu, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti mengungkapkan, posisi energi Indonesia memang masih didominasi energi fosil. Saat ini EBT memang mulai berkontribusi seiring dengan dukungan terhadap pengurangan dampak perubahan iklim.
Akan tetapi, dia ,enilai pengembangan EBT di Tanah Air masih setengah hati karena komposisi energi masih ditopang oleh batu bara. Meski demikian, dia memastikan bahwa bagaimanapun kebijakan penyediaan energi yang terpenting adalah kemudahan dan keterjangkauan harga oleh konsumen.
“Energi harus mampu dibeli masyarakat dan mudah dijangkau,” katanya pada sebuah diskusi virtual beberapa waktu lalu.
Yayan juga memberikan catatan bahwa saat ini perkembangan pasar energi di Indonesia masih berada di supply side bukan di demand side. Padahal, kata dia, selain mengurus supply side, pemerintah seharusnya juga memperhatikan permintaan terhada energi.
Pernyataan tersebut sekaligus mengkritisi masifnya pembangunan pembangkit listrik sehingga pasokan listrik berlebi di sejumlah daerah terutama di Jawa dan Sumatera. Di sisi lain, permintaan tidak meningkat secara signifikan.
Tahun ini, sektor energi dipastikan akan menghadapi tantangan cukup besar. Selain kecenderungan harga komoditas yang terus bergerak naik, isu transisi energi juga mendapat perhatian serius. Tak hanya di dalam negeri, tetapi juga di tataran global.
Sejak dua tahun terakhir, transisi energi terus digaungkan. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung energi bersih sesuai pesan dari konferensi tingkat tinggi (KTT) Iklim yang diinisiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030.
Penggunaan energi bersih memang suatu keniscayaan. Cepat atau lambat, implementasi energi hijau yang bersumber dari sumber-sumber ramah lingkungan akan terjadi. Tak ayal, perhatian pun kini tertuju pada sumber energi primer berupa fosil yang masih menjadi andalan pasokan energi di bumi Pertiwi.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, saat ini bauran energi nasional masih didominasi sumber energi fosil berupa batu bara sebanyak 38%, minyak bumi 31,6%, gas alam 19,2% dan energi baru terbarukan (EBT) 11,2%. Dengan komposisi tersebut, sangat jelas apabila porsi energi yang berasal dari fosil yakni minyak dan batu bara masih sangat dominan yakni 69,6%. Adapun untuk porsi EBT, seiring dengan program transisi energi, pemerintah telah menargetkan bauran EBT ditargetkan mencapai 23% pada 2025.
Melihat data di atas, pantas kiranya apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar para pihak terkait seperti pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki domain di sektor energi untuk mempercepat transisi energi menjadi ke energi ramah lingkungan. Pernyataan Presiden bisa jadi karena merujuk pada besarnya potensi SDA ramah lingkungan yang dimiliki.
Sebut saja misalnya, potensi panas bumi yang mencapai 23,9 gigawat (atau 23.900 Megawat/MW) namun baru termanfaatkan sekitar 2.130 MW saja. Demikian juga tenaga surya yang potensinya mencapai 207.800 MW, namun baru termanfaatkan 182,3 megawatt peak (MWp). Di samping itu ada pula tenaga bayu (angin) yang potensinya mencapai 60.600 MW dan baru dimanfaatkan 154,3 MW. Kemudian, bioenergy yang potensinya 65.200 MW dan baru dimanfaatkan 1.916,4 MW. Adapun tenaga hidro dan gelombang samudera potensinya masing-masing mencapai 75.000 MW dan 17.900 MW. Untuk tenaga hidro baru termanfaatkan sebesar 6.286 MW, sementara sumber energi dari gelombang samudera sama sekali belum digarap.
Melihat potensi besar tersebut, ada optimisme yang besar bahwa Indonesia akan mampu mengejar ketertinggalan dalam memanfaatkan sumber-sumber energi bersih. Akan tetapi, harus diingat bahwa potensi besar energi ramah lingkungan itu akan sangat tergantung pada kondisi kondisi cuaca dan musim. Sehingga apabila ingin menjadikan sistem energi yang memasok secara kontinu selama 24 jam sehari, harus dibarengi teknologi penyimpanan yang memadai.
Misalnya saja pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang akhir-akhir ini digembar-gemborkan bisa menjadi alternatif sebagai pengganti listrik dari batu bara. Untuk menghasilkan listrik, rata-rata PLTS ini maksimal hanya efektif menyerap sinar matahari maksimal delapan jam per hari. Sementara untuk malam hari dipastikan tidak bisa memproduksi listrik, kecuali ada penyimpanan energi berupa baterai berkapasitas besar untuk memasok listrik sepanjang malam. Ini tentu saja berbeda dengan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara yang bisa membangkitkan listriknya kapan saja.
Kembali ke persoalan pasokan listrik seperti disampaikan di awal tadi, kondisi ini bisa menggambarkan bahwa transisi energi kian dekat. Coba bayangkan, apabila sebelumnya di negeri ini sudah terbangun sistem pasokan energi bersih yang tidak mengandalkan batu bara atau minyak bumi, mungkin kita tidak terlalu khawatir akan kelangkaan batubara karena sudah ada sumber energi lain yang siap menyuplai.
Tapi, alih-alih mempercepat transisi energi, ketersediaan sumber daya alam termasuk batu bara semestinya tetap menjadi pertimbangan tersendiri. Dengan status sebagai eksportir terbesar batu bara ke pasar global, di mana setiap tahunnya mengekspor hampir 500 juta metrik ton, Indonesia tidak semestinya mengalami krisis energi.
Artinya, pertimbangan ketahanan energi semestinya menjadikan kita raksasa komoditas strategis tanpa mengesampaingkan kepentingan nasional. Lagi-lagi hal ini sangat berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki. Apalagi dalam UUD 1945 pasal 33 disebutkan bahwa kekayaan negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Maka, isu krisis pasokan batu bara ke pembangkit listrik dan pengguna lain di sejumlah industri seharusnya menjadi cermin bagaimana pengelolaan energi agar tetap berkelanjutan.
Sedikit berbeda dengan minyak bumi, kendati masa transisi energi memungkinkan bahan bakar fosil ini ditinggalkan secara perlahan, namun kenyataannya minyak bumi masih tetap dibutuhkan, bahkan untuk beberapa dekade ke depan. Hal ini terlihat berbagai kebijakan pemerintah yang masih memberikan karpet merah bagi pengembangan sektor minyak dan gas (migas).
Bahkan, di tengah isu transisi energi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari (bph) pada 2030. Hal ini mengindikasikan bahwa paling tidak selama satu dekad ke depan, industri migas akan terus bergeliat seiring dengan bertambahnya konsumsi minyak untuk transportasi, industri maupun sektor lainnya. Target tersebut, kendati terlihat berat namun bukan mustahil dicapai.
Menteri ESDM Arifin Tasrif pada akhir tahun lalu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan industri hulu minyak dan gas bumi (migas) di tengah upaya transisi energi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang masif dilakukan.
Menurut dia, industri hulu migas yang berperan dalam mencari cadangan, menproduksi dan mengamankan pasokan migas tetap menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia. Kendati demikian, kata dia, di masa transisi energi ini Indonesia juga mendukung pendukung program karbon rendah dan berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon pada 2060 atau lebih cepat
“Kami juga terus berupaya meningkatkan pengembangan dan penggunaan energi terbarukan,” kata Arifin pada sebuah konferensi di Bali, Desember lalu.
Sementara itu, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti mengungkapkan, posisi energi Indonesia memang masih didominasi energi fosil. Saat ini EBT memang mulai berkontribusi seiring dengan dukungan terhadap pengurangan dampak perubahan iklim.
Akan tetapi, dia ,enilai pengembangan EBT di Tanah Air masih setengah hati karena komposisi energi masih ditopang oleh batu bara. Meski demikian, dia memastikan bahwa bagaimanapun kebijakan penyediaan energi yang terpenting adalah kemudahan dan keterjangkauan harga oleh konsumen.
“Energi harus mampu dibeli masyarakat dan mudah dijangkau,” katanya pada sebuah diskusi virtual beberapa waktu lalu.
Yayan juga memberikan catatan bahwa saat ini perkembangan pasar energi di Indonesia masih berada di supply side bukan di demand side. Padahal, kata dia, selain mengurus supply side, pemerintah seharusnya juga memperhatikan permintaan terhada energi.
Pernyataan tersebut sekaligus mengkritisi masifnya pembangunan pembangkit listrik sehingga pasokan listrik berlebi di sejumlah daerah terutama di Jawa dan Sumatera. Di sisi lain, permintaan tidak meningkat secara signifikan.
(ynt)