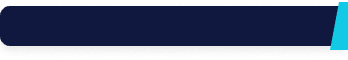Harga Minyak Sawit Melonjak, Candaan Petani: Saatnya Beli Pajero

Harga Minyak Sawit Melonjak, Candaan Petani: Saatnya Beli Pajero
A
A
A
AWAL tahun ini menjadi saat yang melegakan bagi industri sawit nasional. Bagaimana tidak, setelah dua tahun berturut-turut tertekan, harga minyak sawit (crude palm oil/CPO) kini mulai menunjukkan tajinya. Pada perdagangan Kamis pekan lalu (16/1/2020), harga CPO kontrak di Bursa Malaysia Derivatif (BMD) berada di level RM2.943 (US$723) per ton.
Memang harga itu telah menurun dibandingkan pada harga Jumat di pekan sebelumnya yang bertengger di angka RM3.095 (US$761,17). Toh tetap saja, level RM2.943 terbilang tinggi sejak Januari 2017. “Sekarang naik, kami bersyukur ada yang mengompensasi selama dua tahun terakhir,” kata Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), kepada SINDO Weekly, Kamis pekan lalu (16/1/2020).
Ada banyak faktor yang membuat harga minyak sawit melonjak. Dari luar negeri, gesekan politik antara Malaysia dan India terkait masalah Khasmir telah membakar harga CPO. Pemerintah India mengeluarkan kebijakan kepada dunia usahanya agar tak mengekspor minyak sawit dari Jiran. “Ada permasalahan India dan Malaysia, maka yang diuntungkan otomatis harga CPO untuk di Indonesia ini langsung naik,” kata Bhima Yudhistira, ekonom Indef, Selasa pekan lalu (14/1/2020).
Selain itu, Negeri Hindustan juga memberlakukan kebijakan tarif baru terhadap impor minyak sawit dan turunannya. India sebagai pembeli minyak nabati terbesar di dunia melakukan pemangkasan pada pajak impor CPO dan minyak sawit olahan. Pajak impor CPO diturunkan menjadi 37,5% dari 40%. Sementara, pajak untuk berbagai produk olahan minyak sawit menjadi 45% dari 50%.Informasi tersebut tentu menjadi kabar baik untuk CPO. Pasalnya, India mengandalkan impor minyak nabati untuk memenuhi 70% kebutuhan domestiknya. Dua pertiga impor minyak nabati tersebut disumbang minyak sawit dan olahannya. Pemangkasan pajak impor tersebut berpotensi untuk mendorong impor CPO dan olahannya oleh India.
United States Department Agriculture (USDA) mencatat, untuk periode 2019/2020 (Oktober–September), terjadi peningkatan permintaan CPO oleh India sebesar 3,1% menjadi 9,90 juta ton. Tiongkok juga meningkatkan permintaannya menjadi sebanyak 6,70 juta ton (naik 6,3%). Jika ditotal dengan kawasan dunia lainnya, permintaan CPO global naik sebesar 3,4% menjadi 51,6 juta ton.Dari dalam negeri, program mandatory biodiesel, mulai dari B20 dan sekarang B30, juga turut memengaruhi pergerakan harga minyak sawit. Program tersebut memberikan sentimen bahwa permintaan CPO domestik meningkat. “Jadi, itu sebenarnya faktor yang menjadi kombinasi sehingga harga naik,” kata Joko Supriyono.
Peningkatan kebutuhan domestik untuk program biodiesel itu telah mengubah komposisi permintaan antara domestik dan ekspor. Selama ini, pola permintaan domestik sebesar 30% dan ekspor 70%. Pada 2018, dengan total produksi sebanyak 43 juta ton, permintaan domestik mencapai 14 juta ton atau sekitar 33%. Tahun lalu, permintaan domestik itu mencapai 36%. “Artinya suplai ke luar pasar Indonesia otomatis akan berkurang,” tandas Joko.
Jika nanti mandatory biodiesel ditingkatkan lagi menjadi B40 dan B50, tentu saja permintaan akan minyak sawit domestik kian membesar. Kondisi itu tentu saja berdampak positif terhadap perekonomian dalam negeri. Pertama, kita tidak lagi dominan menggantungkan pada ekspor yang selama ini dilakukan.
Kenaikan permintaan domestik akan membuat keseimbangan baru antara ekspor dan dalam negeri. Dengan demikian, bisa saling menopang jika salah satu pasar itu bergolak atau anjlok. “Berarti pasar domestik cukup mampu mengimbangi kalau (di luar) ada gejolak,” kata Joko.
Jika ekspor CPO masih sangat dominan, harganya akan rentan dipengaruhi sentimen negatif dari luar negeri. Dengan adanya program B30, CPO bisa kita gunakan untuk kepentingan sendiri. “Jangan pernah khawatir tidak diminati oleh pasar,” kata Presiden Joko Widodo, belum lama ini.
Kedua, program B30 mampu menekan defisit neraca perdagangan yang selama ini kerap membayangi akibat tingginya volume impor bahan bakar minyak. Penggunaan CPO untuk B30 akan mengurangi impor BBM yang terbilang besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari–Oktober 2019, angka Impor minyak mentah tercatat US$4,343 miliar atau setara Rp60 triliun. Sementara, impor hasil minyak termasuk BBM tercatat US$11,195 miliar atau sekitar Rp156,7 triliun. Jika ditotal, impor minyak kita mencapai Rp216.7 triliun.
Pengurangan impor BBM ujung-ujungnya bisa menghemat devisa yang lumayan besar. Jika program biodiesel bisa menyerap produksi CPO hingga 10 juta kiloliter, devisa yang bisa dihemat Rp122,8 triliun. Program B30 yang baru diluncurkan saja sudah diperkirakan bisa menghemat devisa Rp63 triliun.
Nah, kenaikan harga CPO jelas akan membawa banyak dampak positif buat pihak-pihak yang berkecimpung. Kenaikan harga CPO akan membuat para petani semringah karena bisa meningkatkan harga tandan buah segar (TBS) milik petani. “Karena salah satu indikator dan rumusan pembelian harga TBS di petani itu adalah harga CPO,” kata Mansuetus Darto, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit, Rabu pekan lalu (15/01).
Saat ini, harga TBS di tingkat petani antara Rp1.800–1.900 per kg. Bahkan, harganya ada yang mencapai Rp2.100 per kg. “Jadi, peningkatan harga TBS petani ini terjadi kurang lebih dari Januari kemarin, sekitar 30%,” tambah Darto.
Sayangnya, tak semua petani menikmati kenaikan harga yang signifikan itu. Harga tadi hanya dinikmati oleh petani plasma, sedangkan untuk petani swadaya atau mandiri harganya hanya berkisar Rp1.200–1.300. “Petani swadaya tidak masuk dalam bingkai kemitraan,” jelas Darto.
Petani plasma adalah petani yang sejak dari awal, mulai dari tanam hingga pembersihan lahan, bermitra dengan perusahaan dan ada perjanjian (MoU) kemitraan dengan koperasi dan juga perusahaan. Sementara, petani swadaya atau petani mandiri yang memang membangun sendiri. Jika TBS petani plasma dibeli oleh perusahaan atau mitranya yang lain, TBS petani swadaya kebanyakan dibeli oleh para tengkulak.
Menurut Darto, harga-harga yang ditetapkan tengkulak cenderung tidak diawasi oleh pemerintah sebagaimana yang tertera dalam Permentan No. 1 Tahun 2018 tentang Sistem Penetapan Harga Sawit untuk Petani. “Sampai sekarang, belum ada tindak lanjut di daerah untuk memantau, mengawasi pemberlakuan harga yang dilakukan oleh tengkulak dan juga orang-orang sawit,” katanya.
Jika kehidupan ekonomi petani sawit di daerah meningkat, jelas akan menggerakkan perekonomian daerah setempat. Konsumsi-konsumsi petani yang meningkat akan memperbesar permintaan akan berbagai barang kebutuhan hidup. Bahkan, sudah mulai berseliweran “candaan” di kalangan petani: “saatnya membeli Pajero”.
Perekonomian daerah tempat kebun kelapa sawit juga “ditopang” oleh berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pungutan itu bisa berupa retribusi, ada juga yang berbentuk pajak. Misalnya, sumbangan pihak ketiga, pajak penerangan jalan, dan retribusi alat berat. “Jadi, selama ini sebenarnya daerah itu selalu mencari cara untuk mendapatkan bagian dari industri ini,” kata Joko Supriyono.
Daerah Minta Bagi Hasil
Masalahnya, tidak semua daerah menerapkan itu. Sekalipun ada daerah yang sudah menerapkannya, tetap saja mereka berpandangan bahwa dana yang diperoleh dari sawit masih dianggap kurang. Tak heran kalau kemudian, belum lama ini sejumlah kepala daerah penghasil kelapa sawit mengusulkan adanya ada dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit kepada pemerintah pusat.
Dalam pertemuan di Pekanbaru, sepekan yang lewat, para perwakilan gubernur mengusulkan pembagian dana bagi hasil kelapa sawit daerah dan pusat itu berkisar antara 30% berbanding 70% atau 35% berbanding 65%.
Gubernur Riau Syamsuar, M.Si., menyatakan, beberapa aspek teknis yang menjadi dasar munculnya usulan pembagian DBH kelapa sawit ke pemerintah pusat. Menurutnya, daerah menerima dampak dari pengelolaan perkebunan sawit, seperti kerusakan infrastruktur jalan akibat pengangkutan CPO. Pun tingginya potensi erosi serta juga risiko pencemaran udara, tanah dan air akibat ancaman karhutla, limbah padat B3, serta limbah cair.
Sementara di sisi lain, perkebunan menghasilkan pemasukan bagi negara berupa bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) yang sangat besar. “Namun, belum ada bagian untuk daerah penghasil (sawit),” ujar Syamsuar sambil menambahkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 yang ada baru DBH Pajak dan Migas, sementara DBH sawit belum masuk.
Memang bagi daerah tempat perkebunan kelapa sawit yang belum merasa mendapatkan dampaknya, sangatlah beralasan permintaan itu. Provinsi Kalimantan Barat, misalnya. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2019) menyebutkan, Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan lahan perkebunan kelapa sawit terluas ketiga di Tanah Air.
Dengan luas lahan 1,8 juta hektare, perkebunan kelapa sawit Kalimantan Barat hanya kalah luas dari Riau (3,4 juta hektare) dan Sumatera Utara (2,1 juta hektare). Meski unggul di luasan perkebunan kelapa sawit, Kalimantan Barat tidak dapat dikatakan daerah kaya. Provinsi ini justru merupakan yang paling miskin dibanding wilayah lain di Kalimantan. Menurut BPS per Juli 2019, Kalimantan Barat memiliki angka kemiskinan mencapai 7,49%. Sementara Kalimantan Utara hanya sebesar 6,63%, Kalimantan Timur sebesar 5,94%, Kalimantan Tengah sebesar 4,98%, dan Kalimantan Selatan sebesar 4,55%.
Menanggapi keinginan tersebut, pihak Gapki mempertanyakan relevansi membandingkan antara sawit dan minyak atau batu bara. Menurut Gapki, perkebunan sawit itu sifatnya long term, bahkan long life. “Sebenarnya, sawit ini tidak menghabiskan, sawit ini mengakumulasikan,” tandas Joko Supriyono.
Memang pihak Gapki menyatakan bahwa industri atau perkebunan sawit harus bisa memberikan efek berantai. Namun, itu semua tidak bisa dibebankan kepada mereka semata, tetapi juga pihak pemda. “Pemerintah daerah mesti memfasilitasi bagaimana perusahaan dengan masyarakat terjadi sinergi,” kata Joko.
Salah satu contoh sinergi itu adalah penyediaan lahan oleh pemda untuk pembentukan petani plasma. Kalau pemerintah daerah memfasilitasi menyediakan lahan, pasti perusahaan mau membangun plasma. Problemnya, perusahaan disuruh membangun plasma, tapi terbentur permasalahan lahannya.
Ya memang, agar industri atau perkebunan sawit bisa memberikan efek berantai, semua pemangku kepentingan perlu duduk dan bekerja sama mencari suatu strategi yang bisa menguntungkan semua. (Husni Isnaini dan Efi Susiyanti)
Memang harga itu telah menurun dibandingkan pada harga Jumat di pekan sebelumnya yang bertengger di angka RM3.095 (US$761,17). Toh tetap saja, level RM2.943 terbilang tinggi sejak Januari 2017. “Sekarang naik, kami bersyukur ada yang mengompensasi selama dua tahun terakhir,” kata Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), kepada SINDO Weekly, Kamis pekan lalu (16/1/2020).
Ada banyak faktor yang membuat harga minyak sawit melonjak. Dari luar negeri, gesekan politik antara Malaysia dan India terkait masalah Khasmir telah membakar harga CPO. Pemerintah India mengeluarkan kebijakan kepada dunia usahanya agar tak mengekspor minyak sawit dari Jiran. “Ada permasalahan India dan Malaysia, maka yang diuntungkan otomatis harga CPO untuk di Indonesia ini langsung naik,” kata Bhima Yudhistira, ekonom Indef, Selasa pekan lalu (14/1/2020).
Selain itu, Negeri Hindustan juga memberlakukan kebijakan tarif baru terhadap impor minyak sawit dan turunannya. India sebagai pembeli minyak nabati terbesar di dunia melakukan pemangkasan pada pajak impor CPO dan minyak sawit olahan. Pajak impor CPO diturunkan menjadi 37,5% dari 40%. Sementara, pajak untuk berbagai produk olahan minyak sawit menjadi 45% dari 50%.Informasi tersebut tentu menjadi kabar baik untuk CPO. Pasalnya, India mengandalkan impor minyak nabati untuk memenuhi 70% kebutuhan domestiknya. Dua pertiga impor minyak nabati tersebut disumbang minyak sawit dan olahannya. Pemangkasan pajak impor tersebut berpotensi untuk mendorong impor CPO dan olahannya oleh India.
United States Department Agriculture (USDA) mencatat, untuk periode 2019/2020 (Oktober–September), terjadi peningkatan permintaan CPO oleh India sebesar 3,1% menjadi 9,90 juta ton. Tiongkok juga meningkatkan permintaannya menjadi sebanyak 6,70 juta ton (naik 6,3%). Jika ditotal dengan kawasan dunia lainnya, permintaan CPO global naik sebesar 3,4% menjadi 51,6 juta ton.Dari dalam negeri, program mandatory biodiesel, mulai dari B20 dan sekarang B30, juga turut memengaruhi pergerakan harga minyak sawit. Program tersebut memberikan sentimen bahwa permintaan CPO domestik meningkat. “Jadi, itu sebenarnya faktor yang menjadi kombinasi sehingga harga naik,” kata Joko Supriyono.
Peningkatan kebutuhan domestik untuk program biodiesel itu telah mengubah komposisi permintaan antara domestik dan ekspor. Selama ini, pola permintaan domestik sebesar 30% dan ekspor 70%. Pada 2018, dengan total produksi sebanyak 43 juta ton, permintaan domestik mencapai 14 juta ton atau sekitar 33%. Tahun lalu, permintaan domestik itu mencapai 36%. “Artinya suplai ke luar pasar Indonesia otomatis akan berkurang,” tandas Joko.
Jika nanti mandatory biodiesel ditingkatkan lagi menjadi B40 dan B50, tentu saja permintaan akan minyak sawit domestik kian membesar. Kondisi itu tentu saja berdampak positif terhadap perekonomian dalam negeri. Pertama, kita tidak lagi dominan menggantungkan pada ekspor yang selama ini dilakukan.
Kenaikan permintaan domestik akan membuat keseimbangan baru antara ekspor dan dalam negeri. Dengan demikian, bisa saling menopang jika salah satu pasar itu bergolak atau anjlok. “Berarti pasar domestik cukup mampu mengimbangi kalau (di luar) ada gejolak,” kata Joko.
Jika ekspor CPO masih sangat dominan, harganya akan rentan dipengaruhi sentimen negatif dari luar negeri. Dengan adanya program B30, CPO bisa kita gunakan untuk kepentingan sendiri. “Jangan pernah khawatir tidak diminati oleh pasar,” kata Presiden Joko Widodo, belum lama ini.
Kedua, program B30 mampu menekan defisit neraca perdagangan yang selama ini kerap membayangi akibat tingginya volume impor bahan bakar minyak. Penggunaan CPO untuk B30 akan mengurangi impor BBM yang terbilang besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari–Oktober 2019, angka Impor minyak mentah tercatat US$4,343 miliar atau setara Rp60 triliun. Sementara, impor hasil minyak termasuk BBM tercatat US$11,195 miliar atau sekitar Rp156,7 triliun. Jika ditotal, impor minyak kita mencapai Rp216.7 triliun.
Pengurangan impor BBM ujung-ujungnya bisa menghemat devisa yang lumayan besar. Jika program biodiesel bisa menyerap produksi CPO hingga 10 juta kiloliter, devisa yang bisa dihemat Rp122,8 triliun. Program B30 yang baru diluncurkan saja sudah diperkirakan bisa menghemat devisa Rp63 triliun.
Nah, kenaikan harga CPO jelas akan membawa banyak dampak positif buat pihak-pihak yang berkecimpung. Kenaikan harga CPO akan membuat para petani semringah karena bisa meningkatkan harga tandan buah segar (TBS) milik petani. “Karena salah satu indikator dan rumusan pembelian harga TBS di petani itu adalah harga CPO,” kata Mansuetus Darto, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit, Rabu pekan lalu (15/01).
Saat ini, harga TBS di tingkat petani antara Rp1.800–1.900 per kg. Bahkan, harganya ada yang mencapai Rp2.100 per kg. “Jadi, peningkatan harga TBS petani ini terjadi kurang lebih dari Januari kemarin, sekitar 30%,” tambah Darto.
Sayangnya, tak semua petani menikmati kenaikan harga yang signifikan itu. Harga tadi hanya dinikmati oleh petani plasma, sedangkan untuk petani swadaya atau mandiri harganya hanya berkisar Rp1.200–1.300. “Petani swadaya tidak masuk dalam bingkai kemitraan,” jelas Darto.
Petani plasma adalah petani yang sejak dari awal, mulai dari tanam hingga pembersihan lahan, bermitra dengan perusahaan dan ada perjanjian (MoU) kemitraan dengan koperasi dan juga perusahaan. Sementara, petani swadaya atau petani mandiri yang memang membangun sendiri. Jika TBS petani plasma dibeli oleh perusahaan atau mitranya yang lain, TBS petani swadaya kebanyakan dibeli oleh para tengkulak.
Menurut Darto, harga-harga yang ditetapkan tengkulak cenderung tidak diawasi oleh pemerintah sebagaimana yang tertera dalam Permentan No. 1 Tahun 2018 tentang Sistem Penetapan Harga Sawit untuk Petani. “Sampai sekarang, belum ada tindak lanjut di daerah untuk memantau, mengawasi pemberlakuan harga yang dilakukan oleh tengkulak dan juga orang-orang sawit,” katanya.
Jika kehidupan ekonomi petani sawit di daerah meningkat, jelas akan menggerakkan perekonomian daerah setempat. Konsumsi-konsumsi petani yang meningkat akan memperbesar permintaan akan berbagai barang kebutuhan hidup. Bahkan, sudah mulai berseliweran “candaan” di kalangan petani: “saatnya membeli Pajero”.
Perekonomian daerah tempat kebun kelapa sawit juga “ditopang” oleh berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pungutan itu bisa berupa retribusi, ada juga yang berbentuk pajak. Misalnya, sumbangan pihak ketiga, pajak penerangan jalan, dan retribusi alat berat. “Jadi, selama ini sebenarnya daerah itu selalu mencari cara untuk mendapatkan bagian dari industri ini,” kata Joko Supriyono.
Daerah Minta Bagi Hasil
Masalahnya, tidak semua daerah menerapkan itu. Sekalipun ada daerah yang sudah menerapkannya, tetap saja mereka berpandangan bahwa dana yang diperoleh dari sawit masih dianggap kurang. Tak heran kalau kemudian, belum lama ini sejumlah kepala daerah penghasil kelapa sawit mengusulkan adanya ada dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit kepada pemerintah pusat.
Dalam pertemuan di Pekanbaru, sepekan yang lewat, para perwakilan gubernur mengusulkan pembagian dana bagi hasil kelapa sawit daerah dan pusat itu berkisar antara 30% berbanding 70% atau 35% berbanding 65%.
Gubernur Riau Syamsuar, M.Si., menyatakan, beberapa aspek teknis yang menjadi dasar munculnya usulan pembagian DBH kelapa sawit ke pemerintah pusat. Menurutnya, daerah menerima dampak dari pengelolaan perkebunan sawit, seperti kerusakan infrastruktur jalan akibat pengangkutan CPO. Pun tingginya potensi erosi serta juga risiko pencemaran udara, tanah dan air akibat ancaman karhutla, limbah padat B3, serta limbah cair.
Sementara di sisi lain, perkebunan menghasilkan pemasukan bagi negara berupa bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) yang sangat besar. “Namun, belum ada bagian untuk daerah penghasil (sawit),” ujar Syamsuar sambil menambahkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 yang ada baru DBH Pajak dan Migas, sementara DBH sawit belum masuk.
Memang bagi daerah tempat perkebunan kelapa sawit yang belum merasa mendapatkan dampaknya, sangatlah beralasan permintaan itu. Provinsi Kalimantan Barat, misalnya. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2019) menyebutkan, Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan lahan perkebunan kelapa sawit terluas ketiga di Tanah Air.
Dengan luas lahan 1,8 juta hektare, perkebunan kelapa sawit Kalimantan Barat hanya kalah luas dari Riau (3,4 juta hektare) dan Sumatera Utara (2,1 juta hektare). Meski unggul di luasan perkebunan kelapa sawit, Kalimantan Barat tidak dapat dikatakan daerah kaya. Provinsi ini justru merupakan yang paling miskin dibanding wilayah lain di Kalimantan. Menurut BPS per Juli 2019, Kalimantan Barat memiliki angka kemiskinan mencapai 7,49%. Sementara Kalimantan Utara hanya sebesar 6,63%, Kalimantan Timur sebesar 5,94%, Kalimantan Tengah sebesar 4,98%, dan Kalimantan Selatan sebesar 4,55%.
Menanggapi keinginan tersebut, pihak Gapki mempertanyakan relevansi membandingkan antara sawit dan minyak atau batu bara. Menurut Gapki, perkebunan sawit itu sifatnya long term, bahkan long life. “Sebenarnya, sawit ini tidak menghabiskan, sawit ini mengakumulasikan,” tandas Joko Supriyono.
Memang pihak Gapki menyatakan bahwa industri atau perkebunan sawit harus bisa memberikan efek berantai. Namun, itu semua tidak bisa dibebankan kepada mereka semata, tetapi juga pihak pemda. “Pemerintah daerah mesti memfasilitasi bagaimana perusahaan dengan masyarakat terjadi sinergi,” kata Joko.
Salah satu contoh sinergi itu adalah penyediaan lahan oleh pemda untuk pembentukan petani plasma. Kalau pemerintah daerah memfasilitasi menyediakan lahan, pasti perusahaan mau membangun plasma. Problemnya, perusahaan disuruh membangun plasma, tapi terbentur permasalahan lahannya.
Ya memang, agar industri atau perkebunan sawit bisa memberikan efek berantai, semua pemangku kepentingan perlu duduk dan bekerja sama mencari suatu strategi yang bisa menguntungkan semua. (Husni Isnaini dan Efi Susiyanti)
(ysw)