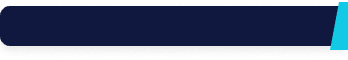Jakarta Masihkah Layak Huni?

Jakarta Masihkah Layak Huni?
A
A
A
Lalu-lintas Jakarta kian hari kian macet dan kian semrawut sehingga ada anekdot bahwa hidup di Jakarta itu tua di jalan. Bayangkan, perjalanan sejauh kurang lebih 30 kilometer di Jakarta itu membutuhkan waktu rata-rata 2-2,5 jam.
Berarti sekitar lima jam untuk pergi dan pulang. Sejumlah program pemerintah untuk mengatasinya belum juga membawa hasil seperti yang diharapkan.
Alih-alih menyelesaikan persoalan, beberapa program malah menjadi sumber masalah baru. Jalan layang non-tol Kasablanca-Tanah Abang di Jakarta Selatan, misalnya, tak berhasil mengurai kemacetan lalu-lintas di jalan di bawahnya, Jalan Prof. Dr. Satrio, malah menjadi sumber kemacetan baru di ujung jalan layang tersebut. Jalan Tol JORR W2 yang diklaim dapat mempercepat waktu tempuh hingga sejam dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Pondok Indah, Jakarta Selatan, ternyata hingga kini tetap saja dua jam atau bahkan lebih karena jalan tol tersebut “dikuasai” truk-truk konteiner yang menuju Bekasi dan Bogor, Jawa Barat.
Sejumlah upaya membangun Jakarta menjadi kota metropolitan kelas dunia yang tertib, teratur, hijau dan tidak polutif tampaknya memang masih jauh dari harapan. Masalah yang dihadapi sangat kompleks. Kesemrawutan lalu-lintas, misalnya, tidak semata-mata disebabkan oleh jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan panjang jalan.
Akan tetapi hal itu juga disebabkan oleh faktor lainnya, seperti ketiadaan disiplin pemakai jalan, sarana transportasi publik yang tidak memadai, pusatpusat perbelanjaan di lokasi yang tidak tepat hingga sumbatan “leher botol” di sejumlah ruas jalan. Intinya, hingga sekarang ini, di Jakarta boleh dibuka usaha apa saja, dimana saja tanpa adanya pengelompokan atau pemikiran jangka panjang dampak dari pembangunan tersebut, misalnya segi penanganan limbahnya maupun dampaknya teradap lalulintas di kawasan tersebut. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi kesemrawutan lalu-lintas Jakarta cenderung tambal sulam, tidak komprehensif dan tidak konsisten.
Ketika membangun angkutan publik Transjakarta dengan jalur khusus, pemerintah melupakan angkutan bus konvensional. Pelayanan dan kondisi bus konvensional dibiarkan tetap buruk. Akibatnya, yang terjadi hanya perpindahan penumpang dari bus konvensional ke Transjakarta. Padahal yang diharapkan adalah perpindahan dari mobil pribadi ke angkutan publik. Selain itu, banyak rencana kebijakan yang hanya berhenti sebatas wacana. Pemerintah DKI Jakarta misalnya pernah mengemukakan akan menerapkan kebijakan pengoperasian mobil secara bergiliran menurut genap-ganjil angka terakhir nomor polisinya. Rencana kebijakan ini menguap begitu saja.
Demikian pula halnya dengan rencana membangun jaringan kereta monorel. Ditandai dengan pembangunan tiang-tiang monorel pada era Gubernur Sutiyoso, proyek ini “mati suri” pada era Gubernur Fauzi Bowo. Rencana ini kemudian dihidupkan lagi oleh Joko Widodo saat menjadi gubernur DKI Jakarta, bahkan sempat melakukan acara peletakan batu pertama. Akan tetapi, setelah itu, tak diikuti oleh batu kedua dan seterusnya. Kendati sudah berganti pengembang, monorel kembali “mati suri” hingga sekarang. Bahkan pernah ada ide “ekstrim” memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta, seperti yang dilakukan oleh Malaysia.
Negara Jiran ini sukses memindahkan pusat pemerintahannya dari Kualalumpur ke Putrajaya. Pada era Soeharto, disebut ibukota akan dipindahkan ke kawasan Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Krisis multidimensi pada 1997-1998 yang menyebabkan kejatuhan Orde Baru, membuat kita melupakan ide tersebut. Ide pemindahan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta muncul lagi pada periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Bahkan ketika itu tidak sekadar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi sekaligus Ibukota Republik Indonesia. Ada yang tetap mengusulkan pindah Jonggol, tetapi sejumlah pihak juga mengusulkan pindah ke Pontianak, Kalimantan Barat dan Karawang, Jawa Barat. Akan tetapi, seperti ide lainnya, pemindahan pusat pemerintahan tersebut hanya sekedar wacana. Tidak pernah ada upaya sungguh-sungguh untuk merealisasikannya. Ibukota Negara hingga kini tetap di Jakarta yang kian macet dan semrawut.
Untuk mengurangi kemacetan lalu-lintas, PT Jakarta Toll Road Development mengusulkan pembangunan enam ruas tol di dalam kota Jakarta. Awalnya ide ini langsung ditentang oleh Gubernur Joko Widodo. Entah mengapa belakangan ini Pemerintah DKI Jakarta mulai melunak dan menyetujui usul tersebut dengan syarat jalan tol itu kelak dapat dilewati oleh bus-bus Transjakarta. Enam jalan tol baru di dalam kota tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan Jakarta.
Seperti halnya pembangunan jalan layang Casablanca-Tanah Abang yang tak dapat menyelesaikan kemacetan di Jalan Prof. Dr. Satrio, jalan tol dalam kota tersebut hanya akan menjadi pemicu kemacetan baru, paling tidak di jalan masuk dan keluar tol tersebut. Kita berharap, enam tol dalam kota ini hanya sebagai wacana, seperti rencana kebijakan lainnya. Lalu-lintas semrawut sebenarnya hanya gejala “penyakit” Jakarta.
Masalah utama Jakarta sesungguhnya adalah wilayah seluas 663 kilometer persegi ini sudah tidak sanggup menampung kegiatan warganya yang mencapai 10 juta jiwa di malam hari dan sekitar 11 juta jiwa pada siang hari. Jakarta telah menjadi wilayah terpadat di Indonesia. Kepadatan penduduknya mencapai 15.000 jiwa per kilometer persegi. Sekarang ini Jakarta menjadi pusat segalanya. Sekitar 80% kredit bank disalurkan di Jakarta. Sebagian besar kantor pusat 501 perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) berada di Jakarta. Sebagian ekspor dan impor juga dilakukan melalui Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta.
Bahkan sebagian besar penumpang pesawat untuk penerbangan internasional harus melewati wilayah Jakarta sebelum sampai di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Inilah yang menjadikan lalu-lintas Jakarta begitu sibuk. Jumlah kendaraan di Jakarta mencapai 15 juta unit. Jika ditambah dengan kendaraan dari Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang masuk dan keluar Jakarta setiap hari maka jumlahnya bisa mencapai 20 juta unit. Sementara panjang jalan di Jakarta nyaris tidak bertambah selama beberapa tahun terakhir ini.
Menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan kelas dunia yang tertib, teratur, hijau dan tidak polutif harus dimulai dengan mengatur dan menata kembali kapasitasnya. Untuk itu sudah waktunya Pemerintah memikirkan dan menerapkan kebijakan pembangunan alternatif yang lebih ekstrim tetapi efektif, suatu kebijakan “out of the box” yaitu “mengosongkan Jakarta.”
Caranya, bukan dengan memindahkan pusat pemerintahan atau Ibukota Negara keluar Jakarta, tapi justru kebalikannya yaitu menjadikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan saja, seperti Canberra, Australia atau Washington DC, Amerika Serikat. Untuk itu dibuat kebijakan radikal agar sejumlah industri manufaktur dan jasa tertentu ditetapkan tidak boleh lagi beroperasi di Jakarta.
Kantor-kantor pusat sejumlah perusahaan juga harus digiring keluar Jakarta. Intinya, berbagai aktivitas - terutama ekonomi - yang terlalu membebani Jakarta digeser ke wilayah-wilayah yang sekarang ini secara alamiah telah berfungsi sebagai penyangga Jakarta, terutama dalam hal pemukiman.
DANANG KEMAYAN JATI
Ketua Kompartemen Pengembangan Kota Baru DPP Real Estate Indonesia
Berarti sekitar lima jam untuk pergi dan pulang. Sejumlah program pemerintah untuk mengatasinya belum juga membawa hasil seperti yang diharapkan.
Alih-alih menyelesaikan persoalan, beberapa program malah menjadi sumber masalah baru. Jalan layang non-tol Kasablanca-Tanah Abang di Jakarta Selatan, misalnya, tak berhasil mengurai kemacetan lalu-lintas di jalan di bawahnya, Jalan Prof. Dr. Satrio, malah menjadi sumber kemacetan baru di ujung jalan layang tersebut. Jalan Tol JORR W2 yang diklaim dapat mempercepat waktu tempuh hingga sejam dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Pondok Indah, Jakarta Selatan, ternyata hingga kini tetap saja dua jam atau bahkan lebih karena jalan tol tersebut “dikuasai” truk-truk konteiner yang menuju Bekasi dan Bogor, Jawa Barat.
Sejumlah upaya membangun Jakarta menjadi kota metropolitan kelas dunia yang tertib, teratur, hijau dan tidak polutif tampaknya memang masih jauh dari harapan. Masalah yang dihadapi sangat kompleks. Kesemrawutan lalu-lintas, misalnya, tidak semata-mata disebabkan oleh jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan panjang jalan.
Akan tetapi hal itu juga disebabkan oleh faktor lainnya, seperti ketiadaan disiplin pemakai jalan, sarana transportasi publik yang tidak memadai, pusatpusat perbelanjaan di lokasi yang tidak tepat hingga sumbatan “leher botol” di sejumlah ruas jalan. Intinya, hingga sekarang ini, di Jakarta boleh dibuka usaha apa saja, dimana saja tanpa adanya pengelompokan atau pemikiran jangka panjang dampak dari pembangunan tersebut, misalnya segi penanganan limbahnya maupun dampaknya teradap lalulintas di kawasan tersebut. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi kesemrawutan lalu-lintas Jakarta cenderung tambal sulam, tidak komprehensif dan tidak konsisten.
Ketika membangun angkutan publik Transjakarta dengan jalur khusus, pemerintah melupakan angkutan bus konvensional. Pelayanan dan kondisi bus konvensional dibiarkan tetap buruk. Akibatnya, yang terjadi hanya perpindahan penumpang dari bus konvensional ke Transjakarta. Padahal yang diharapkan adalah perpindahan dari mobil pribadi ke angkutan publik. Selain itu, banyak rencana kebijakan yang hanya berhenti sebatas wacana. Pemerintah DKI Jakarta misalnya pernah mengemukakan akan menerapkan kebijakan pengoperasian mobil secara bergiliran menurut genap-ganjil angka terakhir nomor polisinya. Rencana kebijakan ini menguap begitu saja.
Demikian pula halnya dengan rencana membangun jaringan kereta monorel. Ditandai dengan pembangunan tiang-tiang monorel pada era Gubernur Sutiyoso, proyek ini “mati suri” pada era Gubernur Fauzi Bowo. Rencana ini kemudian dihidupkan lagi oleh Joko Widodo saat menjadi gubernur DKI Jakarta, bahkan sempat melakukan acara peletakan batu pertama. Akan tetapi, setelah itu, tak diikuti oleh batu kedua dan seterusnya. Kendati sudah berganti pengembang, monorel kembali “mati suri” hingga sekarang. Bahkan pernah ada ide “ekstrim” memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta, seperti yang dilakukan oleh Malaysia.
Negara Jiran ini sukses memindahkan pusat pemerintahannya dari Kualalumpur ke Putrajaya. Pada era Soeharto, disebut ibukota akan dipindahkan ke kawasan Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Krisis multidimensi pada 1997-1998 yang menyebabkan kejatuhan Orde Baru, membuat kita melupakan ide tersebut. Ide pemindahan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta muncul lagi pada periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Bahkan ketika itu tidak sekadar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi sekaligus Ibukota Republik Indonesia. Ada yang tetap mengusulkan pindah Jonggol, tetapi sejumlah pihak juga mengusulkan pindah ke Pontianak, Kalimantan Barat dan Karawang, Jawa Barat. Akan tetapi, seperti ide lainnya, pemindahan pusat pemerintahan tersebut hanya sekedar wacana. Tidak pernah ada upaya sungguh-sungguh untuk merealisasikannya. Ibukota Negara hingga kini tetap di Jakarta yang kian macet dan semrawut.
Untuk mengurangi kemacetan lalu-lintas, PT Jakarta Toll Road Development mengusulkan pembangunan enam ruas tol di dalam kota Jakarta. Awalnya ide ini langsung ditentang oleh Gubernur Joko Widodo. Entah mengapa belakangan ini Pemerintah DKI Jakarta mulai melunak dan menyetujui usul tersebut dengan syarat jalan tol itu kelak dapat dilewati oleh bus-bus Transjakarta. Enam jalan tol baru di dalam kota tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan Jakarta.
Seperti halnya pembangunan jalan layang Casablanca-Tanah Abang yang tak dapat menyelesaikan kemacetan di Jalan Prof. Dr. Satrio, jalan tol dalam kota tersebut hanya akan menjadi pemicu kemacetan baru, paling tidak di jalan masuk dan keluar tol tersebut. Kita berharap, enam tol dalam kota ini hanya sebagai wacana, seperti rencana kebijakan lainnya. Lalu-lintas semrawut sebenarnya hanya gejala “penyakit” Jakarta.
Masalah utama Jakarta sesungguhnya adalah wilayah seluas 663 kilometer persegi ini sudah tidak sanggup menampung kegiatan warganya yang mencapai 10 juta jiwa di malam hari dan sekitar 11 juta jiwa pada siang hari. Jakarta telah menjadi wilayah terpadat di Indonesia. Kepadatan penduduknya mencapai 15.000 jiwa per kilometer persegi. Sekarang ini Jakarta menjadi pusat segalanya. Sekitar 80% kredit bank disalurkan di Jakarta. Sebagian besar kantor pusat 501 perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) berada di Jakarta. Sebagian ekspor dan impor juga dilakukan melalui Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta.
Bahkan sebagian besar penumpang pesawat untuk penerbangan internasional harus melewati wilayah Jakarta sebelum sampai di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Inilah yang menjadikan lalu-lintas Jakarta begitu sibuk. Jumlah kendaraan di Jakarta mencapai 15 juta unit. Jika ditambah dengan kendaraan dari Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang masuk dan keluar Jakarta setiap hari maka jumlahnya bisa mencapai 20 juta unit. Sementara panjang jalan di Jakarta nyaris tidak bertambah selama beberapa tahun terakhir ini.
Menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan kelas dunia yang tertib, teratur, hijau dan tidak polutif harus dimulai dengan mengatur dan menata kembali kapasitasnya. Untuk itu sudah waktunya Pemerintah memikirkan dan menerapkan kebijakan pembangunan alternatif yang lebih ekstrim tetapi efektif, suatu kebijakan “out of the box” yaitu “mengosongkan Jakarta.”
Caranya, bukan dengan memindahkan pusat pemerintahan atau Ibukota Negara keluar Jakarta, tapi justru kebalikannya yaitu menjadikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan saja, seperti Canberra, Australia atau Washington DC, Amerika Serikat. Untuk itu dibuat kebijakan radikal agar sejumlah industri manufaktur dan jasa tertentu ditetapkan tidak boleh lagi beroperasi di Jakarta.
Kantor-kantor pusat sejumlah perusahaan juga harus digiring keluar Jakarta. Intinya, berbagai aktivitas - terutama ekonomi - yang terlalu membebani Jakarta digeser ke wilayah-wilayah yang sekarang ini secara alamiah telah berfungsi sebagai penyangga Jakarta, terutama dalam hal pemukiman.
DANANG KEMAYAN JATI
Ketua Kompartemen Pengembangan Kota Baru DPP Real Estate Indonesia
(ars)