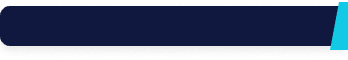Dinilai Bakal Jadi Benalu, SP PLN Tolak Kebijakan Power Wheeling
loading...

Penerapan Power Wheeling dinilai dapat menimbulkan dampak negatif, baik dari segi keuangan hingga ketahanan energi.Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Serikat Pekerja (SP) PLN menolak wacana power wheeling, sebuah konsep yang dinilai telah lama dikenal dalam struktur liberalisasi pasar ketenagalistrikan. Skema yang menciptakan mekanisme Multi Buyer Multi Seller (MBMS) ini memungkinkan pihak swasta dan negara untuk menjual energi listrik di pasar terbuka atau langsung ke konsumen akhir.
Power Wheeling terdiri dari dua jenis transaksi, yakni Wholesale Wheeling dan Retail Wheeling. Wholesale Wheeling terjadi ketika pembangkit listrik (baik milik swasta maupun negara) menjual energi listrik dalam jumlah besar ke perusahaan listrik atau konsumen di luar wilayah usahanya. Sementara, Retail Wheeling memungkinkan pembangkit listrik menjual energi listrik langsung ke konsumen akhir di luar wilayah operasinya.
Ketua Umum DPP SP PLN M Abrar Ali mengatakan, kedua model ini menggunakan jaringan transmisi dan distribusi sebagai "jalan tol" dengan skema open access, di mana semua pembangkit listrik dapat menggunakannya dengan membayar "toll fee."
Namun, penerapan Power Wheeling dinilai dapat menimbulkan dampak negatif signifikan, baik dari segi keuangan, hukum, teknis, maupun ketahanan energi. Abrar memaparkan analisis dampak Power Wheeling sebagai berikut:
Dari sisi keuangan, skema Power Wheeling dinilali akan menyebabkan penurunan permintaan organik dan non-organik: Menurut hitungannya, Power Wheeling dapat menggerus permintaan listrik organik hingga 30% dan permintaan non-organik dari pelanggan Konsumen Tegangan Tinggi (KTT) hingga 50%. "Hal ini akan berujung pada lonjakan beban APBN karena biaya yang harus ditanggung negara," ujarnya melalui keterangan pers, Jumat (6/9/2024).
Setiap 1 GW pembangkit listrik yang masuk melalui skema Power Wheeling, kata Abrar, diperkirakan akan menambah beban biaya hingga Rp3,44 triliun (biaya ToP + Backup cost), yang akan semakin memberatkan keuangan negara. Dampak akumulatif hingga 2030 diperkirakan akan meningkatkan beban Take or Pay (ToP) dari Rp317 triliun menjadi Rp429 triliun, atau terjadi kenaikan sebesar Rp112 triliun.
Dari sisi hukum, lanjut Abrar, Power Wheeling kontradiktif dengan UU No. 20 Tahun 2022. "Power Wheeling merupakan implementasi dari skema MBMS yang melibatkan unbundling. Namun, hal ini bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2022 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004," tegasnya.
Kemudian skema ini juga dinilai mereduksi peran negara karena akan menciptakan kompetisi di pasar penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Hal ini berpotensi mengurangi peran negara dalam menjaga kepentingan umum di sektor ketenagalistrikan.
Di menilai skema ini juga berpotensi menimbulkan perselisihan terkait harga, losses, frekuensi, dan volume yang dapat berdampak pada terhentinya pasokan listrik (blackout) dan merugikan masyarakat luas.
Dari sisi teknis, skema ini menurutnya akan mperparah oversupply. "Saat ini, sistem ketenagalistrikan di Jawa dan Bali telah mengalami oversupply. Penerapan Power Wheeling berpotensi memperburuk kondisi ini, terutama karena pembangkit yang menggunakan energi baru terbarukan (EBT) bersifat intermiten dan tidak stabil," cetusnya.
Power Wheeling yang bersumber dari EBT, kata Abrar, memerlukan spinning reserve tambahan untuk menjaga keandalan sistem, yang justru akan meningkatkan Biaya Pokok Produksi (BPP) dan harga jual listrik kepada konsumen.
Hal itu kemudian berdampak terhadap ketahanan energi. Dengan meningkatnya risiko blackout, kata dia, jaminan pasokan listrik yang stabil semakin sulit dicapai. "Hal ini dapat menghambat akses terhadap listrik yang andal bagi masyarakat," tandasnya.
Penambahan beban akibat skema ToP dan investasi untuk spinning reserve, lanjut dia, akan meningkatkan BPP, yang pada akhirnya membuat harga listrik melonjak dan membebani konsumen serta APBN.
Di bagian lain, dengan prioritas Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 pada pembangunan pembangkit EBT sebesar 51,6%, menurut dia tidak ada urgensi untuk menerapkan Power Wheeling. Hal ini sesuai dengan rencana Net Zero Emission 2060 tanpa menambah risiko dari berbagai aspek.
"Konsep Power Wheeling dikhawatirkan akan digunakan dalam skema liberalisasi penyediaan listrik untuk kepentingan umum, yang pada akhirnya berpotensi melanggar Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara," kata Abrar.
Abrar pun mencontohkan studi kasus di Filipina terkait penerapan skema Power Wheeling dan privatisasi sektor ketenagalistrikan melalui Electric Power Industry Reform Act (Epira) pada tahun 2001. "Pengalaman Filipina ini dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan Power Wheeling," jelasnya.
Beberapa tantangan yang dialami Filipina yang perlu diperhatikan dalam konteks Indonesia menurutnya adalah kenaikan harga listrik. Sejak penerapan skema Power Wheeling, harga listrik di Filipina mengalami kenaikan sebesar 55%. Jika hal ini terjadi di Indonesia, masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah, akan menghadapi beban finansial yang berat, terutama jika harga listrik ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.
Filipina, kata dia, juga menghadapi krisis energi dan sering mengalami pemadaman listrik setelah privatisasi sektor kelistrikan. Tantangan serupa bisa terjadi di Indonesia jika pasokan listrik tidak dijaga dengan baik, dan intermitensi dari pembangkit energi baru terbarukan dapat mengganggu keandalan sistem.
Selain belajar dari pengalaman Filipina, menurut dia Indonesia perlu menghadapi beberapa tantangan utama dalam implementasi Power Wheeling, di antaranya siperlukan kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk memastikan kepastian hukum dalam hubungan antara PLN, produsen listrik swasta, dan konsumen. Regulasi yang tepat juga diperlukan untuk menghindari potensi pembentukan kartel di sektor ketenagalistrikan.
Power Wheeling juga membutuhkan investasi besar dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan. Pemerintah harus memastikan adanya kepastian investasi yang cukup untuk mendorong minat produsen listrik swasta dalam berinvestasi.
Dengan skema Power Wheeling, Lanjutnya, tarif listrik akan ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Ketika permintaan tinggi dan pasokan tetap, tarif listrik pasti naik, yang berakibat pada kenaikan subsidi listrik yang harus ditanggung oleh APBN.
Di bagian lain, kata Abrar, PLN harus menanggung beban tambahan dari spinning reserve dan intermitensi pembangkit energi baru terbarukan. Ini akan mempengaruhi biaya pokok produksi (BPP) listrik, yang dapat berujung pada kenaikan tarif listrik untuk konsumen atau peningkatan subsidi dari APBN.
"Intinya, penerapan Power Wheeling justru dapat merugikan BUMN, APBN, dan konsumen secara akumulatif. Oleh karena itu, Power Wheeling dinilai lebih sebagai benalu dalam transisi energi, yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi negara," tutupnya.
Power Wheeling terdiri dari dua jenis transaksi, yakni Wholesale Wheeling dan Retail Wheeling. Wholesale Wheeling terjadi ketika pembangkit listrik (baik milik swasta maupun negara) menjual energi listrik dalam jumlah besar ke perusahaan listrik atau konsumen di luar wilayah usahanya. Sementara, Retail Wheeling memungkinkan pembangkit listrik menjual energi listrik langsung ke konsumen akhir di luar wilayah operasinya.
Ketua Umum DPP SP PLN M Abrar Ali mengatakan, kedua model ini menggunakan jaringan transmisi dan distribusi sebagai "jalan tol" dengan skema open access, di mana semua pembangkit listrik dapat menggunakannya dengan membayar "toll fee."
Namun, penerapan Power Wheeling dinilai dapat menimbulkan dampak negatif signifikan, baik dari segi keuangan, hukum, teknis, maupun ketahanan energi. Abrar memaparkan analisis dampak Power Wheeling sebagai berikut:
Dari sisi keuangan, skema Power Wheeling dinilali akan menyebabkan penurunan permintaan organik dan non-organik: Menurut hitungannya, Power Wheeling dapat menggerus permintaan listrik organik hingga 30% dan permintaan non-organik dari pelanggan Konsumen Tegangan Tinggi (KTT) hingga 50%. "Hal ini akan berujung pada lonjakan beban APBN karena biaya yang harus ditanggung negara," ujarnya melalui keterangan pers, Jumat (6/9/2024).
Setiap 1 GW pembangkit listrik yang masuk melalui skema Power Wheeling, kata Abrar, diperkirakan akan menambah beban biaya hingga Rp3,44 triliun (biaya ToP + Backup cost), yang akan semakin memberatkan keuangan negara. Dampak akumulatif hingga 2030 diperkirakan akan meningkatkan beban Take or Pay (ToP) dari Rp317 triliun menjadi Rp429 triliun, atau terjadi kenaikan sebesar Rp112 triliun.
Dari sisi hukum, lanjut Abrar, Power Wheeling kontradiktif dengan UU No. 20 Tahun 2022. "Power Wheeling merupakan implementasi dari skema MBMS yang melibatkan unbundling. Namun, hal ini bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2022 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004," tegasnya.
Kemudian skema ini juga dinilai mereduksi peran negara karena akan menciptakan kompetisi di pasar penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Hal ini berpotensi mengurangi peran negara dalam menjaga kepentingan umum di sektor ketenagalistrikan.
Di menilai skema ini juga berpotensi menimbulkan perselisihan terkait harga, losses, frekuensi, dan volume yang dapat berdampak pada terhentinya pasokan listrik (blackout) dan merugikan masyarakat luas.
Dari sisi teknis, skema ini menurutnya akan mperparah oversupply. "Saat ini, sistem ketenagalistrikan di Jawa dan Bali telah mengalami oversupply. Penerapan Power Wheeling berpotensi memperburuk kondisi ini, terutama karena pembangkit yang menggunakan energi baru terbarukan (EBT) bersifat intermiten dan tidak stabil," cetusnya.
Power Wheeling yang bersumber dari EBT, kata Abrar, memerlukan spinning reserve tambahan untuk menjaga keandalan sistem, yang justru akan meningkatkan Biaya Pokok Produksi (BPP) dan harga jual listrik kepada konsumen.
Hal itu kemudian berdampak terhadap ketahanan energi. Dengan meningkatnya risiko blackout, kata dia, jaminan pasokan listrik yang stabil semakin sulit dicapai. "Hal ini dapat menghambat akses terhadap listrik yang andal bagi masyarakat," tandasnya.
Penambahan beban akibat skema ToP dan investasi untuk spinning reserve, lanjut dia, akan meningkatkan BPP, yang pada akhirnya membuat harga listrik melonjak dan membebani konsumen serta APBN.
Di bagian lain, dengan prioritas Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 pada pembangunan pembangkit EBT sebesar 51,6%, menurut dia tidak ada urgensi untuk menerapkan Power Wheeling. Hal ini sesuai dengan rencana Net Zero Emission 2060 tanpa menambah risiko dari berbagai aspek.
"Konsep Power Wheeling dikhawatirkan akan digunakan dalam skema liberalisasi penyediaan listrik untuk kepentingan umum, yang pada akhirnya berpotensi melanggar Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara," kata Abrar.
Abrar pun mencontohkan studi kasus di Filipina terkait penerapan skema Power Wheeling dan privatisasi sektor ketenagalistrikan melalui Electric Power Industry Reform Act (Epira) pada tahun 2001. "Pengalaman Filipina ini dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan Power Wheeling," jelasnya.
Beberapa tantangan yang dialami Filipina yang perlu diperhatikan dalam konteks Indonesia menurutnya adalah kenaikan harga listrik. Sejak penerapan skema Power Wheeling, harga listrik di Filipina mengalami kenaikan sebesar 55%. Jika hal ini terjadi di Indonesia, masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah, akan menghadapi beban finansial yang berat, terutama jika harga listrik ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.
Filipina, kata dia, juga menghadapi krisis energi dan sering mengalami pemadaman listrik setelah privatisasi sektor kelistrikan. Tantangan serupa bisa terjadi di Indonesia jika pasokan listrik tidak dijaga dengan baik, dan intermitensi dari pembangkit energi baru terbarukan dapat mengganggu keandalan sistem.
Selain belajar dari pengalaman Filipina, menurut dia Indonesia perlu menghadapi beberapa tantangan utama dalam implementasi Power Wheeling, di antaranya siperlukan kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk memastikan kepastian hukum dalam hubungan antara PLN, produsen listrik swasta, dan konsumen. Regulasi yang tepat juga diperlukan untuk menghindari potensi pembentukan kartel di sektor ketenagalistrikan.
Power Wheeling juga membutuhkan investasi besar dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan. Pemerintah harus memastikan adanya kepastian investasi yang cukup untuk mendorong minat produsen listrik swasta dalam berinvestasi.
Dengan skema Power Wheeling, Lanjutnya, tarif listrik akan ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Ketika permintaan tinggi dan pasokan tetap, tarif listrik pasti naik, yang berakibat pada kenaikan subsidi listrik yang harus ditanggung oleh APBN.
Di bagian lain, kata Abrar, PLN harus menanggung beban tambahan dari spinning reserve dan intermitensi pembangkit energi baru terbarukan. Ini akan mempengaruhi biaya pokok produksi (BPP) listrik, yang dapat berujung pada kenaikan tarif listrik untuk konsumen atau peningkatan subsidi dari APBN.
"Intinya, penerapan Power Wheeling justru dapat merugikan BUMN, APBN, dan konsumen secara akumulatif. Oleh karena itu, Power Wheeling dinilai lebih sebagai benalu dalam transisi energi, yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi negara," tutupnya.
(fch)