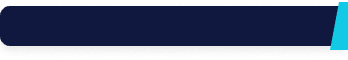Masa Depan Globalisasi Pascapandemi
loading...

Teguh Yudo Wicaksono, Head of Mandiri Institute. Foto: Doc. Bank Mandiri
A
A
A
Oleh
Teguh Yudo Wicaksono
Head of Mandiri Institute.
Tahun 2020 tampaknya menjadi salah satu masa kelam bagi globalisasi. Sepanjang sejarah, globalisasi sudah menjadi narasi besar tentang kita dan segala bentuk pencapaian manusia. Ia digambarkan sebagai proses integrasi aktivitas ekonomi dan kultur lintas batas. Efek dari globalisasi tidak saja terasa dari perubahan kondisi kesejahteraan dan ekonomi, tetapi juga perubahan kultur dan sistem politik.
Melalui keterbukaan arus perdagangan dan gagasan paska perang dunia kedua, kita menjadi saksi kenaikan dramatis kesejahteraan dan perdamaian terpanjang dalam sejarah manusia modern. Pada 1980-1990-an, kebijakan perdagangan yang lebih terbuka menjadi kunci pertumbuhan tinggi Indonesia. China, dengan pertumbuhan dramatis sejak akhir 1990-an, juga menjadi contoh nyata dari manfaat globalisasi.
Namun dalam dua tahun belakangan ini semua seolah bergerak mundur. Ketika Covid-19 mulai merebak, hampir seluruh negara menutup pintu bagi mobilitas manusia. Ini mungkin salah satu orkestrasi kebijakan tertutup terbesar yang pernah ada. Selain itu, banyak negara justru mencari sekoci invidual ketika persoalan pandemik menjadi global. Misalnya saja, banyak negara menutup ekspor pasokan perlindungan pribadi seperti masker dan lainnya dengan alasan mengamankan permintaan domestik.
Memasuki 2021, sains memberikan harapan bahwa kita akan menang atas Covid-19. Namun di sisi lain, temuan vaksin malah membuka tabir ketimpangan antarnegara. Negara-negara produsen vaksin, sebagian besar negara maju, memilih untuk memupuk stok lebih vaksin di atas kebutuhannya. Sementara penduduk negara-negara berkembang dan miskin masih dalam antre panjang untuk mendapatkan vaksin dosis pertama.
Kita seolah lupa bahwa cerita di balik vaksin Covid-19, yang hadir dalam hitungan singkat relatif dengan vaksin sebelumnya, juga cerita sukses globalisasi. BioNTech—perusahaan yang berbasis di Jerman dan berada di balik vaksin BiNTech-Pfizer yang didirikan oleh ilmuan Jerman asal Turki, Dr Ugur Sahin dan Dr Ozlem Tureci. Keduanya merupakan teman baik Albert Bourla, Chief Executive Pfizer yang berasal dari Turki. Pfizer sendiri merupakan perusahaan farmasi besar AS. Tanpa mobilitas manusia dan gagasan lintas batas negara, sebagai bentuk globalisasi, sulit membayangkan vaksin Covid-19 akan ditemukan dalam waktu singkat.
Tetapi memang harus diakui bahwa globalisasi memberikan manfaat yang tidak merata. Ada pihak yang dirugikan akibat dari perdagangan yang lebih terbuka, dan telah lama kelompok ini merasa terpinggirkan dari arus globalisasi. Sebagian besar rasa ketidakpuasan atas globalisasi berasal dari negara-negara berkembang. Namun hal yang menarik, ketidakpuasan terhadap globalisasi kini juga disuarakan oleh kelas menengah negara-negara maju seperti AS, yang selama ini justru menikmati manfaat dari globalisasi.
Profesor Joseph Stiglitz, ekonom peraih nobel ekonomi dalam bukunya “Globalization and its Discontents Revisted: Anti-Globalization in the Era of Trump” (2017), menulis bahwa penentang globalisasi kini juga berasal dari kelas bawah dan menengah negara-negara maju, kelompok yang sempat diuntungkan dari globalisasi. Presiden Trump kemudian menggunakan rasa tidak puas ini dan mengaplikasikannya untuk komoditas politik. Bahkan kebijakan bertransformasi menjadi kebijakan luar negeri AS. Di bawah administrasi Presiden Trump, AS terlibat dalam perang dagang dengan China.
Dengan meluasanya ketidakpuasan atas globalisasi hingga ke negara-negara maju, muncul pertanyaan apakah memang tren globalisasi akan berakhir? Dan apakah memang pandemi telah mempercepat laju deglobalisasi?
Sepanjang sejarah, globalisasi tidak selalu linear dan tentunya mengalami pasang surut. Tren belakangan memang menunjukkan surutnya globalisasi. Contohnya, bila kita lihat dari rasio antara perdagangan internasional—ekspor dan impor—terhadap produk domestik bruto global, ada tren penurunan atas rasio ini. Rasio perdagangan internasional terhadap PDB global mencapai puncak tertinggi di tahun 2008, yang mencapai 60,9 persen di tahun 2008—tertinggi sepanjang masa sejak perang dunia kedua (World Bank 2020).
Namun sejak krisis keuangan global di tahun 2008-2009, rasio ini anjlok menjadi 52,4 persen di tahun 2009. Pandemi Covid-19 dan perang dagang AS-China sebelumnya, juga menekan rasio ini. Di tahun 2020, rasio perdagangan internasional terhadap PDB global turun menjadi 51,5 persen, lebih rendah dibandingkan dengan periode krisis keuangan global.
Pandemik Covid-19 tampaknya memperburuk tren globalisasi. DHL Global Connected Index terbaru melaporkan bahwa pergerakan manusia di era pandemik, yang ditandai oleh perjalanan internasional per kapita, di tahun 2020 jatuh ke tingkat yang setara pada era 1970an. Satu-satunya indikator globalisasi yang masih kuat hanyalah indeks informasi, yang disebabkan karena kenaikan drastis penggunaan internet akibat Covid-19.
Namun di sisi lain ada indikasi arus balik dari tren deglobalisasi ini. Memasuki tahun 2021 kita melihat adanya kenaikan drastis aliran perdagangan global. Temuan menunjukkan bahwa jalur perdagangan tersibuk di dunia tetap menjadi jalur timur transpasifik antara Asia dan wilayah Amerika Utara. Bahkan ditengah disrupsi rantai suplai, Port of Los Angeles—salah satu pelabuhan tersibuk di AS—mencatat kenaikan drastis di bulan September 2021 (Greene 2021).
Persoalan Global Butuh Kerja Sama Global
Selain pandemi Covid-19, kita juga menghadapi persoalan global yang seharusnya menguatkan kerja sama global. Perubahan iklim, ancaman eksistensial yang nyata, sangat membutuhkan solusi dan kerja sama yang bersifat global.
Laporan terakhir dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) telah sangat jelas menunjukkan bahwa tanpa aksi serius untuk mengatasi perubahan iklim, suhu global dunia akan meningkat lebih dari 2°C di tahun 2100 dibandingkan dengan era sebelum revolusi industri. Bila ini terjadi maka manusia telah kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan diri dari bencana global.
Temun IPCC ini juga menjadi latar belakang pentingnya pertemuan tingkat tinggi Conference of Parties ke 26 (COP26) ke-26 di Glasgow, Inggris. Pertemuan KTT COP26 di Glasgow telah menyepakati empat tujuan besar yang mencakup antara lain Mitigasi, Adaptasi, Mobilisasi keuangan global, dan Kolaborasi antarnegara untuk mencapai target yang ambisius.
Bagi sejumlah pihak, komitmen negara-negara maju di COP26 ini untuk menurunkan emisi dan juga membantu negara-negara berkembang menurunkan emisi masih dinilai belum cukup. Professor Jeffrey Sachs dari Universitas Columbia dengan cukup keras menilai bahwa keputusan COP26 masih jauh dari hal yang diperlukan untuk menyelamatkan bumi dari petaka perubahan iklim (Jeffrey Sachs, Fixing the Climate Finance 2021).
Salah satu penyebabnya adalah soal mobilisasi sumber dana untuk penurunan emisi. Ini menjadi menjadi episentrum ketidaksepakatan banyak negara. Negara-negara berkembang melihat bahwa negara-negara maju, yang juga penyumbang emisi terbesar secara akumulatif, tidak menepati janji dalam memobilisasi dana sebesar US$ 100 miliar per tahun untuk menghadapi perubahan iklim pada tahun 2020 lalu.
Indonesia sendiri melalui Nationally Determined Contribution (NDC)—kontribusi pengurangan emisi—sekitar 29 persen dengan upaya nasional hingga 41 persen dari emisi yang dihasilkan pada skenario business as usual (BaU) pada 2030. Namun demikian, Indonesia membutuhkan setidaknya total pembiayaan sebesar Rp3.779 triliun dari 2020 hingga 2030, atau setara dengan Rp346 triliun per tahun (Kementerian Keuangan 2021).
Dari total pendanaan di atas, Indonesia sendiri menghadapi gap pembiayaan yang besar. Untuk itu kerja sama global yang lebih kuat untuk memobilisasi pembiayaan internasional sangat penting. Indonesia sendiri, sebagai perwakilan negara berkembang, harus menyuarakan kebutuhan ini di forum internasional.
Masa Depan Globalisasi dalam Tanda Tanya
Memasuki 2022, sejumlah outlook memberikan sejumlah harapan tentang globalisasi. DHL connected index—salah satu metrik globalisasi—memproyeksikan bahwa indeks diperkirakan akan berada di tingkat 130 pada 2022, menjadi puncak tertinggi baru sepanjang sejarah indeks ini. Selain itu, sepanjang 2020 hingga 2021, pandemi telah menjadi ujian besar bagi konektivitas, integrasi global diperkirakan akan tetap lebih tinggi dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Hal ini merupakan berita yang menggembirakan.
Namun ketidakpastian masih sangat besar. Persaingan geopolitik, terutama antara AS dan China, masih menjadi batu sandungan besar untuk mengatasi persoalan global seperti perubahan iklim. Selain itu, pandemi juga berpotensi mengubah tatanan order internasional.
Mandiri Investment Forum (MIF) 2022 yang diadakan oleh Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas, bekerjasama dengan Kementerian Investasi/BKPM menjadi forum yang mengumpulkan investor, para ekonom dan juga pengambil kebijakan untuk diskusi dan meneropong lagi soal tantangan nasional dan global. Tahun ini MIF 2022 mengusung tema “Recapturing the Growth Momentum”.
Salah satu panel dalam forum ini akan diisi oleh Professor Joseph Stiglitz dan Professor Jeffrey Sachs, yang secara bersama-sama diskusi mengenai masa depan globalisasi. Hal yang juga penting adalah hal yang kritikal terkait dengan perubahan iklim adalah bagaimana mendorong kerja sama global dalam memobilisasi sumber daya untuk mengatasi perubahan iklim.
Kerja sama global dalam pemulihan ekonomi juga merupakan tema besar yang diusung Indonesia dalam Presidensi G20, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Selain itu Indonesia juga akan mengusung green economy dan keberlanjutan (sustainability) sebagai tema spesifik dari G20 tahun ini.
Sebagai penutup, saya ingin mengutip pesan Professor Jeffrey Sachs dalam bukunya The Age of Sustainable Development. Prof Sachs menulis bahwa : “Kita telah memasuki era baru. Masyarakat global saling berhubungan tidak seperti sebelumnya. Bisnis, ide, teknologi, manusia, dan bahkan epidemi melintasi batas dengan kecepatan dan intensitas yang tidak pernah terjadi sebelumnya…Ada kesempatan dan juga risiko baru. Untuk perubahan-perubahan ini, saya melihat bahwa kita telah tiba di Era Pembangunan Berkelanjutan.” (Sachs 2015).
Teguh Yudo Wicaksono
Head of Mandiri Institute.
Tahun 2020 tampaknya menjadi salah satu masa kelam bagi globalisasi. Sepanjang sejarah, globalisasi sudah menjadi narasi besar tentang kita dan segala bentuk pencapaian manusia. Ia digambarkan sebagai proses integrasi aktivitas ekonomi dan kultur lintas batas. Efek dari globalisasi tidak saja terasa dari perubahan kondisi kesejahteraan dan ekonomi, tetapi juga perubahan kultur dan sistem politik.
Melalui keterbukaan arus perdagangan dan gagasan paska perang dunia kedua, kita menjadi saksi kenaikan dramatis kesejahteraan dan perdamaian terpanjang dalam sejarah manusia modern. Pada 1980-1990-an, kebijakan perdagangan yang lebih terbuka menjadi kunci pertumbuhan tinggi Indonesia. China, dengan pertumbuhan dramatis sejak akhir 1990-an, juga menjadi contoh nyata dari manfaat globalisasi.
Namun dalam dua tahun belakangan ini semua seolah bergerak mundur. Ketika Covid-19 mulai merebak, hampir seluruh negara menutup pintu bagi mobilitas manusia. Ini mungkin salah satu orkestrasi kebijakan tertutup terbesar yang pernah ada. Selain itu, banyak negara justru mencari sekoci invidual ketika persoalan pandemik menjadi global. Misalnya saja, banyak negara menutup ekspor pasokan perlindungan pribadi seperti masker dan lainnya dengan alasan mengamankan permintaan domestik.
Memasuki 2021, sains memberikan harapan bahwa kita akan menang atas Covid-19. Namun di sisi lain, temuan vaksin malah membuka tabir ketimpangan antarnegara. Negara-negara produsen vaksin, sebagian besar negara maju, memilih untuk memupuk stok lebih vaksin di atas kebutuhannya. Sementara penduduk negara-negara berkembang dan miskin masih dalam antre panjang untuk mendapatkan vaksin dosis pertama.
Kita seolah lupa bahwa cerita di balik vaksin Covid-19, yang hadir dalam hitungan singkat relatif dengan vaksin sebelumnya, juga cerita sukses globalisasi. BioNTech—perusahaan yang berbasis di Jerman dan berada di balik vaksin BiNTech-Pfizer yang didirikan oleh ilmuan Jerman asal Turki, Dr Ugur Sahin dan Dr Ozlem Tureci. Keduanya merupakan teman baik Albert Bourla, Chief Executive Pfizer yang berasal dari Turki. Pfizer sendiri merupakan perusahaan farmasi besar AS. Tanpa mobilitas manusia dan gagasan lintas batas negara, sebagai bentuk globalisasi, sulit membayangkan vaksin Covid-19 akan ditemukan dalam waktu singkat.
Tetapi memang harus diakui bahwa globalisasi memberikan manfaat yang tidak merata. Ada pihak yang dirugikan akibat dari perdagangan yang lebih terbuka, dan telah lama kelompok ini merasa terpinggirkan dari arus globalisasi. Sebagian besar rasa ketidakpuasan atas globalisasi berasal dari negara-negara berkembang. Namun hal yang menarik, ketidakpuasan terhadap globalisasi kini juga disuarakan oleh kelas menengah negara-negara maju seperti AS, yang selama ini justru menikmati manfaat dari globalisasi.
Profesor Joseph Stiglitz, ekonom peraih nobel ekonomi dalam bukunya “Globalization and its Discontents Revisted: Anti-Globalization in the Era of Trump” (2017), menulis bahwa penentang globalisasi kini juga berasal dari kelas bawah dan menengah negara-negara maju, kelompok yang sempat diuntungkan dari globalisasi. Presiden Trump kemudian menggunakan rasa tidak puas ini dan mengaplikasikannya untuk komoditas politik. Bahkan kebijakan bertransformasi menjadi kebijakan luar negeri AS. Di bawah administrasi Presiden Trump, AS terlibat dalam perang dagang dengan China.
Dengan meluasanya ketidakpuasan atas globalisasi hingga ke negara-negara maju, muncul pertanyaan apakah memang tren globalisasi akan berakhir? Dan apakah memang pandemi telah mempercepat laju deglobalisasi?
Sepanjang sejarah, globalisasi tidak selalu linear dan tentunya mengalami pasang surut. Tren belakangan memang menunjukkan surutnya globalisasi. Contohnya, bila kita lihat dari rasio antara perdagangan internasional—ekspor dan impor—terhadap produk domestik bruto global, ada tren penurunan atas rasio ini. Rasio perdagangan internasional terhadap PDB global mencapai puncak tertinggi di tahun 2008, yang mencapai 60,9 persen di tahun 2008—tertinggi sepanjang masa sejak perang dunia kedua (World Bank 2020).
Namun sejak krisis keuangan global di tahun 2008-2009, rasio ini anjlok menjadi 52,4 persen di tahun 2009. Pandemi Covid-19 dan perang dagang AS-China sebelumnya, juga menekan rasio ini. Di tahun 2020, rasio perdagangan internasional terhadap PDB global turun menjadi 51,5 persen, lebih rendah dibandingkan dengan periode krisis keuangan global.
Pandemik Covid-19 tampaknya memperburuk tren globalisasi. DHL Global Connected Index terbaru melaporkan bahwa pergerakan manusia di era pandemik, yang ditandai oleh perjalanan internasional per kapita, di tahun 2020 jatuh ke tingkat yang setara pada era 1970an. Satu-satunya indikator globalisasi yang masih kuat hanyalah indeks informasi, yang disebabkan karena kenaikan drastis penggunaan internet akibat Covid-19.
Namun di sisi lain ada indikasi arus balik dari tren deglobalisasi ini. Memasuki tahun 2021 kita melihat adanya kenaikan drastis aliran perdagangan global. Temuan menunjukkan bahwa jalur perdagangan tersibuk di dunia tetap menjadi jalur timur transpasifik antara Asia dan wilayah Amerika Utara. Bahkan ditengah disrupsi rantai suplai, Port of Los Angeles—salah satu pelabuhan tersibuk di AS—mencatat kenaikan drastis di bulan September 2021 (Greene 2021).
Persoalan Global Butuh Kerja Sama Global
Selain pandemi Covid-19, kita juga menghadapi persoalan global yang seharusnya menguatkan kerja sama global. Perubahan iklim, ancaman eksistensial yang nyata, sangat membutuhkan solusi dan kerja sama yang bersifat global.
Laporan terakhir dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) telah sangat jelas menunjukkan bahwa tanpa aksi serius untuk mengatasi perubahan iklim, suhu global dunia akan meningkat lebih dari 2°C di tahun 2100 dibandingkan dengan era sebelum revolusi industri. Bila ini terjadi maka manusia telah kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan diri dari bencana global.
Temun IPCC ini juga menjadi latar belakang pentingnya pertemuan tingkat tinggi Conference of Parties ke 26 (COP26) ke-26 di Glasgow, Inggris. Pertemuan KTT COP26 di Glasgow telah menyepakati empat tujuan besar yang mencakup antara lain Mitigasi, Adaptasi, Mobilisasi keuangan global, dan Kolaborasi antarnegara untuk mencapai target yang ambisius.
Bagi sejumlah pihak, komitmen negara-negara maju di COP26 ini untuk menurunkan emisi dan juga membantu negara-negara berkembang menurunkan emisi masih dinilai belum cukup. Professor Jeffrey Sachs dari Universitas Columbia dengan cukup keras menilai bahwa keputusan COP26 masih jauh dari hal yang diperlukan untuk menyelamatkan bumi dari petaka perubahan iklim (Jeffrey Sachs, Fixing the Climate Finance 2021).
Salah satu penyebabnya adalah soal mobilisasi sumber dana untuk penurunan emisi. Ini menjadi menjadi episentrum ketidaksepakatan banyak negara. Negara-negara berkembang melihat bahwa negara-negara maju, yang juga penyumbang emisi terbesar secara akumulatif, tidak menepati janji dalam memobilisasi dana sebesar US$ 100 miliar per tahun untuk menghadapi perubahan iklim pada tahun 2020 lalu.
Indonesia sendiri melalui Nationally Determined Contribution (NDC)—kontribusi pengurangan emisi—sekitar 29 persen dengan upaya nasional hingga 41 persen dari emisi yang dihasilkan pada skenario business as usual (BaU) pada 2030. Namun demikian, Indonesia membutuhkan setidaknya total pembiayaan sebesar Rp3.779 triliun dari 2020 hingga 2030, atau setara dengan Rp346 triliun per tahun (Kementerian Keuangan 2021).
Dari total pendanaan di atas, Indonesia sendiri menghadapi gap pembiayaan yang besar. Untuk itu kerja sama global yang lebih kuat untuk memobilisasi pembiayaan internasional sangat penting. Indonesia sendiri, sebagai perwakilan negara berkembang, harus menyuarakan kebutuhan ini di forum internasional.
Masa Depan Globalisasi dalam Tanda Tanya
Memasuki 2022, sejumlah outlook memberikan sejumlah harapan tentang globalisasi. DHL connected index—salah satu metrik globalisasi—memproyeksikan bahwa indeks diperkirakan akan berada di tingkat 130 pada 2022, menjadi puncak tertinggi baru sepanjang sejarah indeks ini. Selain itu, sepanjang 2020 hingga 2021, pandemi telah menjadi ujian besar bagi konektivitas, integrasi global diperkirakan akan tetap lebih tinggi dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Hal ini merupakan berita yang menggembirakan.
Namun ketidakpastian masih sangat besar. Persaingan geopolitik, terutama antara AS dan China, masih menjadi batu sandungan besar untuk mengatasi persoalan global seperti perubahan iklim. Selain itu, pandemi juga berpotensi mengubah tatanan order internasional.
Mandiri Investment Forum (MIF) 2022 yang diadakan oleh Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas, bekerjasama dengan Kementerian Investasi/BKPM menjadi forum yang mengumpulkan investor, para ekonom dan juga pengambil kebijakan untuk diskusi dan meneropong lagi soal tantangan nasional dan global. Tahun ini MIF 2022 mengusung tema “Recapturing the Growth Momentum”.
Salah satu panel dalam forum ini akan diisi oleh Professor Joseph Stiglitz dan Professor Jeffrey Sachs, yang secara bersama-sama diskusi mengenai masa depan globalisasi. Hal yang juga penting adalah hal yang kritikal terkait dengan perubahan iklim adalah bagaimana mendorong kerja sama global dalam memobilisasi sumber daya untuk mengatasi perubahan iklim.
Kerja sama global dalam pemulihan ekonomi juga merupakan tema besar yang diusung Indonesia dalam Presidensi G20, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Selain itu Indonesia juga akan mengusung green economy dan keberlanjutan (sustainability) sebagai tema spesifik dari G20 tahun ini.
Sebagai penutup, saya ingin mengutip pesan Professor Jeffrey Sachs dalam bukunya The Age of Sustainable Development. Prof Sachs menulis bahwa : “Kita telah memasuki era baru. Masyarakat global saling berhubungan tidak seperti sebelumnya. Bisnis, ide, teknologi, manusia, dan bahkan epidemi melintasi batas dengan kecepatan dan intensitas yang tidak pernah terjadi sebelumnya…Ada kesempatan dan juga risiko baru. Untuk perubahan-perubahan ini, saya melihat bahwa kita telah tiba di Era Pembangunan Berkelanjutan.” (Sachs 2015).
(atk)