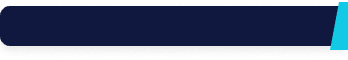Sejarah Freeport di Indonesia 2: Ertsberg dan Andil Julius Tahija

Sejarah Freeport di Indonesia 2: Ertsberg dan Andil Julius Tahija
A
A
A
PENEMUAN Ertsberg memberi berkah bagi Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu pada awalnya. Saat sedang membangun dan mengembangkan tambang nikel di Moa Bay, Kuba, angin politik berubah. Dalam artikel bertajuk “JFK, Indonesia, CIA and Freeport” yang ditulis Lisa Pease pada 1996 di majalah Probe, pergantian kekuasaan membuat Freeport kecewa.
Fidel Castro menggulingkan kekuasaan rezim militer Jenderal Fulgencio Batista yang pro-Amerika Serikat. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasi. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terpaksa angkat kaki.
Hilangnya operasi nikel di Kuba mendorong Freeport memperluas diversifikasi usaha ke seluruh dunia. Dan pertemuan Forbes Wilson dengan Jean Jacques Dozy, membuat Freeport mengalihkan pandangan ke Ertsberg.
Tetapi untuk melanjutkan proyek Ertsberg, Freeport harus melakukan pemboran secara sistematis supaya cadangan bijih dapat dievaluasi dengan pasti. Hanya pekerjaan tersebut tidak mudah dilaksanakan. Faktor penyebabnya kendala teknis saat itu. Untuk membawa peralatan bor yang berton-ton beratnya sulit dilakukan dengan menggunakan perahu dorong.
Jalan keluar satu-satunya ialah memakai helikopter. Namun pada awal tahun 1960-an, helikopter masih menggunakan mesin piston. Untuk terbang menjelajah Ertsberg dengan ketinggian 3.600 meter, helikopter jenis itu hanya mampu mengangkut satu orang dengan beban 210 kilogram.
Dengan kemampuan terbatas, diperlukan waktu berbulan-bulan untuk membawa satu unit peralatan bor dan operatornya ke Ertsberg.
Selain kendala teknis, faktor politik menjadi tantangan terbesar bagi Freeport. Saat itu, Pemerintahan Soekarno sedang bersitegang dengan Belanda soal status New Guinea Barat (sekarang Papua). Belanda berdalih New Guinea secara alamiah tidak mempunyai hubungan geografis dan budaya dengan Kepulauan Nusantara. Dengan demikian, dalil Belanda, New Guinea tidak harus masuk ke dalam Negara Indonesia yang baru merdeka.
Indonesia memprotes dalih Belanda. Presiden Soekarno lalu mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa agar Belanda menyerahkan New Guinea Barat ke Republik Indonesia. Tetapi dalam perdebatan di PBB tahun 1957, Indonesia kalah. Di dalam negeri, Presiden Soekarno mengambil tindakan drastis dengan mengusir warga Belanda dan menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia.
Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno memaklumatkan Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) di Alun-alun Utama Yogyakarta dan menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Operasi Mandala. Soekarno lantas mengganti nama New Guinea Barat menjadi Irian yang merupakan kepanjangan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland.
Operasi militer ini tidak berujung perang terbuka. Belanda pun mendapat tekanan dari Amerika Serikat. Pasalnya, Negeri Paman Sam khawatir dengan semakin mesranya Bung Karno dengan blok Uni Soviet, sehingga AS menekan Belanda untuk menyerah.
Bulan Agustus 1962, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada PBB. Setelah itu pada 1963, PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Setelah Irian Barat berada dalam naungan Republik Indonesia, Freeport juga belum bisa mengembangkan proyek Ertsberg. Kedekatan Soekarno dengan kelompok kiri menjadi penyebabnya. Soekarno ketika itu akrab dengan Republik Rakyat China dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan, pada 1963, hampir semua perusahaan asing diusir dari Indonesia, bersamaan dengan keluarnya Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pecahnya kudeta G-30S/PKI pada 1965, membuat situasi politik di Indonesia berubah. Pengaruh Soekarno memudar seiring gagalnya pemberontakan tersebut. Mayor Jenderal Soeharto berhasil mematahkan pemberontakan. Sejak awal 1967, Soeharto secara resmi ditunjuk menjadi Pejabat Presiden dan setahun kemudian menjadi Presiden.
Berbeda dengan pendahulunya, Presiden Soeharto anti-komunis dan sangat prakmatis dalam hal perekonomian. Soeharto lalu menarik modal asing untuk membangun Indonesia. Hal ini menjadi babak baru bagi Freeport untuk melanjutkan proyek Ertsberg.
Pemimpin Freeport saat itu, Langbourne William mendengar kabar perubahan politik di Indonesia dari Texaco. Perusahaan ini berhasil mempertahankan usahanya di Indonesia kendati ada pergolakan politik. Keberhasilan Texaco ini tidak lepas dari Manajer Indonesia bernama Julius Tahija.
Pada Februari 1966, petinggi Freeport menemui Tahija yang juga pimpinan Texaco. Ia merupakan usahawan yang gesit dan mempunyai banyak relasi. Sebagai orang Ambon, Tahija tidak termasuk dalam elit orang-orang Jawa yang berkuasa. Namun sebagai bekas militer, Tahija mempunyai banyak sahabat di lingkungan pemerintahan. Karena ia mantan serdadu KNIL dan satu angkatan dengan Soeharto.
Dalam buku berjudul “Grasberg: Mining the richest and most remote deposit of copper and gold in the world, in the mountains of Irian Jaya Indonesia”, Tahija lantas mengatur pertemuan antara Freeport dengan Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia Jenderal Ibnu Sutowo di Amsterdam, Belanda.
Meski Freeport sudah menutup rapat-rapat soal ekspedisi Ertsberg, namun Ibnu Sutowo sudah mengetahuinya. Dalam pertemuan, ia mengatakan bahwa pihak Jepang sudah mendekati dan bermaksud melakukan proyek Ertsberg.
Dalam buku Grasberg yang ditulis oleh George A. Mealey, ahli pertambangan yang kemudian menjadi Chief Operating Officer Freeport-McMoRan Copper & Gold, menuliskan bahwa Departemen Pertambangan (kini Kementerian ESDM) yang menganjurkan pihak Jepang untuk mengembangkan Ertsberg. Tetapi pihak Jepang tidak berhasil menemukan Ertsberg dan Departemen Pertambangan kehilangan minat terhadap mereka.
Namun karena Ibnu Sutowo melihat Freeport lebih mampu untuk segera membawa proyek ini pada tingkat produksi, akhirnya membolehkan Freeport untuk meneruskan operasi Ertsberg.
Presiden Freeport Robert Hill dan Forbes Wilson lantas menanyakan kepada Tahija, siapa yang pantas mewakili Freeport untuk berunding dengan Pemerintah Indonesia. Tahija menyodorkan nama Ali Budiardjo. Nama terakhir pernah menjadi penasehat Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia Jenderal Mayor Tahi Bonar Simatupang. Kemudian menjadi pejabat di Departemen Penerangan dan Biro Perancang Negara (kini Bappenas).
Denise Leith dalam bukunya The Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia, menuliskan bahwa Ali Budiardjo mengatakan Freeport sebagai klien pertamanya.
Adapun wawancara dengan Jeffrey Alan Winters, 24 Maret 1989, Ali menceritakan pertemuan pertamanya dengan Freeport pada Juli 1966 dan kedua pada Oktober 1966. “Kami canggung. Karena belum punya dasar hukum untuk melaksanakan perjanjian investasi,” kata Ali, sebagaimana ditulis Jeffrey dalam bukunya Power in Motion: Capital Mobility and The Indonesian State.
Pasalnya, saat itu Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur investasi asing. Hal ini karena sebelumnya, Indonesia di bawah Pemerintahan Soekarno mengusung ekonomi berdikari.
Ali yang juga mendirikan kantor hukum, disebut-sebut menemukan konsep Kontrak Karya (KK). Sebelumnya, Menteri Pertambangan Indonesia menawarkan kepada Freeport konsep kontrak “bagi hasil” merujuk pada pelaksanaan kontrak perminyakan asing yang disiapkan oleh Pemerintahan Soekarno dulu.
Kontrak bagi hasil dianggap cocok untuk perminyakan yang dapat menghasilkan dengan cepat, tetapi tidak untuk pertambangan tembaga yang membutuhkan investasi besar dan waktu lama untuk sampai pada tahap produksi.
Akhirnya Kontrak Karya menjadi kesepakatan. Freeport pun mendapatkan payung hukum: Undang-udang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 yang menjadi awal bagi penanaman modal asing di Indonesia.
Undang-undang ini pun mengubah wajah perekonomian Indonesia, dari sebelumnya tertutup menjadi terbuka dengan asing. “Saya yakin bahwa masa depan Indonesia sangat tergantung pada investasi dalam negeri maupun asing,” ucap Budiardjo.
Ia menambahkan saat itu, modal dalam negeri masih terlalu kecil untuk berperan. Karena Freeport merupakan investasi asing pertama di bawah undang-undang baru, maka Freeport harus berhasil agar menjadi contoh bagi penanaman modal asing lainnya. Atas jasanya, pada 1974, Ali Budiardjo menjadi orang Indonesia pertama yang menduduki posisi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia menggantikan Forbes Wilson.
Pada 5 April 1967, di bawah sorotan kamera televisi, Menteri Pertambangan Indonesia Slamet Bratanata dan Presiden Freeport Sulphur Robert Hill dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Forbes Wilson menandatangani Kontrak Karya selama 30 tahun untuk pengembangan tambang Ertsberg. Inilah Kontrak Karya pertama yang ditandatangani Indonesia di bawah UU Penanaman Modal Asing.
Pada tahun pertama operasi, Freeport menerima tax holiday. Dan harga tembaga saat itu mencapai USD1,40 per pon. Freeport pun meraih untung besar. Seiring waktu, Freeport terus meluaskan area pertambangannya.
Menjelang akhir 1972, pembangunan jalan selesai dibangun, kereta kabel berjalan lancar dan jalur pipa konsentrat terpasang baik. Pada Desember 1972, 10.000 ton bijih Ertsberg yang pertama berhasil dikapalkan.
Tiga bulan kemudian atau tepatnya Maret 1973, Presiden Soeharto meresmikan tambang Ertsberg. Dalam perjalanannya memakai kendaraan jeep, Soeharto memberi nama jalur tersebut sebagai “Tembagapura” yang berarti Kota Tembaga. Tanpa diduga, Soeharto juga mengubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya.
Fidel Castro menggulingkan kekuasaan rezim militer Jenderal Fulgencio Batista yang pro-Amerika Serikat. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasi. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terpaksa angkat kaki.
Hilangnya operasi nikel di Kuba mendorong Freeport memperluas diversifikasi usaha ke seluruh dunia. Dan pertemuan Forbes Wilson dengan Jean Jacques Dozy, membuat Freeport mengalihkan pandangan ke Ertsberg.
Tetapi untuk melanjutkan proyek Ertsberg, Freeport harus melakukan pemboran secara sistematis supaya cadangan bijih dapat dievaluasi dengan pasti. Hanya pekerjaan tersebut tidak mudah dilaksanakan. Faktor penyebabnya kendala teknis saat itu. Untuk membawa peralatan bor yang berton-ton beratnya sulit dilakukan dengan menggunakan perahu dorong.
Jalan keluar satu-satunya ialah memakai helikopter. Namun pada awal tahun 1960-an, helikopter masih menggunakan mesin piston. Untuk terbang menjelajah Ertsberg dengan ketinggian 3.600 meter, helikopter jenis itu hanya mampu mengangkut satu orang dengan beban 210 kilogram.
Dengan kemampuan terbatas, diperlukan waktu berbulan-bulan untuk membawa satu unit peralatan bor dan operatornya ke Ertsberg.
Selain kendala teknis, faktor politik menjadi tantangan terbesar bagi Freeport. Saat itu, Pemerintahan Soekarno sedang bersitegang dengan Belanda soal status New Guinea Barat (sekarang Papua). Belanda berdalih New Guinea secara alamiah tidak mempunyai hubungan geografis dan budaya dengan Kepulauan Nusantara. Dengan demikian, dalil Belanda, New Guinea tidak harus masuk ke dalam Negara Indonesia yang baru merdeka.
Indonesia memprotes dalih Belanda. Presiden Soekarno lalu mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa agar Belanda menyerahkan New Guinea Barat ke Republik Indonesia. Tetapi dalam perdebatan di PBB tahun 1957, Indonesia kalah. Di dalam negeri, Presiden Soekarno mengambil tindakan drastis dengan mengusir warga Belanda dan menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia.
Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno memaklumatkan Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) di Alun-alun Utama Yogyakarta dan menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Operasi Mandala. Soekarno lantas mengganti nama New Guinea Barat menjadi Irian yang merupakan kepanjangan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland.
Operasi militer ini tidak berujung perang terbuka. Belanda pun mendapat tekanan dari Amerika Serikat. Pasalnya, Negeri Paman Sam khawatir dengan semakin mesranya Bung Karno dengan blok Uni Soviet, sehingga AS menekan Belanda untuk menyerah.
Bulan Agustus 1962, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada PBB. Setelah itu pada 1963, PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Setelah Irian Barat berada dalam naungan Republik Indonesia, Freeport juga belum bisa mengembangkan proyek Ertsberg. Kedekatan Soekarno dengan kelompok kiri menjadi penyebabnya. Soekarno ketika itu akrab dengan Republik Rakyat China dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan, pada 1963, hampir semua perusahaan asing diusir dari Indonesia, bersamaan dengan keluarnya Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pecahnya kudeta G-30S/PKI pada 1965, membuat situasi politik di Indonesia berubah. Pengaruh Soekarno memudar seiring gagalnya pemberontakan tersebut. Mayor Jenderal Soeharto berhasil mematahkan pemberontakan. Sejak awal 1967, Soeharto secara resmi ditunjuk menjadi Pejabat Presiden dan setahun kemudian menjadi Presiden.
Berbeda dengan pendahulunya, Presiden Soeharto anti-komunis dan sangat prakmatis dalam hal perekonomian. Soeharto lalu menarik modal asing untuk membangun Indonesia. Hal ini menjadi babak baru bagi Freeport untuk melanjutkan proyek Ertsberg.
Pemimpin Freeport saat itu, Langbourne William mendengar kabar perubahan politik di Indonesia dari Texaco. Perusahaan ini berhasil mempertahankan usahanya di Indonesia kendati ada pergolakan politik. Keberhasilan Texaco ini tidak lepas dari Manajer Indonesia bernama Julius Tahija.
Pada Februari 1966, petinggi Freeport menemui Tahija yang juga pimpinan Texaco. Ia merupakan usahawan yang gesit dan mempunyai banyak relasi. Sebagai orang Ambon, Tahija tidak termasuk dalam elit orang-orang Jawa yang berkuasa. Namun sebagai bekas militer, Tahija mempunyai banyak sahabat di lingkungan pemerintahan. Karena ia mantan serdadu KNIL dan satu angkatan dengan Soeharto.
Dalam buku berjudul “Grasberg: Mining the richest and most remote deposit of copper and gold in the world, in the mountains of Irian Jaya Indonesia”, Tahija lantas mengatur pertemuan antara Freeport dengan Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia Jenderal Ibnu Sutowo di Amsterdam, Belanda.
Meski Freeport sudah menutup rapat-rapat soal ekspedisi Ertsberg, namun Ibnu Sutowo sudah mengetahuinya. Dalam pertemuan, ia mengatakan bahwa pihak Jepang sudah mendekati dan bermaksud melakukan proyek Ertsberg.
Dalam buku Grasberg yang ditulis oleh George A. Mealey, ahli pertambangan yang kemudian menjadi Chief Operating Officer Freeport-McMoRan Copper & Gold, menuliskan bahwa Departemen Pertambangan (kini Kementerian ESDM) yang menganjurkan pihak Jepang untuk mengembangkan Ertsberg. Tetapi pihak Jepang tidak berhasil menemukan Ertsberg dan Departemen Pertambangan kehilangan minat terhadap mereka.
Namun karena Ibnu Sutowo melihat Freeport lebih mampu untuk segera membawa proyek ini pada tingkat produksi, akhirnya membolehkan Freeport untuk meneruskan operasi Ertsberg.
Presiden Freeport Robert Hill dan Forbes Wilson lantas menanyakan kepada Tahija, siapa yang pantas mewakili Freeport untuk berunding dengan Pemerintah Indonesia. Tahija menyodorkan nama Ali Budiardjo. Nama terakhir pernah menjadi penasehat Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia Jenderal Mayor Tahi Bonar Simatupang. Kemudian menjadi pejabat di Departemen Penerangan dan Biro Perancang Negara (kini Bappenas).
Denise Leith dalam bukunya The Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia, menuliskan bahwa Ali Budiardjo mengatakan Freeport sebagai klien pertamanya.
Adapun wawancara dengan Jeffrey Alan Winters, 24 Maret 1989, Ali menceritakan pertemuan pertamanya dengan Freeport pada Juli 1966 dan kedua pada Oktober 1966. “Kami canggung. Karena belum punya dasar hukum untuk melaksanakan perjanjian investasi,” kata Ali, sebagaimana ditulis Jeffrey dalam bukunya Power in Motion: Capital Mobility and The Indonesian State.
Pasalnya, saat itu Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur investasi asing. Hal ini karena sebelumnya, Indonesia di bawah Pemerintahan Soekarno mengusung ekonomi berdikari.
Ali yang juga mendirikan kantor hukum, disebut-sebut menemukan konsep Kontrak Karya (KK). Sebelumnya, Menteri Pertambangan Indonesia menawarkan kepada Freeport konsep kontrak “bagi hasil” merujuk pada pelaksanaan kontrak perminyakan asing yang disiapkan oleh Pemerintahan Soekarno dulu.
Kontrak bagi hasil dianggap cocok untuk perminyakan yang dapat menghasilkan dengan cepat, tetapi tidak untuk pertambangan tembaga yang membutuhkan investasi besar dan waktu lama untuk sampai pada tahap produksi.
Akhirnya Kontrak Karya menjadi kesepakatan. Freeport pun mendapatkan payung hukum: Undang-udang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 yang menjadi awal bagi penanaman modal asing di Indonesia.
Undang-undang ini pun mengubah wajah perekonomian Indonesia, dari sebelumnya tertutup menjadi terbuka dengan asing. “Saya yakin bahwa masa depan Indonesia sangat tergantung pada investasi dalam negeri maupun asing,” ucap Budiardjo.
Ia menambahkan saat itu, modal dalam negeri masih terlalu kecil untuk berperan. Karena Freeport merupakan investasi asing pertama di bawah undang-undang baru, maka Freeport harus berhasil agar menjadi contoh bagi penanaman modal asing lainnya. Atas jasanya, pada 1974, Ali Budiardjo menjadi orang Indonesia pertama yang menduduki posisi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia menggantikan Forbes Wilson.
Pada 5 April 1967, di bawah sorotan kamera televisi, Menteri Pertambangan Indonesia Slamet Bratanata dan Presiden Freeport Sulphur Robert Hill dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Forbes Wilson menandatangani Kontrak Karya selama 30 tahun untuk pengembangan tambang Ertsberg. Inilah Kontrak Karya pertama yang ditandatangani Indonesia di bawah UU Penanaman Modal Asing.
Pada tahun pertama operasi, Freeport menerima tax holiday. Dan harga tembaga saat itu mencapai USD1,40 per pon. Freeport pun meraih untung besar. Seiring waktu, Freeport terus meluaskan area pertambangannya.
Menjelang akhir 1972, pembangunan jalan selesai dibangun, kereta kabel berjalan lancar dan jalur pipa konsentrat terpasang baik. Pada Desember 1972, 10.000 ton bijih Ertsberg yang pertama berhasil dikapalkan.
Tiga bulan kemudian atau tepatnya Maret 1973, Presiden Soeharto meresmikan tambang Ertsberg. Dalam perjalanannya memakai kendaraan jeep, Soeharto memberi nama jalur tersebut sebagai “Tembagapura” yang berarti Kota Tembaga. Tanpa diduga, Soeharto juga mengubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya.
(ven)