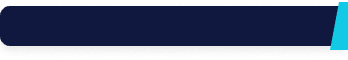Perusahaan China Akan Menghadapi Gelombang Kegagalan di 2019

Perusahaan China Akan Menghadapi Gelombang Kegagalan di 2019
A
A
A
TOKYO - Konflik dagang yang ditabuh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Republik Rakyat China, membuat perekonomian Negeri Tirai Bambu melambat menjadi 6,6% pada tahun lalu, merupakan level terendah dalam waktu 28 tahun.
Dan sejauh ini, negosiasi kedua negara ekonomi besar dunia tersebut belum menemui titik kesepakatan. Di lain sisi, gelombang kegagalan bisnis akan melanda perusahaan-perusahaan asal China di tahun ini.
Perusahaan asuransi kredit perdagangan asal Prancis, Euler Hermes, memperkirakan tingkat insolvensi perusahaan China akan naik menjadi 20% pada 2019, jauh melebihi tingkat global sebesar 6%. Insolven adalah keadaan ketika debitur tidak dapat melunasi utang kepada semua krediturnya dan debitur yang memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya.
Tingkat insolvensi perusahaan China melompat tinggi hingga 60% pada tahun 2018 kemarin, seiring dengan perekonomian mereka yang mencapai level terendah dalam hampir tiga dekade.
Menurut Euler Hermes, gelombang kegagalan perusahaan China tergambar sejak akhir tahun lalu, dimana banyak perusahaan mengungkapkan rasa sakit dalam laporan keuangan mereka. Imbas perlambatan ekonomi.
Melansir Nikkei Asian Review, Selasa (12/2/2019), perhitungan yang dilakukan oleh Nikkei menunjukkan 30% dari sekitar 3.600 perusahaan yang terdaftar di China menderita penurunan laba bersih selama tahun 2018. Sekitar 400 membukukan rugi bersih.
Sementara itu, mengutip dari South China Morning Post, pada pekan kedua Januari 2019, sebanyak 5 perusahaan China menyatakan default (gagal bayar) atas utang senilai 3,5 miliar yuan (USD446,25 juta). Pada tahun lalu, gelombang default perusahaan China mencapai USD17 miliar, imbas perlambatan ekonomi dan melambungnya biaya refinancing untuk menambal sektor swasta yang kekurangan uang.
Salah satunya, Beijing Kang Dexin Composite Material, sebuah perusahaan berteknologi tinggi yang memasok produk film optik untuk Apple dan bahan serat karbon untuk Mercedes-Benz. Akibat gagal bayar, nilai kapitalisasi pasarnya anjlok 58% dalam dua bulan terakhir menjadi 23 miliar yuan dari sebelumnya 54 miliar yuan.
Dan krisis ini akan memberi tekanan kian besar bagi perusahaan-perusahaan China di tahun 2019. Apalagi surat utang yang dikeluarkan perusahaan China sudah mencatat rekor tertinggi sepanjang masa di tahun lalu.
Terkait default, Standard & Poor’s Global Ratings baru-baru ini menurunkan rating kredit terhadap dua pengembang properti asal China, Yida China Holdings dan Guorui Properties yang terdaftar di bursa saham Hong Kong.
Fitch Ratings yang belum lama ini menetapkan prospek sektor yang stabil untuk portofolio 434 perusahaan di Asia Pasifik, menempatkan perusahaan properti China dengan prospek negatif. "Perang dagang AS dan China mulai berdampak pada perusahaan-perusahaan China," kata Direktur Senior Fitch Ratings, Matt Jamieson kepada Nikkei Asian Review.
Karena itu, Presiden China Xi Jinping menegaskan agar perusahaan mengurangi utangnya yang terlalu berlebihan. Xi Jinping lantas menjadikan masalah ini sebagai prioritas. Tujuannya mengurangi risiko ekonomi yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat utang yang dilakukan perusahaan-perusahaan China.
Pada masa lalu, Pemerintah China memberi kelonggaran utang bagi perusahaan China agar menjaga ekonomi tetap booming. Namun sejak 2017, Pemerintah China telah menekan bank untuk mengendalikan pinjaman kepada perusahaan milik negara yang dikenal sebagai perusahaan zombie. Yaitu perusahaan yang hanya mengandalkan hidup dari subsidi pemerintah dan pinjaman bank.
Media China melaporkan bahwa Beijing ingin semua perusahaan milik negara yang berstatus zombie, ditutup pada tahun 2020. Tetapi hal ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara.
Managing Partner di AIS Capital, Xio Minjie, mengatakan dalam jangka pendek, penutupan perusahaan zombie akan menjadi pukulan besar bagi ekonomi China. "Banyak dari perusahaan negara yang zombie ini adalah perusahaan-perusahaan tua yang bergerak di bidang perdagangan dan baja. Jika ditutup akan berpengaruh pada gangguan rantai pasokan," ujarnya.
Di sisi lain, ekonom senior untuk Asia di Euler Hermes, Mahamaoud Islam, mengatakan penutupan perusahaan zombie justru bisa membuat ekonomi berfungsi lebih baik dalam jangka panjang.
Euler Hermes memperkirakan tingkat kebangkrutan untuk perusahaan-perusahaan Asia lainnya akan cenderung stabil, dengan Singapura pada tingkat 3%, Hong Kong 2%, dan Jepang 1%. Namun, lonjakan kebangkrutan untuk perusahaan China di tahun 2019 ini, diperkirakan akan naik 15%.
Meski demikian, Analis Kredit Utama di Standard & Poor’s, Cindy Huang, mengatakan risiko divergensi (penyebaran) gagal bayar pada perusahaan-perusahaan China mulai menyempit, meski perusahaan yang lemah terus menghadapi risiko penurunan peringkat kredit dan default yang lebih tinggi.
Pasalnya, menurut rekan Cindy, yaitu Matthew Chow, bahwa ada tanda-tanda menggembirakan. Baru-baru ini, kata Chow, beberapa perusahaan properti di China dan perusahaan lain bergabung menerbitkan obligasi baru untuk mendapatkan dana segar.
"Situasi mulai membaik saat ini dibanding beberapa bulan lalu. Kami melihat ada peningkatan likuiditas di perusahaan properti di China. Tapi para pemain yang lemah tidak mendapat banyak manfaat dari itu," tukasnya.
Adapun Pemerintah China untuk mengatasi masalah ekonomi, berencana meningkatkan stimulus berupa pemotongan pajak, pengeluaran infrastruktur dan dana senilai 2,5 triliun yuan atau setara USD370 miliar. Selain itu, pemerintah juga mendorong bank untuk memberikan lebih banyak kredit kepada perusahaan negara yang sehat.
Dan sejauh ini, negosiasi kedua negara ekonomi besar dunia tersebut belum menemui titik kesepakatan. Di lain sisi, gelombang kegagalan bisnis akan melanda perusahaan-perusahaan asal China di tahun ini.
Perusahaan asuransi kredit perdagangan asal Prancis, Euler Hermes, memperkirakan tingkat insolvensi perusahaan China akan naik menjadi 20% pada 2019, jauh melebihi tingkat global sebesar 6%. Insolven adalah keadaan ketika debitur tidak dapat melunasi utang kepada semua krediturnya dan debitur yang memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya.
Tingkat insolvensi perusahaan China melompat tinggi hingga 60% pada tahun 2018 kemarin, seiring dengan perekonomian mereka yang mencapai level terendah dalam hampir tiga dekade.
Menurut Euler Hermes, gelombang kegagalan perusahaan China tergambar sejak akhir tahun lalu, dimana banyak perusahaan mengungkapkan rasa sakit dalam laporan keuangan mereka. Imbas perlambatan ekonomi.
Melansir Nikkei Asian Review, Selasa (12/2/2019), perhitungan yang dilakukan oleh Nikkei menunjukkan 30% dari sekitar 3.600 perusahaan yang terdaftar di China menderita penurunan laba bersih selama tahun 2018. Sekitar 400 membukukan rugi bersih.
Sementara itu, mengutip dari South China Morning Post, pada pekan kedua Januari 2019, sebanyak 5 perusahaan China menyatakan default (gagal bayar) atas utang senilai 3,5 miliar yuan (USD446,25 juta). Pada tahun lalu, gelombang default perusahaan China mencapai USD17 miliar, imbas perlambatan ekonomi dan melambungnya biaya refinancing untuk menambal sektor swasta yang kekurangan uang.
Salah satunya, Beijing Kang Dexin Composite Material, sebuah perusahaan berteknologi tinggi yang memasok produk film optik untuk Apple dan bahan serat karbon untuk Mercedes-Benz. Akibat gagal bayar, nilai kapitalisasi pasarnya anjlok 58% dalam dua bulan terakhir menjadi 23 miliar yuan dari sebelumnya 54 miliar yuan.
Dan krisis ini akan memberi tekanan kian besar bagi perusahaan-perusahaan China di tahun 2019. Apalagi surat utang yang dikeluarkan perusahaan China sudah mencatat rekor tertinggi sepanjang masa di tahun lalu.
Terkait default, Standard & Poor’s Global Ratings baru-baru ini menurunkan rating kredit terhadap dua pengembang properti asal China, Yida China Holdings dan Guorui Properties yang terdaftar di bursa saham Hong Kong.
Fitch Ratings yang belum lama ini menetapkan prospek sektor yang stabil untuk portofolio 434 perusahaan di Asia Pasifik, menempatkan perusahaan properti China dengan prospek negatif. "Perang dagang AS dan China mulai berdampak pada perusahaan-perusahaan China," kata Direktur Senior Fitch Ratings, Matt Jamieson kepada Nikkei Asian Review.
Karena itu, Presiden China Xi Jinping menegaskan agar perusahaan mengurangi utangnya yang terlalu berlebihan. Xi Jinping lantas menjadikan masalah ini sebagai prioritas. Tujuannya mengurangi risiko ekonomi yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat utang yang dilakukan perusahaan-perusahaan China.
Pada masa lalu, Pemerintah China memberi kelonggaran utang bagi perusahaan China agar menjaga ekonomi tetap booming. Namun sejak 2017, Pemerintah China telah menekan bank untuk mengendalikan pinjaman kepada perusahaan milik negara yang dikenal sebagai perusahaan zombie. Yaitu perusahaan yang hanya mengandalkan hidup dari subsidi pemerintah dan pinjaman bank.
Media China melaporkan bahwa Beijing ingin semua perusahaan milik negara yang berstatus zombie, ditutup pada tahun 2020. Tetapi hal ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara.
Managing Partner di AIS Capital, Xio Minjie, mengatakan dalam jangka pendek, penutupan perusahaan zombie akan menjadi pukulan besar bagi ekonomi China. "Banyak dari perusahaan negara yang zombie ini adalah perusahaan-perusahaan tua yang bergerak di bidang perdagangan dan baja. Jika ditutup akan berpengaruh pada gangguan rantai pasokan," ujarnya.
Di sisi lain, ekonom senior untuk Asia di Euler Hermes, Mahamaoud Islam, mengatakan penutupan perusahaan zombie justru bisa membuat ekonomi berfungsi lebih baik dalam jangka panjang.
Euler Hermes memperkirakan tingkat kebangkrutan untuk perusahaan-perusahaan Asia lainnya akan cenderung stabil, dengan Singapura pada tingkat 3%, Hong Kong 2%, dan Jepang 1%. Namun, lonjakan kebangkrutan untuk perusahaan China di tahun 2019 ini, diperkirakan akan naik 15%.
Meski demikian, Analis Kredit Utama di Standard & Poor’s, Cindy Huang, mengatakan risiko divergensi (penyebaran) gagal bayar pada perusahaan-perusahaan China mulai menyempit, meski perusahaan yang lemah terus menghadapi risiko penurunan peringkat kredit dan default yang lebih tinggi.
Pasalnya, menurut rekan Cindy, yaitu Matthew Chow, bahwa ada tanda-tanda menggembirakan. Baru-baru ini, kata Chow, beberapa perusahaan properti di China dan perusahaan lain bergabung menerbitkan obligasi baru untuk mendapatkan dana segar.
"Situasi mulai membaik saat ini dibanding beberapa bulan lalu. Kami melihat ada peningkatan likuiditas di perusahaan properti di China. Tapi para pemain yang lemah tidak mendapat banyak manfaat dari itu," tukasnya.
Adapun Pemerintah China untuk mengatasi masalah ekonomi, berencana meningkatkan stimulus berupa pemotongan pajak, pengeluaran infrastruktur dan dana senilai 2,5 triliun yuan atau setara USD370 miliar. Selain itu, pemerintah juga mendorong bank untuk memberikan lebih banyak kredit kepada perusahaan negara yang sehat.
(ven)