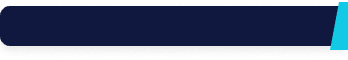Buru-buru Masifkan PLTSa, Guru Besar UI Ingatkan Bahayanya
loading...

Keinginan pemerintah memasifkan penggunaan PLTSa dinilai justru bisa mengancam sistem kelistrikan. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Keinginan pemerintah mempercepat bauran energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi 23% pada 2025 dengan memasifkan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atap (PLTSa) dinilai bisa mengancam sistem kelistrikan.
Terlebih saat ini ada rencana merevisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 49/2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Isi dari Permen ESDM yang sedang diharmonisasi tersebut menyebutkan bahwa tarif ekspor-impor PLTS Atap akan menjadi 100% atau naik 35% dibandingkan dengan peraturan lama yang hanya 65%. Artinya, PLN harus membeli 100% listrik dari PLTS atap.
Terkait alasan pengembangan EBT secara masif ini, Guru Besar Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) Iwa Garniwa menunjukkan bahwa data statistik justru menunjukkan bahwa Indonesia hanya menyumbang emisi 1,8%. Angka itu jauh di bawah China yang sebesar 2,8% dan Jepang 3,3%.
"Bahkan Amerika Serikat menyumbang emisi hingga 14,5%. Artinya, Indonesia tidak dianggap sebagai negara yang mengotori langit dunia," katanya saat diskusi bersama media, Jumat (13/8/2021).
Fakta lainnya, lanjut Iwa, sebanyak 68% pembangkit di Indonesia masih menggunakan batu bara yang harga jual listriknya murah. Dari dua fakta ini, tegas Iwa, tidak ada alasan untuk terburu-buru mengembangkan EBT secara massif.
Sementara, pemerintah melalui Kementerian ESDM terus menekan penggunaan energi berbasis fosil dari tahun ke tahun dengan mendorong secara masif pembangkit listrik berbasis EBT. Targetnya, bauran energi berbasis EBT mencapai sebesar 23% pada 2025.
Iwa mengingatkan, tujuan utama dari pengembangan energi adalah agar masyarakat mendapatkan akses energi dengan harga yang terjangkau. Sedangkan dari sisi PLN, imbuh dia, listrik harus dapat beroperasi dengan handal, berkualitas, dan juga ekonomis.
Sementara itu, terkait pengembangan PLTSa secara masif, Iwa mengingatkan bahwa pembangkit ini bersifat intermiten atau tidak bisa berdiri sendiri. Pembangkit jenis ini perlu dukungan pembangkit lain yang lebih andal agar pasokan listrik stabil. Dari sisi itu, tegas dia, bauran energi nasional harus kuat.
"Saya melihatnya begini, kita itu kebiasaan ingin gampang saja tapi tidak smart. Paling gampang kan beli PV (photovoltaic)?" ujarnya.
Iwa menambahkan, pengembangan PLTSa secara masif jangan sampai melupakan keberadaan PLN. PLTSa yang bersifat intermiten tetap membutuhkan listrik PLN dari sumber lainnya. Karena itu, kata dia, akan ada batasan, baik dari sisi keandalan maupun batasan dari sisi harga. "Tidak bisa pokoknya EBT sebanyak-banyaknya. Pembuat kebijakan kok seperti tidak paham situasi?" cetusnya.
Iwa menegaskan, meski mengembangkan PLTSa relatif mudah dan murah, namun kebijakan itu akan berdampak terhadap biaya pokok produksi (BPP) listrik PLN.
"Bayangkan misalnya jika di suatu perumahan 50% menggunakan rooftop tanpa baterai. Sementara PLN untuk menaruh gardu distribusi harus menghitung BPP. Berapa investasinya dan berapa harapan KWh yang dijual? Lalu yang 50% tadi energinya harus diambil (PLN), BPP-nya kan mahal? Bagaimana nanti pengaruhnya pada BPP PLN," tandasnya.
Terlebih saat ini ada rencana merevisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 49/2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Isi dari Permen ESDM yang sedang diharmonisasi tersebut menyebutkan bahwa tarif ekspor-impor PLTS Atap akan menjadi 100% atau naik 35% dibandingkan dengan peraturan lama yang hanya 65%. Artinya, PLN harus membeli 100% listrik dari PLTS atap.
Terkait alasan pengembangan EBT secara masif ini, Guru Besar Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) Iwa Garniwa menunjukkan bahwa data statistik justru menunjukkan bahwa Indonesia hanya menyumbang emisi 1,8%. Angka itu jauh di bawah China yang sebesar 2,8% dan Jepang 3,3%.
"Bahkan Amerika Serikat menyumbang emisi hingga 14,5%. Artinya, Indonesia tidak dianggap sebagai negara yang mengotori langit dunia," katanya saat diskusi bersama media, Jumat (13/8/2021).
Fakta lainnya, lanjut Iwa, sebanyak 68% pembangkit di Indonesia masih menggunakan batu bara yang harga jual listriknya murah. Dari dua fakta ini, tegas Iwa, tidak ada alasan untuk terburu-buru mengembangkan EBT secara massif.
Sementara, pemerintah melalui Kementerian ESDM terus menekan penggunaan energi berbasis fosil dari tahun ke tahun dengan mendorong secara masif pembangkit listrik berbasis EBT. Targetnya, bauran energi berbasis EBT mencapai sebesar 23% pada 2025.
Iwa mengingatkan, tujuan utama dari pengembangan energi adalah agar masyarakat mendapatkan akses energi dengan harga yang terjangkau. Sedangkan dari sisi PLN, imbuh dia, listrik harus dapat beroperasi dengan handal, berkualitas, dan juga ekonomis.
Sementara itu, terkait pengembangan PLTSa secara masif, Iwa mengingatkan bahwa pembangkit ini bersifat intermiten atau tidak bisa berdiri sendiri. Pembangkit jenis ini perlu dukungan pembangkit lain yang lebih andal agar pasokan listrik stabil. Dari sisi itu, tegas dia, bauran energi nasional harus kuat.
"Saya melihatnya begini, kita itu kebiasaan ingin gampang saja tapi tidak smart. Paling gampang kan beli PV (photovoltaic)?" ujarnya.
Iwa menambahkan, pengembangan PLTSa secara masif jangan sampai melupakan keberadaan PLN. PLTSa yang bersifat intermiten tetap membutuhkan listrik PLN dari sumber lainnya. Karena itu, kata dia, akan ada batasan, baik dari sisi keandalan maupun batasan dari sisi harga. "Tidak bisa pokoknya EBT sebanyak-banyaknya. Pembuat kebijakan kok seperti tidak paham situasi?" cetusnya.
Iwa menegaskan, meski mengembangkan PLTSa relatif mudah dan murah, namun kebijakan itu akan berdampak terhadap biaya pokok produksi (BPP) listrik PLN.
"Bayangkan misalnya jika di suatu perumahan 50% menggunakan rooftop tanpa baterai. Sementara PLN untuk menaruh gardu distribusi harus menghitung BPP. Berapa investasinya dan berapa harapan KWh yang dijual? Lalu yang 50% tadi energinya harus diambil (PLN), BPP-nya kan mahal? Bagaimana nanti pengaruhnya pada BPP PLN," tandasnya.
(fai)