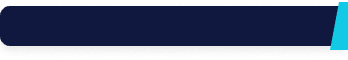Regulasi Keamanan Pangan Diskriminatif Bukan Prinsip Regulatory yang Baik
loading...

Peneliti senior mengatakan regulasi keamanan pangan diskriminatif yang hanya diberlakukan pada satu produk tertentu saja bukan prinsip regulatory yang baik. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Mantan Vice-Chair Codex Alimentarius Commission (CAC), Purwiyatno Hariyadi yang juga peneliti senior Seafast Center LPPM IPB mengatakan regulasi keamanan pangan diskriminatif yang hanya diberlakukan pada satu produk tertentu saja bukan prinsip regulatory yang baik. Menurutnya, hal itu bisa menyebabkan tujuan dari kebijakan yang mau dibuat itu tidak tercapai.
Hal itu disampaikannya menanggapi wacana revisi kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mau mewajibkan pelabelan “berpotensi mengandung BPA” hanya pada produk kemasan galon guna ulang saja. Baru-baru ini BPOM mengadakan sarasehan yang disebut sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat melalui regulasi pelabelan BPA pada air minum dalam kemasan (AMDK) di Medan, Sumatera Utara.
BPOM mengatakan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap kemasan AMDK galon guna ulang, ditemukan migrasi BPA yang sudah di atas batas ambang yang membahayakan kesehatan.
Menurut Purwiyatno, penelitian yang dilakukan hanya kepada produknya saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa itu membahayakan bagi kesehatan. “Kalau kita bicara mengenai resiko keamanan pangan maka landasannya adalah bukannya ada atau tidak ada bahaya dalam hal ini BPA dalam produknya, tetapi seberapa besar paparan atau exposure BPA tersebut terhadap masyarakat,” ujarnya.
Dia mengutarakan bahwa kebijakan terkait pelabelan BPA ini termasuk regulatory science yang harus mempertimbangkan berbagai faktor. Di antaranya faktor ekonomi, sosial, dan lain-lain, termasuk aspek politik juga bisa masuk di sana.
“Makanya, ketika kita basisnya paparan, maka semua potensi paparan itu harus dihitung, harus dicek. Jadi misalnya masyarakat kita itu berpotensi terpapar BPA, itu harus diteliti juga dari mana saja BPA itu berasal. Karena kurang bermakna juga kalau yang ditekankan itu hanya potensi paparannya saja,” tukasnya.
Karena, menurutnya, ujung dari me-manage resiko itu adalah mengurangi resiko terpapar terhadap bahaya yang diidentifikasi tersebut. “Jadi, penelitiannya harus lengkap agar efektif dan efisien. Karena, kalau hanya parsial, bisa jadi tujuan dari kebijakan itu tidak tercapai,” ungkapnya.
Jadi, tegasnya, yang diteliti itu bukan jumlah BPA pada produk tetapi jumlah BPA yang masuk ke dalam tubuh. “Dan itu juga, yang diuji seharusnya tidak hanya BPA yang ada pada produk AMDK saja, tapi semua kemasan pangan lain yang juga ber-BPA,” ucapnya.
Dia mengatakan, bahwa melakukan kajian resiko kepada masyarakat itu sesuai dengan amanat PP No.86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
Hal itu disampaikannya menanggapi wacana revisi kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mau mewajibkan pelabelan “berpotensi mengandung BPA” hanya pada produk kemasan galon guna ulang saja. Baru-baru ini BPOM mengadakan sarasehan yang disebut sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat melalui regulasi pelabelan BPA pada air minum dalam kemasan (AMDK) di Medan, Sumatera Utara.
BPOM mengatakan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap kemasan AMDK galon guna ulang, ditemukan migrasi BPA yang sudah di atas batas ambang yang membahayakan kesehatan.
Menurut Purwiyatno, penelitian yang dilakukan hanya kepada produknya saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa itu membahayakan bagi kesehatan. “Kalau kita bicara mengenai resiko keamanan pangan maka landasannya adalah bukannya ada atau tidak ada bahaya dalam hal ini BPA dalam produknya, tetapi seberapa besar paparan atau exposure BPA tersebut terhadap masyarakat,” ujarnya.
Dia mengutarakan bahwa kebijakan terkait pelabelan BPA ini termasuk regulatory science yang harus mempertimbangkan berbagai faktor. Di antaranya faktor ekonomi, sosial, dan lain-lain, termasuk aspek politik juga bisa masuk di sana.
“Makanya, ketika kita basisnya paparan, maka semua potensi paparan itu harus dihitung, harus dicek. Jadi misalnya masyarakat kita itu berpotensi terpapar BPA, itu harus diteliti juga dari mana saja BPA itu berasal. Karena kurang bermakna juga kalau yang ditekankan itu hanya potensi paparannya saja,” tukasnya.
Karena, menurutnya, ujung dari me-manage resiko itu adalah mengurangi resiko terpapar terhadap bahaya yang diidentifikasi tersebut. “Jadi, penelitiannya harus lengkap agar efektif dan efisien. Karena, kalau hanya parsial, bisa jadi tujuan dari kebijakan itu tidak tercapai,” ungkapnya.
Jadi, tegasnya, yang diteliti itu bukan jumlah BPA pada produk tetapi jumlah BPA yang masuk ke dalam tubuh. “Dan itu juga, yang diuji seharusnya tidak hanya BPA yang ada pada produk AMDK saja, tapi semua kemasan pangan lain yang juga ber-BPA,” ucapnya.
Dia mengatakan, bahwa melakukan kajian resiko kepada masyarakat itu sesuai dengan amanat PP No.86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.