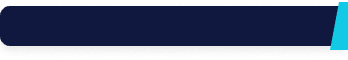Cetak Uang Demi Atasi Krisis, Ini Untung-Ruginya Kata Ekonom
loading...

Wacana mencetak uang untuk membiayai pemulihan ekonomi dan mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19 menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Wacana mencetak uang dalam jumlah masif, antara Rp600 triliun hingga Rp4.000 triliun untuk mengatasi mengemuka dengan semakin besarnya kebutuhan pembiayaan anggaran. Tindakan ini dinilai sebagai langkah cepat yang dibutuhkan dalam menangani dampak pandemi, yang dikhawatirkan mendorong terjadinya krisis ekonomi .
Belum lama ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, usulan itu masuk akal. Dia pun tak khawatir, terutama dari sisi inflasi yang kerap kali dikhawatirkan otoritas moneter. Dikatakan Said, kebijakan mencetak uang tentu berakibat pada peningkatan inflasi dapat dimitigasi dengan berbagai instrumen pengendalian yang wewenangnya dimiliki Bank Indonesia, misalnya melalui BI Rate dan kewenangan penetapan Giro Wajib Minimum (GWM).
"Kalau cetak uang Rp600 triliun kemudian seakan-akan uangnya banjir, tidak juga. Hitungan kami kalau BI cetak Rp600 triliun, itu inflasinya sekitar 5-6%, tidak banyak. Masa Rp600 triliun tiba-tiba inflasi akan naik 60-70%? tidak juga kalau menurut kami," ungkapnya belum lama ini.
Menanggapi wacana ini, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet yang dihubungi SINDOnews membeberkan untung-ruginya langkah ini. Dia mengatakan, bertambahnya kebutuhan pembiayaan anggaran saat ini tidak terlepas dari beragam insentif yang dikeluarkan pemerintah baik itu untuk pemulihan ekonomi maupun kesehatan.
"Nah di sisi lain, likuiditas untuk kebutuhan pembiayaan di saat ini tentu tidak mudah mendapatkannya baik itu di luar negeri maupun dalam negeri, makanya wacana ini muncul," ujar Yusuf di Jakarta, Kamis (14/5/2020).
(Baca Juga: Alasan Banggar DPR Dorong BI Cetak Uang Rp600 Triliun)
Yusuf melanjutkan, sisi positif dari wacana ini, di level tertentu, adalah pemerintah tidak perlu repot-repot mencari sumber pembiayaan dari luar negeri, seperti sebelumnya pemerintah sempat mewacanakan untuk menerbitkan surat utang dengan tenor hingga 50 tahun. Dengan kebijakan ini, pilihan tersebut bisa diminimalisir.
"Sisi positif lainnya, dengan perhitungan tertentu, pemerintah bisa menambah nominal insentif di tengah kebutuhan insentif yang semakin bertambah karena adanya Covid-19 mulai dari misalnya menambah dana bansos, menambah penerima kartu pra-kerja, hingga kebijakan transfer langsung kepada masyarakat," ungkapnya.
Namun demikian, sambung dia, secara teoritis, kebijakan mencetak uang bisa mengerek inflasi. Apalagi jika kecepatan peredaran jumlah uang yang beredar (dicetak) lebih cepat dari pemenuhan kebutuhan barang yang tersedia di masyarakat.
"Hal inilah yang kemudian memantik perdebatan sekarang, apakah kebijakan cetak uang ini tepat karena bisa memantik inflasi. Untuk itu memang diperlukan exercise dari Bank Indonesia (BI), jika memang wacana ini mau dilakukan, seberapa besar inflasi yang terjadi jika BI menjalankan kebijakan ini," imbuh Yusuf.
Karena, kata dia, beberapa penelitian menunjukkan, hubungan negatif antara penambahan jumlah uang beredar terhadap inflasi. Inflasi yang terjadi di Indonesia juga lebih sering disumbangkan faktor misalnya kelangkaan bahan pangan dibandingkan kenaikan jumlah uang beredar. "Jangan dilupakan juga disaat pandemi seperti sekarang inflasi kecenderungannya rendah karena daya beli melemah," tambahnya.
(Baca Juga: Gubernur BI Tolak Cetak Uang Rp4.000 Triliun Demi Tangani Covid-19)
Indonesia memang pernah mengadopsi kebijakan ini sebelumnya di periode Orde Lama, dimana saat itu BI belum seindependen sekarang, dituntut untuk mendukung program prioritas politik pemerintah.
"Sayangnya saat itu kebutuhan pembiayaan pembangunan begitu besar dan BI terus melakukan kebijakan pencetakan uang. Karena kebijakan ini, ditambah alur distribusi barang yang tersendat dan kondisi politik yang tidak mendukung, akhirnya bermuara terhadap hiperinflasi (atau tingkat inflasi yang mencapai 100% atau lebih)," jelas Yusuf.
Namun, dia menambahkan, jika ditarik ke konteks saat ini kondisi Indonesia sudah jauh berbeda. Untuk beberapa pos insentif, kondisi saat ini memang berbeda dengan tahun 1998. "Waktu itu ada Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) namun lebih ke bantuan likuditas bank tertentu. Sedangkan sekarang cakupannya luas bisa untuk bansos, kartu pra-kerja, dan yang lainnya," tandasnya.
Amerika Serikat merupakan negara yang sering melakukan kebijakan pencetakan uang di saat krisis. Kebijakan AS sering dikenal dengan Quantitative Easing (QE). "Salah satu kebijakan QE AS yang paling terkenal yaitu ketika krisis keuangan 2008, untuk melakukan recovery ekonomi menambah jumlah uang beredar hingga USD4 triliun, meskipun demikian kebijakan QE ini tidak serta merta kemudian ekonomi AS menjadi pulih dalam waktu cepat. Saat itu dibutuhkan waktu dua tahun untuk kembali menormalkan pertumbuhan ekonomi AS," pungkas Yusuf.
Belum lama ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, usulan itu masuk akal. Dia pun tak khawatir, terutama dari sisi inflasi yang kerap kali dikhawatirkan otoritas moneter. Dikatakan Said, kebijakan mencetak uang tentu berakibat pada peningkatan inflasi dapat dimitigasi dengan berbagai instrumen pengendalian yang wewenangnya dimiliki Bank Indonesia, misalnya melalui BI Rate dan kewenangan penetapan Giro Wajib Minimum (GWM).
"Kalau cetak uang Rp600 triliun kemudian seakan-akan uangnya banjir, tidak juga. Hitungan kami kalau BI cetak Rp600 triliun, itu inflasinya sekitar 5-6%, tidak banyak. Masa Rp600 triliun tiba-tiba inflasi akan naik 60-70%? tidak juga kalau menurut kami," ungkapnya belum lama ini.
Menanggapi wacana ini, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet yang dihubungi SINDOnews membeberkan untung-ruginya langkah ini. Dia mengatakan, bertambahnya kebutuhan pembiayaan anggaran saat ini tidak terlepas dari beragam insentif yang dikeluarkan pemerintah baik itu untuk pemulihan ekonomi maupun kesehatan.
"Nah di sisi lain, likuiditas untuk kebutuhan pembiayaan di saat ini tentu tidak mudah mendapatkannya baik itu di luar negeri maupun dalam negeri, makanya wacana ini muncul," ujar Yusuf di Jakarta, Kamis (14/5/2020).
(Baca Juga: Alasan Banggar DPR Dorong BI Cetak Uang Rp600 Triliun)
Yusuf melanjutkan, sisi positif dari wacana ini, di level tertentu, adalah pemerintah tidak perlu repot-repot mencari sumber pembiayaan dari luar negeri, seperti sebelumnya pemerintah sempat mewacanakan untuk menerbitkan surat utang dengan tenor hingga 50 tahun. Dengan kebijakan ini, pilihan tersebut bisa diminimalisir.
"Sisi positif lainnya, dengan perhitungan tertentu, pemerintah bisa menambah nominal insentif di tengah kebutuhan insentif yang semakin bertambah karena adanya Covid-19 mulai dari misalnya menambah dana bansos, menambah penerima kartu pra-kerja, hingga kebijakan transfer langsung kepada masyarakat," ungkapnya.
Namun demikian, sambung dia, secara teoritis, kebijakan mencetak uang bisa mengerek inflasi. Apalagi jika kecepatan peredaran jumlah uang yang beredar (dicetak) lebih cepat dari pemenuhan kebutuhan barang yang tersedia di masyarakat.
"Hal inilah yang kemudian memantik perdebatan sekarang, apakah kebijakan cetak uang ini tepat karena bisa memantik inflasi. Untuk itu memang diperlukan exercise dari Bank Indonesia (BI), jika memang wacana ini mau dilakukan, seberapa besar inflasi yang terjadi jika BI menjalankan kebijakan ini," imbuh Yusuf.
Karena, kata dia, beberapa penelitian menunjukkan, hubungan negatif antara penambahan jumlah uang beredar terhadap inflasi. Inflasi yang terjadi di Indonesia juga lebih sering disumbangkan faktor misalnya kelangkaan bahan pangan dibandingkan kenaikan jumlah uang beredar. "Jangan dilupakan juga disaat pandemi seperti sekarang inflasi kecenderungannya rendah karena daya beli melemah," tambahnya.
(Baca Juga: Gubernur BI Tolak Cetak Uang Rp4.000 Triliun Demi Tangani Covid-19)
Indonesia memang pernah mengadopsi kebijakan ini sebelumnya di periode Orde Lama, dimana saat itu BI belum seindependen sekarang, dituntut untuk mendukung program prioritas politik pemerintah.
"Sayangnya saat itu kebutuhan pembiayaan pembangunan begitu besar dan BI terus melakukan kebijakan pencetakan uang. Karena kebijakan ini, ditambah alur distribusi barang yang tersendat dan kondisi politik yang tidak mendukung, akhirnya bermuara terhadap hiperinflasi (atau tingkat inflasi yang mencapai 100% atau lebih)," jelas Yusuf.
Namun, dia menambahkan, jika ditarik ke konteks saat ini kondisi Indonesia sudah jauh berbeda. Untuk beberapa pos insentif, kondisi saat ini memang berbeda dengan tahun 1998. "Waktu itu ada Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) namun lebih ke bantuan likuditas bank tertentu. Sedangkan sekarang cakupannya luas bisa untuk bansos, kartu pra-kerja, dan yang lainnya," tandasnya.
Amerika Serikat merupakan negara yang sering melakukan kebijakan pencetakan uang di saat krisis. Kebijakan AS sering dikenal dengan Quantitative Easing (QE). "Salah satu kebijakan QE AS yang paling terkenal yaitu ketika krisis keuangan 2008, untuk melakukan recovery ekonomi menambah jumlah uang beredar hingga USD4 triliun, meskipun demikian kebijakan QE ini tidak serta merta kemudian ekonomi AS menjadi pulih dalam waktu cepat. Saat itu dibutuhkan waktu dua tahun untuk kembali menormalkan pertumbuhan ekonomi AS," pungkas Yusuf.
(fai)