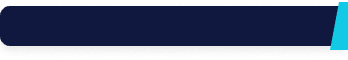Masifkan Pengembangan PLTS Atap, Guru Besar ITS: Siapkan Dulu APBN
loading...

Pemerintah disarankan menyiapkan APBN guna menanggung konsekuensi kebijakan mendorong pengembangan PLTS Atap secara masif. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) Mukhtasor mengingatkan pemerintah untuk siap menanggung konsekuensi terkait rencana revisi regulasi terkait PLTS Atap . Sebab, aturan baru itu berpotensi mengerek biaya pokok produksi (BPP) listrik yang ujungnya akan dibebankan pada pelanggan PLN atau subsidi pemerintah.
Kementerian ESDM saat ini tengah merevisi regulasi terkait pengembangan PLTS Atap di dalam negeri. Namun, dalam draf rancangan aturan itu, ada salah satu klausul yang dinilai kontroversial oleh para pakar, yakni kewajiban PLN membeli listrik dari PLTS Atap dengan harga yang sama dengan tarif dari PLN, atau 100% dari sebelumnya yang hanya 65%.
"Rencana penerbitan Permen ESDM soal PLTS Atap ini terburu-buru. Harusnya pihak terkait memberikan masukan dalam penyusunan Permen terkait revisi PLTS Atap. Jika ada informasi yang tidak match, pihak independen dilibatkan. Apalagi ini demi kepentingan nasional dan berdampak tidak hanya bagi PLN, tapi juga keuangan negara," ujar Mukthtasor dalam diskusi bersama media, Selasa (17/8/2021).
Dia mengingatkan, ketentuan yang diputuskan nanti dalam Permen ESDM terkait PLTS Atap itu harus sudah memperhitungkan konsekuensi dan mitigasinya. "Kalau ditetapkan 1:1 harus ada kompensasi kepada PLN. Berapa beban kompensasinya? Begitu juga kalau 1:0,65, berapa kompensasinya," ujarnya.
Artinya, tegas Mukhtasor, APBN harus disiapkan untuk menanggung konsekuensi dari keputusan tersebut. Namun, imbuh dia, beban tambahan APBN akibat kompensasi itu selanjutnya menimbulkan risiko tertekannya belanja pembangunan untuk sektor lain, yang bisa berujung pada terganggunya perekonomian.
Di sisi lain, kata Mukhtasior, PLTS Atap relatif hanya terjangkau golongan masyarakat tertentu di kota-kota besar. Sementara, pengembangan PLTS menurutnya lebih pas untuk menghadirkan listrik di daerah terpencil atau menggantikan pembangkit diesel yang kebanyakan digunakan di daerah.
"Jadi (jika pemerintah ingin mengembangkan EBT), sebaiknya fokus ke PLTS, bukan ke PLTS Atap. Itu hanya menguntungkan orang kaya saja," cetusnya.
Terkait dengan aturan baru yang tengah digodok pemerintah, berdasarkan kalkulasi Laboratorium Sistem Tenaga Listrik Institut Teknologi Bandung (ITB), jika tarif PLTS Atap yang dijual ke PLN ditetapkan 100% atau Rp1.444,3 per kWh, lalu diikuti penambahan kapasitas PLTS Atap sebesar 1 GW tiap tahun, maka hingga 2030 akan ada kenaikan BPP Rp11,3 per KWh atau Rp42,5 triliun selama sembilan tahun.
Kontroversi fokus Kementerian ESDM pada pengembangan PLTS Atap atau rooftop photovoltaic power station juga dipertanyakan Dosen Ekonomi Energi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satiyakti. Dia menilai hal ini lebih bersifat pencitraan internasional semata.
Pencitraan ini kemungkinan digunakan untuk menjaring investor bahwa Indonesia sedang menjalankan greenhouse gas policy sesuai dengan Nationally Determined Contributions (NDC) dari Paris Agreement.
Namun, Yayan mengatakan, meski pengembangan PLTS Atap secara masif sangat bagus demi menurunkan ketergantungan listrik berbahan bakar fosil, banyak hal yang perlu dipertimbangkan agar kebijakan ini menuai sukses. Berkaca pada pasar yang cukup berhasil mengembangkan teknologi ini, yaitu Uni Eropa, Yayan menyertakan sejumlah catatan.
Pertama, terkait insentif ekonomi bagi rumah tangga yang menggunakan teknologi ini. "Apakah insentifnya lebih banyak dibandingkan biaya investasi dan pemeliharaannya?" ujar dia.
Doktor dari Czech University of Life Science Prague itu menilai, jika instalasi, layanan purna jual, maintenance untuk teknologi ini mudah diakses dan dengan nilai investasi yang ekonomis, makan akan banyak yang tertarik.
Kedua, investasi yang efisien untuk PLTS Atap menurutnya tidak mudah. Di beberapa negara Eropa seperti Perancis, Jerman, Spanyol atau Italia, kata dia, Levelised Cost of Electricity (LCOE) kurang lebih 20 euro cent/kWh, masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan LCOE di wilayah Eropa Tengah-Timur seperti Hungaria, Bulgaria, Romania, dan Estonia yang hanya 5-10 euro cent/kWh pada 2017.
"Namun, harganya terus turun dalam jangka waktu tiga tahun sebesar 50% menjadi 5-10 euro cent/kWh. "Artinya pengembangan R&D untuk teknologi rooftop PV di Eropa sangat signifikan menurunkan LCOE selama periode 2017-2019," paparnya.
Sementara, lanjut Yayan, jika melihat tarif dasar listrik (TDL) Indonesia, harga akhir listrik di negara ini per April-Juni berada di kisaran 6-8 euro cent/kWh. "Kita dapat bayangkan ini harga konsumsi akhir, jika kita bandingkan dengan harga rooftop di EU harga tersebut adalah ongkos produksinya, jadi mereka akan jual di kisaran 9-10 euro cent/kWh. Artinya TDL saat ini tidak mendukung terhadap keekonomisan investasi teknologi rooftop PV," tegasnya.
Berdasarkan hasil perhitungan di EU, lanjut Yayan, WACC (Weight Cost of Capital) untuk investasi rooftop berada di 7% sedangkan di Indonesia WACC atau IRR keekonomian di atas 10%. "Di sini ada kesenjangan antara daya beli versus harga, investasi versus harga keekonomian," jelasnya.
Kementerian ESDM saat ini tengah merevisi regulasi terkait pengembangan PLTS Atap di dalam negeri. Namun, dalam draf rancangan aturan itu, ada salah satu klausul yang dinilai kontroversial oleh para pakar, yakni kewajiban PLN membeli listrik dari PLTS Atap dengan harga yang sama dengan tarif dari PLN, atau 100% dari sebelumnya yang hanya 65%.
"Rencana penerbitan Permen ESDM soal PLTS Atap ini terburu-buru. Harusnya pihak terkait memberikan masukan dalam penyusunan Permen terkait revisi PLTS Atap. Jika ada informasi yang tidak match, pihak independen dilibatkan. Apalagi ini demi kepentingan nasional dan berdampak tidak hanya bagi PLN, tapi juga keuangan negara," ujar Mukthtasor dalam diskusi bersama media, Selasa (17/8/2021).
Dia mengingatkan, ketentuan yang diputuskan nanti dalam Permen ESDM terkait PLTS Atap itu harus sudah memperhitungkan konsekuensi dan mitigasinya. "Kalau ditetapkan 1:1 harus ada kompensasi kepada PLN. Berapa beban kompensasinya? Begitu juga kalau 1:0,65, berapa kompensasinya," ujarnya.
Artinya, tegas Mukhtasor, APBN harus disiapkan untuk menanggung konsekuensi dari keputusan tersebut. Namun, imbuh dia, beban tambahan APBN akibat kompensasi itu selanjutnya menimbulkan risiko tertekannya belanja pembangunan untuk sektor lain, yang bisa berujung pada terganggunya perekonomian.
Di sisi lain, kata Mukhtasior, PLTS Atap relatif hanya terjangkau golongan masyarakat tertentu di kota-kota besar. Sementara, pengembangan PLTS menurutnya lebih pas untuk menghadirkan listrik di daerah terpencil atau menggantikan pembangkit diesel yang kebanyakan digunakan di daerah.
"Jadi (jika pemerintah ingin mengembangkan EBT), sebaiknya fokus ke PLTS, bukan ke PLTS Atap. Itu hanya menguntungkan orang kaya saja," cetusnya.
Terkait dengan aturan baru yang tengah digodok pemerintah, berdasarkan kalkulasi Laboratorium Sistem Tenaga Listrik Institut Teknologi Bandung (ITB), jika tarif PLTS Atap yang dijual ke PLN ditetapkan 100% atau Rp1.444,3 per kWh, lalu diikuti penambahan kapasitas PLTS Atap sebesar 1 GW tiap tahun, maka hingga 2030 akan ada kenaikan BPP Rp11,3 per KWh atau Rp42,5 triliun selama sembilan tahun.
Kontroversi fokus Kementerian ESDM pada pengembangan PLTS Atap atau rooftop photovoltaic power station juga dipertanyakan Dosen Ekonomi Energi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satiyakti. Dia menilai hal ini lebih bersifat pencitraan internasional semata.
Pencitraan ini kemungkinan digunakan untuk menjaring investor bahwa Indonesia sedang menjalankan greenhouse gas policy sesuai dengan Nationally Determined Contributions (NDC) dari Paris Agreement.
Namun, Yayan mengatakan, meski pengembangan PLTS Atap secara masif sangat bagus demi menurunkan ketergantungan listrik berbahan bakar fosil, banyak hal yang perlu dipertimbangkan agar kebijakan ini menuai sukses. Berkaca pada pasar yang cukup berhasil mengembangkan teknologi ini, yaitu Uni Eropa, Yayan menyertakan sejumlah catatan.
Pertama, terkait insentif ekonomi bagi rumah tangga yang menggunakan teknologi ini. "Apakah insentifnya lebih banyak dibandingkan biaya investasi dan pemeliharaannya?" ujar dia.
Doktor dari Czech University of Life Science Prague itu menilai, jika instalasi, layanan purna jual, maintenance untuk teknologi ini mudah diakses dan dengan nilai investasi yang ekonomis, makan akan banyak yang tertarik.
Kedua, investasi yang efisien untuk PLTS Atap menurutnya tidak mudah. Di beberapa negara Eropa seperti Perancis, Jerman, Spanyol atau Italia, kata dia, Levelised Cost of Electricity (LCOE) kurang lebih 20 euro cent/kWh, masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan LCOE di wilayah Eropa Tengah-Timur seperti Hungaria, Bulgaria, Romania, dan Estonia yang hanya 5-10 euro cent/kWh pada 2017.
"Namun, harganya terus turun dalam jangka waktu tiga tahun sebesar 50% menjadi 5-10 euro cent/kWh. "Artinya pengembangan R&D untuk teknologi rooftop PV di Eropa sangat signifikan menurunkan LCOE selama periode 2017-2019," paparnya.
Sementara, lanjut Yayan, jika melihat tarif dasar listrik (TDL) Indonesia, harga akhir listrik di negara ini per April-Juni berada di kisaran 6-8 euro cent/kWh. "Kita dapat bayangkan ini harga konsumsi akhir, jika kita bandingkan dengan harga rooftop di EU harga tersebut adalah ongkos produksinya, jadi mereka akan jual di kisaran 9-10 euro cent/kWh. Artinya TDL saat ini tidak mendukung terhadap keekonomisan investasi teknologi rooftop PV," tegasnya.
Berdasarkan hasil perhitungan di EU, lanjut Yayan, WACC (Weight Cost of Capital) untuk investasi rooftop berada di 7% sedangkan di Indonesia WACC atau IRR keekonomian di atas 10%. "Di sini ada kesenjangan antara daya beli versus harga, investasi versus harga keekonomian," jelasnya.
(fai)