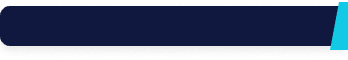Hantu Stagflasi Bangkit Lagi? Ini Penyebab dan Dampaknya
loading...

Stagflasi dicirikan dengan kenaikan harga-harga dan perlambatan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan. Foto/Dok MPI/Advenia
A
A
A
JAKARTA - Pertumbuhan lemah, inflasi tinggi, itulah stagflasi . Dunia sedang bergulat dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sangat curam disertai naiknya harga-harga. Jadi, apakah kita sedang mengalami stagflasi?
Stagflasi merupakan kondisi di mana inflasi dan kontraksi ekonomi terjadi secara bersamaan. Mengutip laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
Sedangkan stagflasi berasal dari kata stagnan dan inflasi, diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang terus melambat disertai dengan kenaikan harga secara terus-menerus.
“Jadi stag- merujuk pada stagnansi. Jadi kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan kemudian -flasi adalah untuk inflasi, harga naik,” terang Project Coordinator pada Development Data Group Bank Dunia Raka Banerjee saat berbincang di The Development Podcast edisi 21 Juli, dikutip dari laman worldbank.org, Senin (31/10/2022).
“Dan pada dasarnya ketika Anda menyatukan keduanya, pertumbuhan yang melambat dikombinasikan dengan kenaikan harga, Anda mengalami stagflasi,” imbuh dia.
Belum lama ini, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF mengingatkan akan meningkatnya potensi risiko resesi. Kedua lembaga keuangan internasional pun kompak memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2023 menjadi 2,7% (IMF) dan 1,9% (Bank Dunia).
Bank Dunia menyebut perlambatan dalam kegiatan ekonomi saat ini merupakan yang paling tajam dalam 80 tahun terakhir.
Terkait inflasi, lembaga bermarkas di Washington DC Amerika Serikat (AS) itu juga memperkirakan inflasi global bakal memuncak tahun ini, sebelum akhirnya turun ke kisaran 4-5% di 2023.
Sebagai catatan pada April 2022 lalu inflasi global berada di angka 7,8% dan mencapai 9,4% di sejumlah negara berkembang dan ekonomi berkembang.
“Itu yang tertinggi sejak 2008. Dan jika Anda melihat ekonomi (negara) maju, ini adalah yang tertinggi yang pernah kita lihat sejak 1982,” ungkap Raka.
Berurusan dengan inflasi yang tinggi saja sudah rumit, dengan stagflasi tentu saja jauh lebih rumit. Para ahli pun menyebut perpaduan antara inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lemah ini sebagai masalah yang sulit diatasi.
“Ini (stagflasi) merupakan perpaduan dari semua hal-hal yang tidak Anda inginkan dalam perekonomian,” tukas Raka.
Pernah Terjadi pada Tahun 1970-an
Stagflasi bukanlah fenomena baru. Kondisi ini pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1970-an di Amerika Serikat . Kala itu, Negeri Paman Sam tengah dilanda segudang masalah ekonomi.
Anggaran perang Vietnam yang selangit, runtuhnya perjanjian Bretton Woods, embargo minyak Arab Saudi, merupakan beberapa faktor yang menjadi pemicu.
“Pengiriman minyak yang dihentikan pada saat itu menaikkan harga. Jadi kita memiliki lebih sedikit pasokan, sementara permintaan sama. Imbasnya, biaya hidup naik, pada saat yang sama ekonomi global menderita cukup parah,” beber Raka.
Dengan kondisi tersebut, saat itu Bank Sentral AS Federal Reserve atau The Fed secara agresif memperketat kebijakan moneter, intinya menaikkan suku bunga secara signifikan.
Langkah ini memang mampu mendinginkan ekonomi dan akhirnya inflasi turun, tetapi kenaikan suku bunga yang agresif datang dengan efek samping, resesi, dan meningkatnya pengangguran.
“Pada akhirnya ekonomi memang pulih di AS, tetapi itu sangat menyakitkan dan tentu saja ada banyak penderitaan di luar negeri juga. Banyak negara miskin, pasar negara berkembang, ekonomi berkembang, mengalami krisis utang, terutama pada 1980-an,” tutur Raka.
Penyebab Stagflasi
Seperti hantu lama yang bangkit dari masa lalu, stagflasi kembali menghantui saat ini. Terkait penyebabnya, meskipun tidak persis sama dengan stagflasi tahun 1970-an, terdapat kemiripan dalam hal ekonomi yang menukik tajam ke bawah, inflasi yang meroket, serta krisis pasokan.
Sebagaimana diketahui, perang Rusia-Ukraina telah menambah kerusakan ekonomi yang ditinggalkan oleh pandemi Covid-19 dan menarik lebih keras pada jeda pertumbuhan ekonomi.
Perang menyebabkan dunia gonjang-ganjing, salah satunya terkait ancaman krisis pangan dan energi sehubungan gangguan rantai pasok. Belum lagi harga komoditas seperti minyak mentah yang melejit dan sejumlah embargo. Lonjakan biaya bahan baku menyebabkan inflasi dan membuat orang kekurangan uang untuk dibelanjakan.
“Jadi jika Anda menggabungkan efek rebound pandemi dan perang, kenaikan dua tahun harga energi dan harga pangan, benar-benar sangat, sangat besar. Sebagai perbandingan, ini adalah kenaikan dua tahun terbesar dalam harga energi sejak tahun 1970-an dan kenaikan harga pangan dua tahun terbesar kedua,” ujar Franziska Ohnsorge, Manager of the Prospects Group Bank Dunia, dalam diskusi podcast yang sama.
Tak hanya itu, stagflasi ini juga bisa disebabkan oleh tatanan kebijakan ekonomi yang buruk. Contohnya manakala pemerintah membuat kebijakan yang merugikan industri, regulasi barang, pasar, dan tenaga kerja yang tidak baik akan membuat produksi terhambat, membiarkan uang beredar terlalu cepat, dan imbasnya harga barang meroket.
Ditambah dengan adanya pelemahan laju ekonomi di waktu bersamaan akan menimbulkan bencana yang lebih besar dari sekedar resesi maupun inflasi.
Dampak Stagflasi
Stagflasi tidak bisa ditentukan oleh ambang batas tertentu dan saat ini juga belum ada otoritas ekonomi tunggal yang secara resmi menyatakan apakah stagflasi telah terjadi, tidak seperti periode resesi.
Meski begitu, tanda-tandanya bisa dicermati dari tingginya angka pengangguran, ekonomi yang melemah, dan naiknya harga-harga barang.
Risiko stagflasi meningkat dengan konsekuensi yang berpotensi berbahaya bagi ekonomi berpenghasilan menengah dan rendah.
Franziska menyatakan, stagflasi merupakan sesuatu yang sangat merugikan rumah tangga berpenghasilan rendah. Pasalnya, pertumbuhan yang lambat berarti lapangan kerja yang lebih sedikit dan upah yang lebih rendah.
“Sementara, inflasi yang tinggi berarti pada saat yang sama mengikis nilai riil, daya beli terutama rumah tangga berpenghasilan rendah, yang mengandalkan upah dari pendapatan rumah tangga mereka. Dan itu juga mengikis nilai riil aset mereka karena mereka cenderung tidak mampu melindungi tabungan mereka dari inflasi,” tukasnya.
Di sisi lain, sambung dia, stagflasi ini sangat rawan krisis. Berkaca pada tahun 1970-an, dibutuhkan dua kali lipat suku bunga global menjadi 14% selama enam tahun untuk mengembalikan inflasi ke dalam target.
“Kenaikan sembilan poin persentase dalam tingkat kebijakan moneter AS dalam dua tahun. Itu, ya, memang mengakhiri inflasi, tetapi juga memicu resesi global pada tahun 1982 ketika pendapatan per kapita global turun satu persen. Dan itu kemudian memicu rangkaian krisis utang,” tuturnya.
Tak Ada Formula Pasti untuk Obati Stagflasi
Tidak ada obat yang pasti untuk mengatasi stagflasi. Meski begitu, meningkatkan kegiatan ekonomi menjadi salah satu solusi.
Inflasi tinggi mungkin bisa diobati tapi juga berisiko memicu efek samping lain. Biasanya bank sentral di suatu negara akan mengambil langkah menaikkan suku bunga secara agresif untuk melawan tingginya inflasi. Namun, kebijakan ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya, jika suku bunga diturunkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inflasi akan semakin memburuk. Jadi, seperti makan buah simalakama.
“Obat untuk inflasi tinggi, yang persis seperti yang dilakukan pemerintah sekarang, pengetatan kebijakan dan bank sentral, obat untuk inflasi tinggi menyebabkan efek samping yaitu pertumbuhan yang rendah,” kata Franziska.
Menurut dia, dibutuhkan reformasi struktural, reformasi peningkatan pertumbuhan, dan ini cenderung sangat spesifik untuk setiap negara negara.
“Jadi yang dibutuhkan adalah langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan produktivitas, tetapi apa hal-hal khusus ini sangat tergantung pada kondisi di negara tersebut,” pungkasnya.
Stagflasi merupakan kondisi di mana inflasi dan kontraksi ekonomi terjadi secara bersamaan. Mengutip laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
Sedangkan stagflasi berasal dari kata stagnan dan inflasi, diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang terus melambat disertai dengan kenaikan harga secara terus-menerus.
“Jadi stag- merujuk pada stagnansi. Jadi kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan kemudian -flasi adalah untuk inflasi, harga naik,” terang Project Coordinator pada Development Data Group Bank Dunia Raka Banerjee saat berbincang di The Development Podcast edisi 21 Juli, dikutip dari laman worldbank.org, Senin (31/10/2022).
“Dan pada dasarnya ketika Anda menyatukan keduanya, pertumbuhan yang melambat dikombinasikan dengan kenaikan harga, Anda mengalami stagflasi,” imbuh dia.
Belum lama ini, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF mengingatkan akan meningkatnya potensi risiko resesi. Kedua lembaga keuangan internasional pun kompak memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2023 menjadi 2,7% (IMF) dan 1,9% (Bank Dunia).
Bank Dunia menyebut perlambatan dalam kegiatan ekonomi saat ini merupakan yang paling tajam dalam 80 tahun terakhir.
Terkait inflasi, lembaga bermarkas di Washington DC Amerika Serikat (AS) itu juga memperkirakan inflasi global bakal memuncak tahun ini, sebelum akhirnya turun ke kisaran 4-5% di 2023.
Sebagai catatan pada April 2022 lalu inflasi global berada di angka 7,8% dan mencapai 9,4% di sejumlah negara berkembang dan ekonomi berkembang.
“Itu yang tertinggi sejak 2008. Dan jika Anda melihat ekonomi (negara) maju, ini adalah yang tertinggi yang pernah kita lihat sejak 1982,” ungkap Raka.
Berurusan dengan inflasi yang tinggi saja sudah rumit, dengan stagflasi tentu saja jauh lebih rumit. Para ahli pun menyebut perpaduan antara inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lemah ini sebagai masalah yang sulit diatasi.
“Ini (stagflasi) merupakan perpaduan dari semua hal-hal yang tidak Anda inginkan dalam perekonomian,” tukas Raka.
Baca Juga
Pernah Terjadi pada Tahun 1970-an
Stagflasi bukanlah fenomena baru. Kondisi ini pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1970-an di Amerika Serikat . Kala itu, Negeri Paman Sam tengah dilanda segudang masalah ekonomi.
Anggaran perang Vietnam yang selangit, runtuhnya perjanjian Bretton Woods, embargo minyak Arab Saudi, merupakan beberapa faktor yang menjadi pemicu.
“Pengiriman minyak yang dihentikan pada saat itu menaikkan harga. Jadi kita memiliki lebih sedikit pasokan, sementara permintaan sama. Imbasnya, biaya hidup naik, pada saat yang sama ekonomi global menderita cukup parah,” beber Raka.
Dengan kondisi tersebut, saat itu Bank Sentral AS Federal Reserve atau The Fed secara agresif memperketat kebijakan moneter, intinya menaikkan suku bunga secara signifikan.
Langkah ini memang mampu mendinginkan ekonomi dan akhirnya inflasi turun, tetapi kenaikan suku bunga yang agresif datang dengan efek samping, resesi, dan meningkatnya pengangguran.
“Pada akhirnya ekonomi memang pulih di AS, tetapi itu sangat menyakitkan dan tentu saja ada banyak penderitaan di luar negeri juga. Banyak negara miskin, pasar negara berkembang, ekonomi berkembang, mengalami krisis utang, terutama pada 1980-an,” tutur Raka.
Penyebab Stagflasi
Seperti hantu lama yang bangkit dari masa lalu, stagflasi kembali menghantui saat ini. Terkait penyebabnya, meskipun tidak persis sama dengan stagflasi tahun 1970-an, terdapat kemiripan dalam hal ekonomi yang menukik tajam ke bawah, inflasi yang meroket, serta krisis pasokan.
Sebagaimana diketahui, perang Rusia-Ukraina telah menambah kerusakan ekonomi yang ditinggalkan oleh pandemi Covid-19 dan menarik lebih keras pada jeda pertumbuhan ekonomi.
Perang menyebabkan dunia gonjang-ganjing, salah satunya terkait ancaman krisis pangan dan energi sehubungan gangguan rantai pasok. Belum lagi harga komoditas seperti minyak mentah yang melejit dan sejumlah embargo. Lonjakan biaya bahan baku menyebabkan inflasi dan membuat orang kekurangan uang untuk dibelanjakan.
“Jadi jika Anda menggabungkan efek rebound pandemi dan perang, kenaikan dua tahun harga energi dan harga pangan, benar-benar sangat, sangat besar. Sebagai perbandingan, ini adalah kenaikan dua tahun terbesar dalam harga energi sejak tahun 1970-an dan kenaikan harga pangan dua tahun terbesar kedua,” ujar Franziska Ohnsorge, Manager of the Prospects Group Bank Dunia, dalam diskusi podcast yang sama.
Tak hanya itu, stagflasi ini juga bisa disebabkan oleh tatanan kebijakan ekonomi yang buruk. Contohnya manakala pemerintah membuat kebijakan yang merugikan industri, regulasi barang, pasar, dan tenaga kerja yang tidak baik akan membuat produksi terhambat, membiarkan uang beredar terlalu cepat, dan imbasnya harga barang meroket.
Ditambah dengan adanya pelemahan laju ekonomi di waktu bersamaan akan menimbulkan bencana yang lebih besar dari sekedar resesi maupun inflasi.
Dampak Stagflasi
Stagflasi tidak bisa ditentukan oleh ambang batas tertentu dan saat ini juga belum ada otoritas ekonomi tunggal yang secara resmi menyatakan apakah stagflasi telah terjadi, tidak seperti periode resesi.
Meski begitu, tanda-tandanya bisa dicermati dari tingginya angka pengangguran, ekonomi yang melemah, dan naiknya harga-harga barang.
Risiko stagflasi meningkat dengan konsekuensi yang berpotensi berbahaya bagi ekonomi berpenghasilan menengah dan rendah.
Franziska menyatakan, stagflasi merupakan sesuatu yang sangat merugikan rumah tangga berpenghasilan rendah. Pasalnya, pertumbuhan yang lambat berarti lapangan kerja yang lebih sedikit dan upah yang lebih rendah.
“Sementara, inflasi yang tinggi berarti pada saat yang sama mengikis nilai riil, daya beli terutama rumah tangga berpenghasilan rendah, yang mengandalkan upah dari pendapatan rumah tangga mereka. Dan itu juga mengikis nilai riil aset mereka karena mereka cenderung tidak mampu melindungi tabungan mereka dari inflasi,” tukasnya.
Di sisi lain, sambung dia, stagflasi ini sangat rawan krisis. Berkaca pada tahun 1970-an, dibutuhkan dua kali lipat suku bunga global menjadi 14% selama enam tahun untuk mengembalikan inflasi ke dalam target.
“Kenaikan sembilan poin persentase dalam tingkat kebijakan moneter AS dalam dua tahun. Itu, ya, memang mengakhiri inflasi, tetapi juga memicu resesi global pada tahun 1982 ketika pendapatan per kapita global turun satu persen. Dan itu kemudian memicu rangkaian krisis utang,” tuturnya.
Tak Ada Formula Pasti untuk Obati Stagflasi
Tidak ada obat yang pasti untuk mengatasi stagflasi. Meski begitu, meningkatkan kegiatan ekonomi menjadi salah satu solusi.
Inflasi tinggi mungkin bisa diobati tapi juga berisiko memicu efek samping lain. Biasanya bank sentral di suatu negara akan mengambil langkah menaikkan suku bunga secara agresif untuk melawan tingginya inflasi. Namun, kebijakan ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya, jika suku bunga diturunkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inflasi akan semakin memburuk. Jadi, seperti makan buah simalakama.
“Obat untuk inflasi tinggi, yang persis seperti yang dilakukan pemerintah sekarang, pengetatan kebijakan dan bank sentral, obat untuk inflasi tinggi menyebabkan efek samping yaitu pertumbuhan yang rendah,” kata Franziska.
Menurut dia, dibutuhkan reformasi struktural, reformasi peningkatan pertumbuhan, dan ini cenderung sangat spesifik untuk setiap negara negara.
“Jadi yang dibutuhkan adalah langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan produktivitas, tetapi apa hal-hal khusus ini sangat tergantung pada kondisi di negara tersebut,” pungkasnya.
(ind)